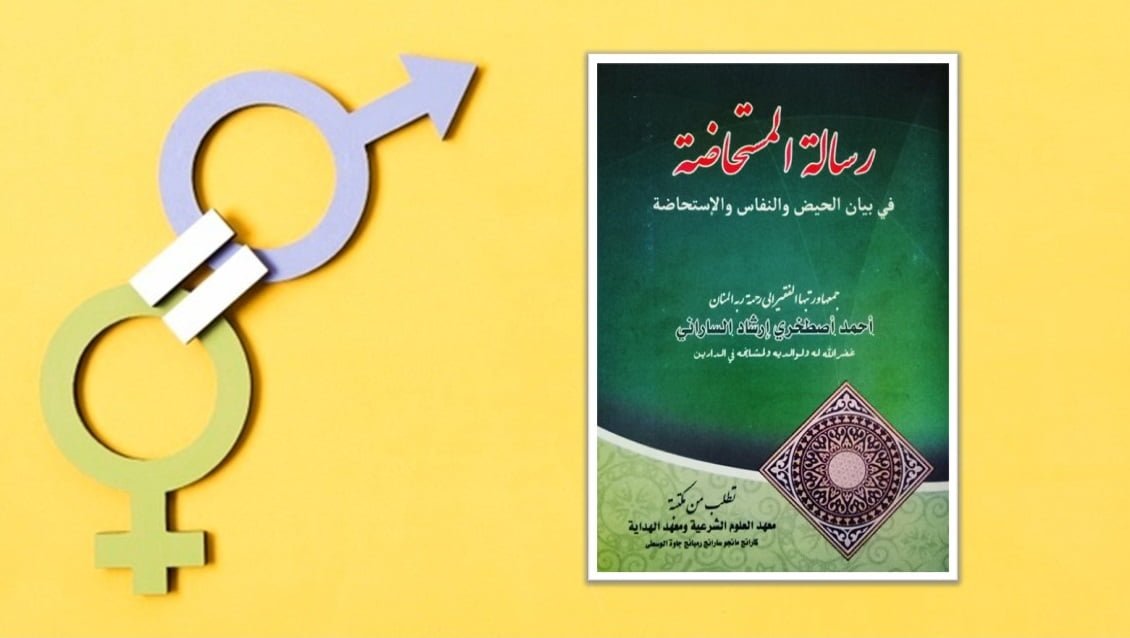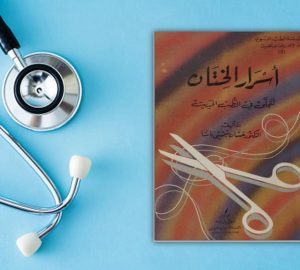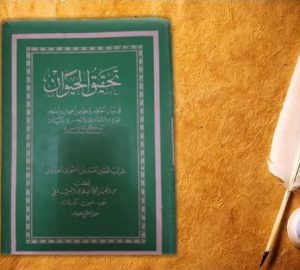Isu gender equality sering kali menyudutkan masyarakat pesantren pada posisi ‘kontra’ kesejahteraan kaum Hawa. Rujukan terhadap turats karya ulama salaf, yang konon diproduksi dalam budaya patriarki, boleh jadi alasan utama masalah ini.
Namun begitu, klaim ketidakberpihakan kalangan pesantren terhadap gender equality ini agaknya perlu dipertanyakan ulang. Benarkah demikian?
Dalam tulisan ini, izinkan penulis berbagi hasil pembacaan terhadap sebuah karya yang lahir dari tradisi pesantren. Sebuah karya dari literatur hukum Islam, fikih kewanitaan berjudul Risalah al-Mustahadhah (Risalatul Mustahadhah).
Kitab Risalah al-Mustahadhah merupakan karya tulis KH. Ahmad Usthukhri Irsyad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangmangu, Sarang, Rembang. Beliau merupakan menantu dari Allahu yarham KH. Muthi’ Ma‘shum, salah satu masyayikh Pondok Sarang.
Selain menjadi pengasuh di Al-Hidayah, Mbah Usthukhri, sapaan akrab beliau, juga aktif mengajar di Madrasah Ghazaliyyah Syafi‘iyyah (MGS) Karangmangu.
Kitab Risalah al-Mustahadhah sendiri sejatinya memiliki nama “Al-Mustahadhah”, sebagaimana KH. Abdurrochim Ahmad memberikan nama kitab tersebut dalam catatan pengantarnya.
Imbuhan ‘Risalah’ pada bagian awal menunjukkan bahwa, secara kuantitas, kitab ini berisi materi yang cukup sederhana, ulasan dasar, dan tidak membutuhkan halaman yang begitu banyak.
Masih dalam catatan Mbah Him, begitu para santri biasa menyebut KH. Abdurrochim Ahmad, disebutkan bahwa kitab ini sedianya ditujukan kepada kalangan santri putri Madrasah Putri Ghozaliyyah (MPG) Karangmangu.
Kitab tersebut semacam diktat dari guru untuk muridnya. Namun harapannya, dapat bermanfaat secara luas bagi setiap insan muslim dan muslimah.
Poin gender equality dalam Risalah al-Mustahadhah ada pada bagaimana karya tersebut mampu memberikan kontribusi panduan hukum bagi kaum hawa. Kesetaraan pada aspek hukum inilah yang menjadi perhatian serius kalangan pesantren.
Aspek tersebut berkaitan dengan bentuk pengejawantahan nyata atas firman Allah, Surat Al-Hujurat ayat 13,
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (QS. Al-Hujurat: 13)
Aspek ketakwaan yang menjadi nilai aksentuasi ayat di atas dalam tradisi Islam secara umum dipahami sebagai menjalankan setiap perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dua hal yang tidak akan mungkin tercapai manakala tidak didasari dengan fondasi ilmu dan pengetahuan yang memadai, termasuk aspek hukum kewanitaan di dalamnya.
Bukti adanya perhatian kaum pesantren terhadap kebutuhan hukum kewanitaan adalah ditulisnya kitab Risalah al-Mustahadhah. Hal ini mengingat minimnya keberadaan karya serupa yang disusun secara eksklusif, satu hal yang juga disampaikan Mbah Usthukhri dalam mukadimahnya.
Memang pembahasan mengenai fikih kewanitaan telah banyak ditulis, namun karya kitab cetak yang dihasilkan jarang yang diterbitkan secara mandiri dan terpisah. Dengan kata lain karya tersebut selalu menjadi satu dengan pembahasan yang lain.
Hal ini tentu menjadi kendala bagi sebagian kalangan terkait dengan detail dan kerumitan penjelasan atau mungkin budget pembelian.
Nah, yang cukup menarik terkait gender equality dalam fikih kewanitaan semacam ini adalah kehadiran kaum pria sebagai mu’allif (pengarang) kitab. Apabila menilik konten pembahasan yang disajikan, mestinya karya semacam ini ditulis dan disusun oleh mu’allif perempuan. Sehingga cakupan pembahasan di dalamnya dapat lebih komprehensif. Namun, nyatanya tidak demikian.
Risalah al-Mustahadhah ini misalnya, ditulis oleh Kiai Usthukhri. Atau mungkin karya yang lain seperti Al-Inba’ ‘an Masa’il al-Dima’ yang ditulis oleh Mu‘adz Fadlil. Ini berarti bahwa tidak benar jika masyarakat pesantren tidak mengindahkan kesejahteraan kaum hawa melalui gender equality.
Terlebih jika masalah kepenulisan ini diperluas pada aspek pengkajian. Tidak sedikit majelis-majelis pengajian yang bandongan yang diselenggarakan dan diikuti oleh santri-santri putra, yang beberapa majelis tersebut justru digelar secara sukarela dan tidak mengikat secara wajib.
Hal ini juga berarti bahwa kesadaran terhadap kesejahteraan kaum hawa juga telah dimiliki para santri putra. Hingga praktis gender equality tidak hanya mencakup para kiai sebagai pemateri, tetapi juga mencakup para santri putra yang menjadi praktisi pengkaji.
Alhasil, dengan beberapa fakta yang telah penulis kemukakan sebelumnya, keberpihakan kaum santri terhadap budaya patriarki dan penolakan terhadap gender equality agaknya tidak sepenuhnya dapat dibenarkan.
Meski penulis yakin, banyak di antara pembaca yang tetap keukeuh dengan stigma negatif ini terhadap kaum santri sarungan. Wallahu a‘lam bi al-shawab.