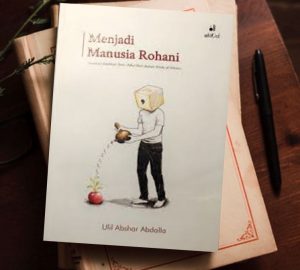Pada Rabu, 15 April, menjelang subuh waktu Sydney Australia, saya mendapat sebuah pertanyaan dari seseorang melalui layanan pesan media sosial. Pertanyaan tersebut soal beredarnya video berisi pembacaan puisi paskah karya Ulil Abshar Abdalla yang dibacakan oleh sejumlah anak (muslim) yang diduga tayang di TVRI.
Melalui akun twitter, Gus Ulil, begitu ia akrab disapa, mengkonfirmasi bahwa puisi tersebut memang karyanya yang ditulis tujuh tahun silam. Sebagaimana dilansir Republika (15/4), pihak TVRI juga sudah mengkonfirmasi bahwa tuduhan penayangan puisi paskah itu adalah hoaks.
Kendati sudah dikonfirmasi oleh pihak-pihak terkait, saya tetap mencoba untuk menjawab tanggapan pengirim pesan yang baginya mengandung sejumlah kontroversi. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi perbincangan sejumlah orang.
Pertama, adanya kecurigaan bahwa puisi itu akan merusak keimanan anak-anak (muslim). Kedua, puisi tersebut berpotensi memecah belah umat. Ketiga, pro-kontra puisi kaitannya dengan penistaan agama Islam.
Berangkat dari tiga poin di atas, tulisan ini mencoba untuk mengurai kontroversi di balik puisi tersebut, serta memberikan cara pandang yang lebih produktif dalam merespon, khususnya bagi kalangan orangtua dan guru.
Menikmati Puisi yang Tak Mudah
Mulanya saya berpikir sangat sederhana bahwa penampilan tersebut hanyalah sebuah karya seni. Pada perspektif ini, kita bisa menikmatinya dengan mengambil sisi keindahan diksi, terampil, pembawaan yang bersahaja, serta proses produksi yang sederhana tapi menawan.
Apalagi di tengah krisis Pandemi Covid-19, menikmati puisi tersebut bisa sebagai makanan jiwa atau setidaknya menjadi hiburan. Tanggapan sederhana ini sepertinya belum memuaskan penanya yang kemudian mengirimkan beberapa fakta lain, seperti munculnya logo Nahdlatul Ulama (NU) pada kopiah/peci anak laki-laki yang membacakan puisi dan adanya redaksi dalam puisi itu yang menyebut-nyebut nama Jesus.
Melihat beberapa fakta yang disampaikan, ternyata keindahan diksi, kedalaman makna, serta momentum paskah adalah hal penting yang luput dari perhatian sebagian penonton. Mereka yang mengirim pesan kepada saya adalah orang yang memilih sudut pandang lain untuk dijadikan perhatiannya.
Dalam keyakinan saya, orang tipe di atas sangat rawan untuk memproblematisir puisi karya Gus Ulil tersebut. Faktanya penonton tipe ini lebih memberikan perhatian pada simbol berupa gambar serta kata-kata yang mencolok, seperti logo NU dan kata Jesus.
Simbol NU yang identik dengan Islam dan kata Jesus yang merujuk pada imam kristiani telah menjadi pusat perhatian. Mereka tidak salah, karena berbagai simbol telah berebut makna dalam kasus puisi paskah yang dibacakan anak kecil berkopiah NU itu.
Pada saat demikian, pengalaman hidup, referensi, serta situasi yang melingkupi penonton akan memberikan sumbangsih besar dalam proses mencerna dan mengambil makna sebuah “show”. Pada kontestasi makna dan audience itulah persoalan bermula.
Sikap berbeda justru ditunjukkan Gus Ulil selaku penulis puisi. Meski diserang hoaks atas penayangan di televisi, ia justru malah senang bahwa puisi yang sudah beredar setiap perayaan Paskah sejak tujuh silam itu masih banyak yang suka.
Belakangan, Gus Ulil juga menulis sebuah klarifikasi di sebuah media online. Selain dari Gus Ulil, saya juga mendapatkan informasi dari seorang kiai pengasuh pesantren, dimana video tersebut diproduksi.
Kiai tersebut menjelaskan produksi pembacaan puisi itu sengaja dibuat untuk memberikan penghiburan kepada saudara-saudara Nasrani. Beban umat beragama kini sedang sangat berat, bolehlah kiranya kita berikan penghiburan untuk sedikit meringankan. Demikian kira-kira maksud dari produksi video tersebut.
Berkenaan dengan kontroversi soal simbol dan puisi, pemikir asal Perancis Roland Barthes, menulis sebuah esai berjudul “La mort de l’auteur“, dalam Bahasa Indonesia mungkin berarti matinya penulis.
Esai yang dibuatnya tahun 1967 itu sangat popular dalam dunia analisa wacana. Perdebatan soal apa yang dimaksud Barthes dengan matinya sang penulis sampai sekarang pun masih terjadi. Pesan penting dari tulisan Barther adalah setelah karya beredar, maka ia punya takdirnya sindiri, tanpa bergantung pada siapa yang menulis atau siapa memroduksi karya tersebut. Demikian pula yang terjadi dalam konteks puisi paskah Gus Ulil yang dibacakan santri NU dari Bogor tersebut.
Gus Ulil mengambarkan betapa tulisan itu muncul pada momen sakral (tajallyat) dengan pergulatan pemikiran yang tidak main-main. Hal ihwal bagaimana sajak, atau puisi itu dibuat bisa dibaca di media alif.id.
Demikian juga para santri pembaca puisi tersebut adalah anak-anak belia yang ingin memberikan kado terbaiknya demi sebuah persaudaraan sesama anak bangsa. Namun demikian, jika pada akhirnya karya itu kemudian diberikan tafsir yang berbeda dengan keinginan penulis, maka begitulah takdir sebuah karya, ia terlepas dari pemiliknya.
Menyikapi hal ini, saya mengusulkan sebuah sikap produktif. Reading like a historian, sebuah kurikulum membaca kritis yang dikembangkan oleh Stanford History Education Group di Amerika, membuat saya begitu berkesan.
Kurikulum ini mengajak anak-anak untuk mempelajari sebuah karya dengan mulai melihat sejauh mana sumber sebuah karya itu valid. Setelah anak-anak dapat melakukan validasi sumber, kemudian diajak untuk memahami konteks dimana karya itu lahir. Setelah keduanya dilakukan kemudian mereka ditantang untuk membuat sebuah klaim sejarah.
Tahapan terakhir ini menurut saya sangat menarik, karena anak-anak diajarkan untuk memiliki pandangan sendiri tentang peristiwa tertentu. Mereka sekaligus belajar bagaimana membangun argumen yang kokoh dengan sumber yang valid serta melalui proses kontekstualisasi.
Peristiwa anak-anak ‘terlanjur’ menonton pembacaan puisi adalah “the point of no return”. Mereka telah menontonnya dan waktu tidak bisa kita putar kembali. Hal yang bisa kita lakukan adalah memberikan memori positif bagi anak-anak yang terlanjur menonton.
Telepas dari kontroversi puisi Gus Ulil, saya ingin mengajak kepada orang tua atau guru, yang merasa menyesal karena putra putrinya atau anak didiknya menonton tayangan tersebut, untuk berani mencoba hal baru. Mari kita ajak anak-anak untuk menonton sekali lagi, kemudian ceritakan kepada mereka mengenai konteks puisi itu hadir, termasuk ajaklah anak anak belajar dari kreativitas dua santri pembaca puisi tersebut.
Marilah kita mulai membuka diri untuk berbagai kemungkinan klaim yang akan diberikan anak-anak kita. Melalui proses ini saya yakin anak-anak akan mengalami proses belajar yang menyenangkan dan memberikan memori indahnya perbedaan dan sikap saling menghargai. Selamat mencoba.