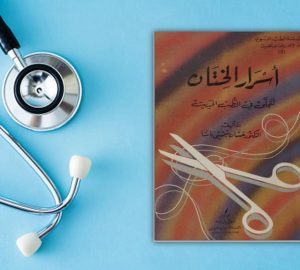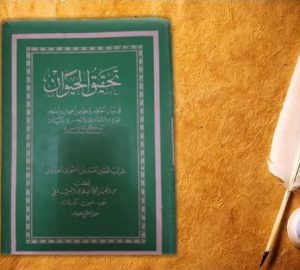Dua Kitab untuk Sang Sultan: Hubungan Kerajaan Banten dan Mekah Abad ke-17
Bagi banyak kerajaan di nusantara masa lalu, kuasa politik dipandang bukan saja tentang urusan dunia. Perpanjangan tangan dari kuasa Tuhan dipandang nilai penting di dalamnya. Tata-pengaturan adalah mandatori ilahiah yang meliputi kesatuan jagad dunia dan akhirat. Rakyat harus diyakinkan bahwa raja dan kerajaan mereka telah sah dalam dua semesta ini. Bagi semesta duniawi, raja tertentu melalui musyawarah dan “intrik” di tingkat elit kerajaan. Namun bagaimana pengesahan di semesta akhirat dicari?
Kerajaan Banten di abad ke-17 menjadi pionir dalam usaha mencari pengesahan ini di luar dari dirinya sendiri. Pengiriman utusan ke “Rumah Tuhan” adalah pencarian status maha penting kerajaan. Gelar “sultan” yang sah sebagai wakil dari kekhalifahan Turki Utsmani diperoleh. Namun lebih dari sekedar gelar, dari Mekah utusan juga membawa kitab-kitab yang khusus dipersembahkan untuk pemangku gelar sultan yang sah pertama di nusantara.
Ada dua kitab yang merupakan buah dari pertanyaan Sultan Abul Mafakhir Abdul Qadir (bertahta 1596-1647) yang dikenal dengan Pangeran Ratu. Kelahiran dua kitab ini menunjukkan perhatian Sang Sultan terhadap keilmuan tasawuf di masa itu. Bukti relasi luas kesultanan Banten dengan pusat keilmuan Islam di Mekah. Jalinan yang melengkapi kepentingan politik seperti dalam artikel di tirto “Pangeran Ratu Abdulmafakhir Raja Banten, Sultan “Resmi” Pertama di Nusantara” (https://tirto.id/raja-banten-sultan-resmi-pertama-di-nusantara-crmp). Kitab ditulis oleh ulama kenamaan di pusat dunia Islam.
Syaikh Ibn ‘Alan bernama lengkap Muhammad ‘Ali bin Muhammad ‘Alan bin Ibrahim al-Bakri ash-Shiddiqi asy-Syafi’i (1588-1647). Beliau adalah seorang mufasir, muhaddis, faqih mazhab Syafi’i, dan seorang sufi dari Mekah. Beliau hidup pada rentang waktu dari akhir abad ke-16 hingga paruh awal abad ke-17. Beliau memiliki banyak sekali karya yang menunjukkan penguasaaannya atas beragam cabang keilmuan Islam.
Dalam al-A‘lam Qamus Tarajim karya Khoiruddin az-Zirkili (J. VI, h. 293), kita dapat menemukan daftar beberapa karyanya yang sejauh ini telah ditemukan. Dalam bidang tafsir beliau menulis Dhiya’us Sabil (Lentera Penerang Jalan). Dalam bidang hadis karyanya yang amat terkenal adalah Dalilul Falihin Li Thuruqi Riyadhish Shalihin (Petunjuk Orang-orang Yang Bahagia Menuju Taman Orang-orang Saleh). Kitab ini adalah syarah setebal 8 jilid atas kitab Riyadhush Shalihin karya Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi.
Dalam bidang tasawuf dia menulis karya Al-Mawahib al-Fathiyyah ala ath-Thariqah al-Muhammadiyyah. Sedangkan dalam bidang usul fiqih, beliau memiliki karya at-Talaththuf Fil Wushul Ilat Ta’arruf. Tidak ketinggalan, beliau juga menulis dalam bidang kajian bahasa yaitu Ithaful Fadhil bi Fi’lil Mabni Li Ghairil Fa’il. Serta beberapa kitab lainnya dalam bidang sejarah dan syair. Karya-karya tersebut sebagian telah diterbitkan, namun masih banyak di antara yang masih berupa manuskrip yang perlu penelitian filologis untuk menjadikannya siap diterbitkan.
Khoiruddin az-Zirkili melewatkan dua kitab penting yang ditulis untuk Sultan Abul Mafakhir Abdul Qadir. Kitab pertama berjudul Al-Mawahib ar-Rabbaniyyah ‘Anil As’ilah al-Jawiyyah. Sultan Abul Mafakhir Abdul Qadir memberikan beberapa pertanyaan terkait kuasa. Sebuah hadis dalam kitab Nashihatul Muluk yang ditulis Syaikhul Islam Imam al-Ghazali menjadi pembuka. Apa maksud dari seorang raja akan dimasukkan ke dalam neraka jika menghukum lebih berat atau lebih ringan dari ketetapan hukum Tuhan? Demikian kira-kira inti pertanyaannya. Kekhawatiran akan masuk ke dalam golongan raja yang masuk neraka terlihat. Dan atas pertanyaan itu, Syaikh Ibn ‘Alan dengan bijak menjawab sebagaimana terekam dalam sebuah manuskrip di Perpustakaan Nasional Indonesia.
Manuskrip A 105 koleksi Perpustakaan Nasional menyimpan teks penting ini. Kitab ini telah disunting oleh Ais Farida (2001) sebagai tugas skripsi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Syaikh Ibn ‘Alan menjelaskan bahwa maksud hadis itu adalah kewajiban adil bagi seorang penguasa. Dengan mengutip hadis lain Syaikh Ibn ‘Alan menjelaskan bahwa ketidakadilan adalah perusak kekuasaan bangsa-bangsa terdahulu. Jika seorang yang punya kedudukan melakukan kesalahan, bahkan kesalahan besar seperti korupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi misalnya, maka dia tidak dihukum. Namun, jika seorang dari rakyat biasa melakukan kesalahan kecil, hanya mengambil satu buah coklat dari kebun perusahaan pemerintah misalnya, maka hukum ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Bahkan sang Nabi agung mengatakan bahwa seandainya putrinya Fatimah mencuri maka sang Nabi sendiri yang akan memotong tangannya.
Dari analisis terhadap kitab ini, Agus Prasetyo (2019) menulis skripsi di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kesimpulan dari skripsinya adalah bahwa Sultan Abul Mafakhir Abdul Qadir adalah seorang Raja Sufi. Hal ini diperkuat dengan fakta keseriusan Sultan mengkaji dan mengamalkan ajaran al-Insan al-Kamil yang diulas oleh Abdul Karim al-Jili.
Namun skripsi terakhir melewatkan satu data penting. Bukan hanya Sang Sultan meminta agar kitab al-Insan al-Kamil disalin, namun juga beliau meminta penjelasan atas kitab tersebut kepada ulama yang ahli di bidang ini. Kitab kedua yang ditulis untuk Sultan Banten. Syaikh Ibn ‘Allan menulis jawaban atas pertanyaan itu dan menamainya dengan Raf’ul Hijab ‘An ‘Ara’is Khamsatil Abwab. Manuskrip kitab ini tersimpan di perpustakaan Leiden Belanda dengan kode Or. 5660 pada halaman 66v hingga 73v.
Manuskrip ini sendiri mengandung beragam teks sufistik dalam bahasa Arab dengan sebagian diberikan makna gandul ala pesantren dalam bahasa Jawa. Di dalamnya kita bisa menemukan teks kitab Sababul Kasyfi wal Bayani Lima Yarahu al-Muhtadhar Bil ‘Iyan (h. 1v-5r) yang dinisbatkan kepada Syaikh Abdurrauf Singkel. Ini merupakan penjelasan penulisnya atas beredarnya ajaran syahadat kematian di masyarakat Jawa. Untuk lebih jelas soal syahadat sekarat ini bisa dilihat pada tulisan “Islamisasi Jawa: Mati Bersama Cahaya” (https://alif.id/read/nur-ahmad/islamisasi-jawa-mati-bersama-cahaya-b206723p/).
Teks lain yang ada di manuskrip ini adalah jawaban dari Syaikh Ibrahim al-Kurani (w. 1690) kepada masyarakat Nusantara atas kejadian di mana seorang syaikh yang terkenal alim namun menyatakan pernyataan yang secara lahiriahnya amat bertentangan dengan syariah. Ahmad Ginanjar Sya’ban telah memberikan ulasan menarik dalam “Al-Maslakul Jali: Fatwa Ulama Madinah atas Polemik Siti Jenar di Nusantara (1674)” (https://alif.id/read/ahmad-ginanjar/al-maslakul-jali-fatwa-ulama-madinah-atas-polemik-siti-jenar-di-nusantara-1674-b210014p/). Landasan dari ulasannya adalah sebuah edisi cetak yang didasarkan pada manuskrip yang tersimpan Perpustakaan Nasional Tunisia di Tunis. Manuskrip kita menunjukkan bahwa kitab ini tersebar luas dan dikaji juga di Jawa. Hal ini disimpulkan dari makna ala pesantren yang digunakan.
Teks Raf’ul Hijab ‘An ‘Ara’is Khamsatil Abwab menjadi salah satu kandungannya. Kitab ini sebagaimana disebutkan dalam mukadimah, ditulis oleh Syaikh Ibn ‘Alan sebagai jawaban atas pertanyaan yang disampaikan dalam lembaran kertas surat dari Abul Ma’ali Ahmad, putera mahkota yang naik tahta pada 1647-1651, dan ayahnya Sultan Abul Mafakhir Abdul Qadir. Dari mukadimah kitab kita bisa menduga bahwa keduanya meminta penjelasan mengenai lima bab dari kitab al-Insan al-Kamil karya Abdul Karim al-Jili (w. 1424). Lima bab ini dimulai dari bab 50 tentang Ruhul Qudus hingga bab 54 tentang al-Wahm. Dalam menjelaskan bab ini, Syaikh Ibn ‘Alan memenggalnya menjadi fragmen-fragmen kecil lalu memberikan penjelasan atas fragmen tersebut. Kitab berisi ide sufi yang bersifat filosofi ini dijelaskan dengan ungkapan yang lebih mudah.
Dua kitab menunjukkan bahwa bukan hanya status sultan namun juga kitab-kitab yang dibawa pulang utusan dari Mekah. Bukan hanya relasi politik, namun juga jaringan keilmuan antara Hijaz dan Nusantara pada abad ke-17 terkukuhkan. Mereka juga menunjukkan bahwa diskursus keislaman di Nusantara bukanlah keislaman yang pinggiran. Namun diskursus yang menandai jejaring kompleks yang menghubungkan praktek-praktek islam lokal di banyak belahan dunia Islam, termasuk dari nusantara, didiskusikan di pusat dunia Islam di Mekah. Bagi Sultan, kekuasaan adalah wadah untuk mewujudkan keadilan bukan hanya di dunia ini, namun juga berdampak pada kehidupan di akhirat. Demikian.