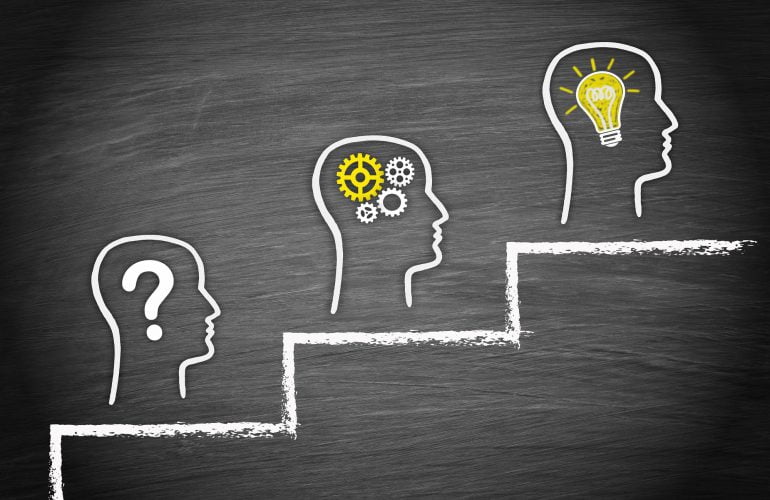Berbicara soal rasionalitas dalam ajaran Islam, tentunya perlu untuk menyebut sebuah hadis berikut:
الدِّيْنُ هُوَ الْعَقْلُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَاعَقْلَ لَهُ
“Agama adalah akal, dan tidak dianggap beragama orang yang tidak memiliki akal”. (HR. An-Nasai)
Dalam bukunya Al-Kuny dan beberapa periwayat hadis yang lain menyatakan bahwa hadis tersebut cacat dari sisi periwayatan. Namun demikian, sekalipun hadis ini cacat dari sisi periwayatan, namun apakah makna hadis tersebut sepenuhnya salah?
Sebelum menguraikan lebih jauh, langkah awalnya adalah memahami kesepakan para ulama terkait makna akal. Hal ini mengingat begitu beragamnya penafsiran-penafsiran ulama terkait makna akal itu sendiri.
Seorang sufi besar asal Baghdad, Al-Harist bin Asad Al-Muhasibi, pernah mengulas makna akal dalam karyanya yang berjudul Ma’iyatul aql wa maknâhu wa ikhtilâfu al-nâs fîhi:
“Akal adalah insting yang diciptakan Allah swt kepada banyak makhluk-Nya, yang (pada hakikatnya) tidak tejangkau oleh hamba-hamba-Nya, baik melalui (pengajaran) sebagian terhadap sebagian yang lain maupun secara berdiri sendiri. Mereka semua tidak dapat menjangkaunya dengan pandangan, indra, dan rasa. Denga akal itulah hamba-hamba Allah mengenal-Nya”.
Pendapat di atas juga senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh Imam Ibnu Hambal dan beberapa ulama salaf lainnya.
Adalagi yang berpendapat bahwa akal terdiri dari dua macam. Pertama, akal yang merupakan anugerah Allah. Kedua, akal yang dapat diperoleh dan dikembangkan oleh manusia melalui penalaran, pendidikan, dan pengalaman hidup. Ini yang kemudian dinamakan al-‘aql al-mukawwin dan al-‘aql al-mukawwan oleh pemikir Maroko, Muhammad Abid Al-Jabiri.
Imam Abu Hamid Al-Ghazali, seorang teolog dan sufi besar, dalam kitab Ar-Risalah al-Laduniyyah mengingatkan bahwa akal memiliki banyak sekali pengertian. Akal bisa berarti kekuatan potensial yang hanya dimiliki oleh umat manusia.
Bagi Imam Al-Ghazali, akal bisa berarti pengetahuan yang dapat dicerna oleh seorang anak dan menuju dewasa, lalu bisa juga diartikan pengetahuan yang diperoleh pengetahuan seseorang berdasarkan pengalamannya.
Dalam literatur-literatur tasawuf, akal juga terkadang dimaknai dengan al-qalb (hati), atau ar-rûh (jiwa). Pendapat ini yang kiranya sejalan dengan pendapat Al-Muhasibi di atas. Sedangkan para pakar logika memaknainya dengan al-quwwah al-natiqiyyah (potensi untuk menalar).
Berangkat dari beberapa pengertian di atas, kiranya bisa kita tarik kesimpulan bahwa makna akal adalah daya fikir yang bila digunakan dapat mengantarkan seseorang untuk mengerti dan memahami persoalan-perosoalan yang difikirkannya.
Manusia adalah makhluk yang dianugerahi potensi untuk berpikir. Sehingga sudah sewajarnya untuk mengungkap makna kebenaran dengan kekuatan nalar yang dimilikinya. Tetapi, apakah semua persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dapat dipecahkan hanya dengan akal saja?
Islam hadir sebagai sebuah agama yang menuntun umat manusia pada dua dimensi sekaligus. Sekalipun kedua dimensi ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan; dimensi fisika (physical dimension) dan dimensi metafisika (metaphysical dimension).
Rasionalitas ajaran agama Islam bukan berarti menempatkan posisi akal sebagai bak seorang “raja”. Ini sebabnya, sekalipun manusia itu berakal, tetapi ajaran Islam dan beberapa ajaran agama lainnya manusia tetap membutuhkan seorang Nabi atau Rasul sebagai petunjuk untuk menuju jalan kebenaran.
Permasalahan qadha, qadar, dan hubungan antara kehendak Tuhan dan perbuatan manusia misalnya, demikian ini telah dibahas secara panjang lebar oleh para penganut setiap agama. Begitu pula para pemikir; baik dalam sudut pandang filsafat Yunani, China, Arab, India, atau selainnya.
Hal ini juga telah dibahas oleh Socrates, Plato dan filsuf-filsuf setelahnya hingga para pemikir abad ini. Meskipun demikian, dari pendapat-pendapat tersebut belum ada yang mampu memberikan jawaban yang tuntas lagi memuaskan semua akal.
Berbeda dengan dimensi metafisika yang berada di luar jangkauan akal manusia. Dalam ranah dimensi fisika, syariat justru menuntut umat manusia untuk memanfaatkan akal sebaik mungkin. Berkali-kali Al-Qur’an menyindir manusia dengan potongan ayat, afalâ ta’qilûn (أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ).
Di sisi lain, sikap rasional dan rasionalitas dalam artian yang positif menuntut adanya pertanggungjawaban. Apabila sebuah keyakinan keberagamaan atau moral mulai dipertanyakan, dalam konteks seperti ini seseorang dituntut untuk bersikap rasional. Artinya, seseorang berusaha untuk memastikan kembali kepercayaan atau sikapnya secara argumentatif. Namun, hal ini juga bukan berarti kita harus memahami segala sesuatu semau sendiri.
Terhadap serangan argumentatif, kita bisa saja mengambil sikap begini misalnya: “Saya sudah mempertimbangkan argumentasi anda; argumentasi ini menarik dan saya tidak dapat menanggapi seluruhnya. Namun, saya menganggapnya belum puas. Maka, selama anda tidak dapat mengajukan argumen lebih meyakinkan, saya akan tetap seperti sekarang”. Sikap seperti ini merupakan contoh kecil dari sikap rasionalitas dalam Islam.
Jadi, beragama secara dewasa menuntut kita untuk memakai nalar. Apalagi kita hidup di zaman yang begitu kompleks akan persoalan-persoalan budaya dan peradaban. Tetapi, hal ini bukan berarti kita harus memahami segala sesuatu semua nalar kita.
Akal memiliki wilayahnya, begitu juga agama. Keduanya harus saling mengakui dan tidak untuk dipertentangkan. Namun, harus juga menjadi sebuah catatan, bahwa ada sesuatu yang bertentangan dengan akal, ada juga sesuatu yang belum/tidak dipahami oleh akal.
Diferensiasi ini yang selayaknya disadari secara mendalam dalam kehidupan beragama. Mengingat bahwa prinsip pokok umat beragama adalah meyakini adanya supreme being (keyakinan terhadap sesuatu yang tinggi dan agung).
Di akhir kata, terkait rasionalitas dalam Islam, saya ingin menyampaikan sebuah syair yang ditulis oleh Imam Fakhruddin al-Razi, seorang teolog, dokter, sekaligus muffasir Al-Qur’an yang masyhur:
نهاية اقدام العُقول عقال
وأكثر سعي العالمين ضلال
وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا
Akhir dari kesungguhan akal manusia adalah keterbelengguan,
Dan kebanyakan usaha para cendekiawan menuju kesesatan..
Kita tidak memperoleh faidah apapun sepanjang usia kita,
Yang kita dapatkan hanyalah sebatas kumpulan apa kata si A, apa kata si B…