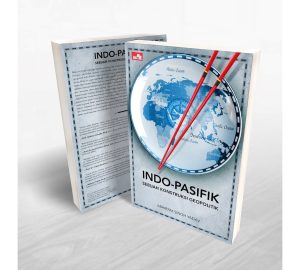Indonesia sesungguhnya pernah dipimpin oleh seorang presiden yang gemar membaca dan menulis sebuah buku. Pengalaman melahap banyak buku dan menjadi seorang penulis, yang di kemudian hari rupanya takdir hidup mengantarkan mereka menjadi orang nomor satu di negara ini, tentu saja berpengaruh terhadap wawasan kebangsaan serta pola kepemimpinannya. Siapa saja gerangan?
Pertama, presiden Soekarno yang terkenal dengan buku monomentalnya, Di Bawah Bendera Revolusi (1959) atau yang lazim disingkat DBR. Membaca DBR dan beberapa buku Bung Karno yang lain (di antaranya terdapat pidato-pidato yang dibukukan), memberikan kesan bahwa ia memang seorang pejuang kemerdekaan yang hebat, pemersatu, dan seorang humanis, sehingga memang layak menjadi presiden RI pertama pada masanya.
Kehebatan Bung Karno bukan semata-mata karena ia menjadi juru kunci dalam mengarsiteki basis epistemologi negara, seperti perumusan Pancasila beserta arti atau makna yang terkandung di dalamnya, tetapi juga karena wawasan kebangsaannya itu ditulis menjadi sebuah buku, sehingga dapat menginspirasi dan bahkan sebagai pedoman kenegaraan bagi sebagian masyarakat.
Bung Karno, yang menurut pengakuannya telah terlibat dalam gelanggang perjuangan kemerdekaan sejak usia 18 tahun mampu mencerap pengetahuan di luar pengetahuan mainstream, seperti yang terlihat dalam sidang BPUPKI, ketika tokoh-tokoh lain mengajukan konsep ideologi negara yang bercorak modern—negara Islam dan atau negara integralistik (Soepomo)—Bung Karno justru mengajukan konsep Pancasila sebagai ideologi negara pada sidang BPUPKI I tanggal 1 Juni 1945. Pancasila, menurut Bung Karno, bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, tetapi sudah menyejarah ratusan tahun silam.
Itulah sebabnya, Bung Karno menolak predikat yang diberikan oleh Prof. Mr. Notonagoro saat pengukuhan Doctor Honoris Causa di UGM sebagai “pencipta Pancasila”, tetapi ia lebih setuju sebagai “penggali Pancasila”.
“Aku bukan pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Aku hanya menggali Pancasila daripada buminya bangsa Indonesia. Pancasila terbenam di dalam bumi bangsa Indonesia 350 tahun lamanya. Aku gali kembali dan aku persembahkan Pancasila ini di atas persada bangsa Indonesia kembali,” ungkap Bung Karno di depan Kongres Rakyat Jawa Timur pada 24 September 1955.
Kedua, presiden B.J. Habibie. Pengalaman Habibie dengan buku sebenarnya tidak ada yang istimewa diceritakan, karena aktivitas menulis baginya merupakan “tuntutan” dan panggilan batin akademik sebagai seorang dosen. Gelar professor yang diraihnya merupakan puncak apresiasi kepenulisan di jalur akademik. Ketokohannya lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan atau lebih tepatnya ahli teknologi penerbangan yang karena situasi politik mengantarkannya menjadi presiden RI ke-3.
Namun sebagai pengalaman hidup, B.J. Habibie adalah orang pertama bergelar profesor yang pernah menjadi presiden RI. Gelar profesornya diperoleh pada usia yang relatif muda, berusia 41 tahun (dari ITB, 1967). Jadi, B.J. Habibie ketika menjadi presiden telah berstatus sebagi guru besar atau profesor. Inilah kehebatan B.J. Habibie. Berbeda dengan presiden setelahnya, sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang memperoleh gelar kehormatan profesor dari Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) tahun 2014 dan saat itu masih sebagai presiden RI ke-6.
Ketiga, presiden Abdurahman Wahid. Kepopuleran intelektual-kiai yang menjadi presiden ke-4 ini di jagad kepenulisan tidak diragukan lagi, karena ia memang melahirkan banyak buku jauh sebelum dan bahkan setelah menjadi presiden. Ada titik pembeda dan sekaligus persamaan antara Soekarno, Habibie, dan Gus Dur (panggilan akrab Abdurahman Wahid) sebagai seorang penulis buku.
Satu di antara dapat dilihat pada karakter muatan tulisannya, yang kalau Soekarno penguasaan terhadap ilmu sejarah sangat kuat, terbukti dengan ide Pancasila yang ia cetuskan sebagai warisan leluhur sejak 350 tahun, orientasi pemikirinnya berdimensi masa lalu, kini/sekarang dan esok; Habibie sebagai ilmuwan di bidang teknologi, jika membaca karya-karyanya hanya berorientasi pada masa kini dan esok; sedangkan Gus Dur serupa dengan Soekarno yang karya-karyanya banyak bermuatan sejarah kolosal kebangsaan, seperti yang tampak pada buku Membaca Sejarah Nusantara (2010), maka orientasi pemikirannya juga berdimensi masa lalu, kini, dan esok.
Kalau boleh disimpulkan, dalam konteks dunia buku dan kepenulisan, Soekarno adalah generasi awal sebagai “pemantik buku”; Habibie adalah “periset yang menghasilkan buku”, dan Gus Dur adalah “penulis sekaligus penggila buku”, sebab gangguan penglihatan pada Gus Dur lantaran mempunyai hobi fanatik baca buku.
Pengalaman Gus Dur dengan buku bahkan sering pula dijadikan otokritik bernuasan humor yang memang menjadi kekhasannya. Konon presiden AS Bill Clinton pernah terheran-heran kepada Gus Dur dari mana dia tahu cerita tentang perpustakaan Eisenhower. “Saya baca di buku Ted Sorrensen,” kata Gus Dur.
“Loh, jadi presiden Clinton sendiri tidak tahu cerita itu?”, tanya Jaya Suprana.
“Ya mungkin nggak tahu, sebab dia nggak baca buku. Mana mungkin presiden Amerika baca buku? Kalau dia baca buku berarti kelihatan dia nggak punya kerjaan. Nah,kalau presiden Indonesia, justru harus baca buku sebab nggak ada kerjaan,” timpal Gus Dur.
Keempat, ironis, karena memang tidak ada lagi presiden RI setelah Gus Dur yang menulis secara serius dan simultan dalam rentan waktu yang lama, baik sebelum maupun setelah menjadi presiden.
Selamat hari buku nasional!