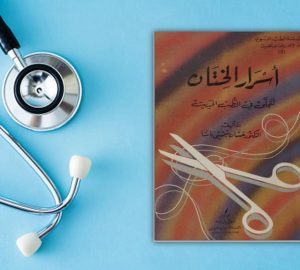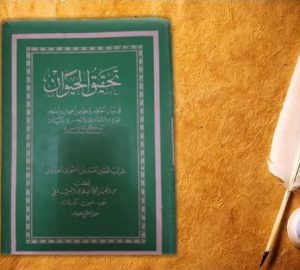Rujukan primadona mengenai isu pemukulan istri adalah ayat 34 surat An-Nisa. Secara tersurat, ayat ini memberi jalan bagi suami yang istrinya nusyuz (membangkang), untuk menasihatinya, berpisah ranjang darinya, dan kemudian memukulnya. Bahkan redaksi ayat ini menggunakan kalimat perintah (fi’l amr): nasihatilah (fa’izhuhunna), pisah ranjanglah (wahjuruhunna fil madhaji’) dan pukullah (wadhribuhunna). Dengan tegas dan jelas, dalam ayat ini, suami diberi wewenang untuk memukul istri yang nusyuz.
“Para perempuan (istri) yang kamu khawatirkan kedurhakaan mereka, hendaklah kalian nasihati mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur, dan pukul mereka”. (QS. al-Nisa, 4: 34).
Tetapi hampir semua penjelasan ulama tafsir melakukan pengetatan luar biasa bagi praktik pemukulan yang bisa dikatakan mustahil bisa dilakukan seorang suami. Syekh Nawawi Banten (w. 1314 H/1897 M) misalnya, yang kitab Syarh ‘Uqud al-Lujjayn-nya dianggap beberapa kalangan sebagai bias gender, memberi tafsir super ketat pada ayat tersebut.
Bahwa pemukulan istri, oleh suami, hanya boleh dilakukan setelah nasihat dan pisah ranjang, dan tidak boleh dipraktikkan dengan pukulan yang melukai dan tidak boleh juga yang membekas di tubuh badan perempuan, tidak boleh di muka, dan tidak boleh di satu tempat berkali-kali. Memukul pun harus menggunakan sapu tangan yang lembut. Syekh Nawawi sendiri memandang mukul istri itu tidak baik (khilaf al-awla) dan harus dihindari dalam keadaan apa pun (at-Tafsir al-Munir, Juz 1, hal. 149).
Jauh sebelum Syekh Nawawi Banten, pada masa Tabi’in ada Ima Atha bin Rabah (w. 126 H/744 M) yang menyatakan bahwa hukum suami memukul istri adalah makruh. Bayangkan, sesuatu yang dibolehkan (bahkan menggunakan redaksi kalimat perintah), tetapi turun dalam tafsir menjadi makruh (tidak baik), sesuatu yang harus dihindari. Satu level di bawah haram (Ahkam al-Qur’an li Ibn ‘Arabi, juz 1, hal. 420).
Begitu pun pendiri Mazhab Syafi’i, Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i (w. 204 H/820 M), dalam Kitab Magnum Opusnya al-Umm, menyatakan bahwa tidak memukul istri dalam kondisi apa pun adalah perilaku yang harus dipilih dan itu lebih baik (al-Umm, juz 5, hal. 207). Jadi, dalam pandangan Imam Syafi’i ini ini, sesuatu yang disampaikan dalam redaksi perintah di Alquran, hanya dipahami sebagai boleh, dan itu pun tidak dipilih, karenan yang dipilihnya adalah justru tidak memukul istri dalam kondisi nusyuz sekalipun.
Para ulama lain, baik klasik maupun kontemporer, secara umum sama, memberi pembatasan-pembatasan terentu kepada praktik pemukulan istri ini. Intinya, hal ini dibolehkan, tetapi harus dikontrol jangan sampai digunakan suami secara semena-mena.
Bagi suami yang baik dan berakhlak mulia tidak akan memukul istrinya. Hal ini bisa dibaca di tafsir-tafsir kontemporer Arab seperti al-Manar, atau di Indonesia seperti al-Azhar dan al-Misbah. Penjelasan ini tentu saja tidak tersurat di dalam Alquran. Dari manakah semua penjelasan ini muncul?
Tentu saja, semua ini lahir dari metodologi tafsir yang dikembangkan para ulama. Bahwa ayat Alquran tidak dipahami secara tekstual apa adanya. Melainkan dengan merujuk kepada berbagai rujukan lain, seperti ayat lain tentang mu’asyarah bil ma’ruf yang menuntut suami untuk selalu berperilaku baik terhadap istri (QS. An-Nisa, 4: 19).
Di samping itu juga hadis-hadis tentang perilaku mulia Nabi Muhammad saw. yang tidak memukul istri dan tidak menganjurkan sama sekali para suami untuk memukul istri. Jika merujuk pada pernyataan langsung Imam Atha bin Rabah dan Imam Syafi’i, maka pertimbangan yang mereke rujuk adalah hadis-hadis.
Artinya, teks-teks hadis memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran para ulama klasik untuk tidak mendorong para suami memukul istri, sekalipun pada kondisi yang diperbolehkan Alquran. Teks-teks hadis, dalam hal ini, jelas lebih eksplisit dalam membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan untuk terbebas dari kekerasan.
Tesis ini, sesungguhnya, bisa sedikit mematahkan thesis beberapa akademisi Muslim yang menganggap bahwa justru hadits-hadits yang menjadi sumber misoginisme.
Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, misalnya, ada teks-teks yang menyindir para suami yang masih saja memukul istri mereka, ada juga teks hadits yang menasihati perempuan untuk tidak menikahi laki-laki yang memiliki tabiat keras dan suka memukul.
Sementara itu ada teks hadis yang jelas dan tegas dimana Nabi Muhammad saw. menjadi teladan dalam hal tidak pernah memukul istri. Sementara di teks hadis Sunan Abu Dawud ada perintah tegas Nabi Muhamad saw. melarang siapa pun memukul perempuan.
Dari Abdullah bin Zam’ah r.a., mendengar Nabi saw berkhutbah dan menyebut perempuan, kemudian berkata: “Seseorang di antara kamu masih saja suka memukul istrinya bagaikan memukul hamba sahaya, (padahal) bisa jadi ia menggaulinya (hubungan intim) di akhir hari”. (Sahih Bukhari, no. Hadits: 4992, 5259, dan 6042).
Nabi saw. berkata (kepada Fathimah bint Qays): “Mu’awiyah itu masih terlunta-lunta dan miskin, sementara Abu al-Jahm itu keras terhadap perempuan –atau suka memukul istri atau seperti itulah- karena itu pilihlah Usamah bin Zayd”. (Sahih Muslim, no. hadits: 3785 dan 3786).
Dari Aisyah ra, berkata: Rasulullah saw. tidak pernah memukul apapun sama sekali dengan tangan, tidak juga (memukul) perempuan, atau pembantu. (Sahih Muslim, no. hadits: 6195).
Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab ra, berkata: Rasulullah saw. berkata: “Janganlah (kamu sekalian) memukul perempuan”. Kemudian Umar datang menghadap Rasulullah Saw, dan berkata: “Para perempuan membangkang atas suami mereka, maka perkenankanlah (kami) memukul mereka”.
Kemudian (di lain hari) para perempuan dalam jumlah banyak (datang berkumpul) mengitari keluarga Rasulullah saw., dan mereka mengeluhkan perilaku suami-suami mereka. Kemudian Rasulullah saw. berkata: “Para perempuan berkumpul mengitari keluarga Muhammad, mengeluhkan perilaku suami-suami mereka, para suami yang demikian bukanlah termasuk orang-orang yang baik”. (Sunan Abu Dawud, no. hadits: 2148).
Dari teks-teks hadits ini, dan dengan metodologi Ushul Fiqh, seorang ulama tafsir kontemporer, Ibn Asyur (w. 1393 H/ 1973 M) dalam Tafsir at-Tahrir wat-Tanwir justru mendorong pemerintah Islam untuk melarang pemukulan suami terhadap istri secara mutlak, karena alasan dan latar belakang yang disebut Alquran sudah tidak relevan lagi pada masa sekarang.
Dengan gambaran sederhana di atas, tulisan ini mengajukan thesis bahwa pandangan para pemikir progresif dan feminis Muslim, seperti Riffat Hassan, Ali Asghar Engineer, dan Syed Mohammed Ali, yang menegasikan Hadits dalam proyek pemikiran mereka mengenai Islam adil gender harus ditinjau ulang.
Sebaliknya, Hadits, dengan metodologi tafsir tertentu, seperti Qira’ah Mubadalah misalnya, bisa ikut berkontribusi besar dalam perumusan prinsip-prinsip keadilan gender dalam Islam. Khususnya pada semangat anti kekerasan berbasis gender.