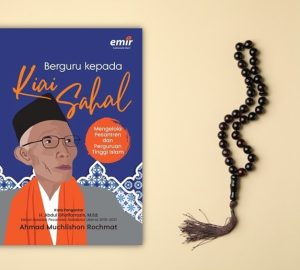Judul : Tuhan yang Tersembunyi: Renungan dari Balik Aksara
Penulis : Hairus Salim
Penerbit : Buku Mojok, Jogjakarta
Cetak : 2019
Tebal : xii+216 halaman
ISBN : 978 602 1318 99 7
Esai sulit terlupa dari Goenawan Mohamad berjudul “Posisi Sastra Keagamaan Dewasa Ini”. Esai mula-mula dimuat di majalah Horison edisi Juli 1966. Esai kecil tapi berkhasiat bagi pengenang kesusastraan Indonesia masa 1930-an sampai 1960-an. Ia “mengesahkan” genre sastra keagamaan dengan mengamati penerbitan buku sastra bertema agama dari pengarang-pengarang sudah kondang meski cuma puluhan orang.
Goenawan Mohamad berdalih sekian teks sastra masa 1960-an “telah mendesak kita untuk mengakui kehadirannja jang berbeda” dari buku-buku bercap sastra keagamaan gubahan Hamka sejak masa 1930-an. Pengesahan memiliki peringatan: “Apabila sastra keagamaan berusaha mendjawab persoalan-persoalan jang timbul dalam situasi kita sekarang dengan cara menjodorkan djawaban jang sudah djadi, rapih, dan korek, dengan gaja chotbah-chotbahan sedikit, maka ia akan menjebabkan kita sebagai pembatja mendjadi djemu dan malas.”
Pembuat “sambungan” dalam misi hampir sama adalah Hairus Salim dengan penerbitan buku berjudul Tuhan yang Tersembunyi: Renungan dari Balik Aksara (2019). Tiga puluh esai disajikan Hairus Salim dengan pokok sastra dan agama. Ia mungkin tak seturut anggapan Goenawan Mohamad di masa lalu. Kita simak dari pengajuan pengertian di esai-pengantar berjudul “Tuhan yang Tersembunyi, Menelisik Agama dalam Kesusastraan.”
Di situ, kita tak pernah menemukan nama atau kutipan dari esai pernah dimuat di Horison. Kita cuma menemukan misi atau arah hampir sama. Hairus Salim mengakui: “Namun perhatian utama saya lebih pada tema keagamaan secara intrinsik, bagaimana tema itu dipilih, diolah, dibangun sebagai narasi, dan apa maknanya.” Ikhtiar itu terjadi setahun lalu. Hari demi hari, ia mengulas teks sastra. Sebulan, Hairus Salim suntuk menikmati 17 novel dan 13 cerpen.
Esai-esai pun terikat ke sastra dan agama, terbit jadi buku mengesankan. Kita seperti menghadapi buku jilid II, setelah YB Mangunwijaya mempersembahkan buku berjudul Sastra dan Religiositas (1982). Buku itu pernah memberi pengaruh besar bagi penekun sastra Indonesia. YB Mangunwijaya pun tak meniatkan buku itu kritik sastra, kerja serius dan berselera akademik di pembacaan puluhan teks sastra Indonesia dan dunia. Buku cuma ingin mengejawantahkan dalil: “Pada mulanya, sastra itu religius.” Ia pun mengakui: bahwa penulisan esai-esai di buku itu “tidak dari titik kritik serta penilaian intern khas ilmu kesusastraan, tetapi biasa saja dari pandangan seorang yang menaruh minat pada kesusastraan dan kadar religiositasnya.”
Kini, kita menemukan kesinambungan tulisan Goenawan Mohamad dan YB Mangunwijaya disajikan di masa berbeda. Hairus Salim membuat ulasan tanpa kepatuhan ke kaidah-kaidah akademik atau kritik sastra. Ia memilih menuliskan “pengalaman membaca” dengan ketakjuban atau kegemasan dalam memberi pujian atau kritik di pengisahan agama.
Bermula dari cerpen berjudul “Pengemis dan Selawat Badar” gubahan Ahmad Tohari, kita disuguhi esai menggetarkan batin. Cerpen itu dihadirkan dalam pengisahan ulang secara ringkas dan dikaitkan ke referensi sufistik. Pengemis bermodal selawat badar ada di bus melaju ke Jakarta. Pengemis itu dimarahi kernet dan diabaikan para penumpang. Terjadilah kecelakaan berdarah dan menewaskan puluhan penumpang! Pengemis itu selamat, keluar dari bus ringsek dengan tenang: berjalan kembali ke arah Cirebon. Cerpen dan bacaan sufi memicu Hairus Salim memberi penilaian: “Cerpen dalam keseluruhannya harus dilihat juga sebagai suatu kritik pada kemiskinan dan cara menghadapinya.”
Hairus Salim pantang selesai menjadi pembaca menuruti situasi zaman cerpen saat digubah dan dibaca di masa lalu. Hikmah dari pengalaman membaca cerita ditaruh di masa sekarang meski berkesan melebihkan: “Rasanya, pengemis itu tidak ada apa-apanya dan sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding mereka yang memanipulasi agama melalui mobilisasi dan pengembangan isu yang canggih untuk tujuan ekonomi-politik. Orang-orang menjadi terpecah dan bertengkar karenanya. Mereka ini jauh lebih mencemaskan dan berbahaya.” Kita menganggap alinea itu “imbuhan” bermaksud cara baca terbukti kontekstual.
Cerita gubahan pengarang dari Mesir pun dipilih untuk mendapat ulasan agak ironik. Pengarang tenar dan terpujikan bernama Taufik el Hakim. Hairus Salim membaca cerpen berjudul “Sang Martir”. Alkisah, setan kapok dijuluki “Yang Terkutuk.” Ia ingin bertobat atau beriman. Segala keburukan ditinggalkan demi perubahan peran.
Keinginan tak mudah direstui pelbagai pihak telanjur mengenali setan itu di kubu terkutuk. Setan kebelet ingin jadi hamba berhak memuji Tuhan dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Di mata para pendakwah dan kaum beriman, keinginan setan itu “mustahil”. Seorang imam di Al Azhar bingung atas permintaan setan. Islam mengajarkan kalimat terucap: “Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk.” Kalimat itu tak mungkin dibuang gara-gara menuruti keinginan setan. Pertobatan setan bisa mengganggu tatanan dan struktur agama.
Cerpen terbaca Hairus Salim saat masih berkuliah di IAIN Sunan Kalijaga. Pembacaan ulang setahun lalu terasa berbeda meski tak terlalu mengejutkan. Cerita pelik dan “kocak” tak mendapat ulasan panjang. Hairus Salim justru cenderung ke pencatat hikmah tanpa pawai argumentasi: “Cerpen ini menyerukan dan mengajak ke beragama ke tingkatan yang lebih tinggi, ke tingkatan muhabbah, cinta, dan dengan tidak menjadikan setan sebagai motif dan tujuan dalam beragama.” Kita lekas saja bermufakat. Cara menaruh hikmah di akhir tulisan membuktikan Hairus Salim belum ingin berlagak menjadi kritikus sastra. Kecukupan dalam menikmati dan memberi tafsir tak berkepanjangan justru mengajak pembaca mau merenung sejenak: mengena.
Cara baca dan ulasan itu mengingatkan ke pendapat Goenawan Mohamad: “… tugas kesusastraan bukanlah memberikan djawaban. Tetapi djustru memberikan pertanjaan. Seorang pengarang jang biasa memberikan djawaban jang telah siap kepada para pembatja dalam menghadapi persoalan-persoalan hidupnja, akan tidak membantu si pembatja dengan baik.” Kini, kita pelan-pelan membaca ulasan-ulasan garapan Hairus Salim sambil “membaca lagi” situasi keberagamaan di Indonesia.
Kita menganggap tema agama di Indonesia mulai rawan memicu perdebatan mengeras dan rumit, jauh dari percakapan terbuka dan renungan. Penerbitan buku sengaja dimaksudkan untuk “ikhtiar kecil menjaga kewarasan.” Pilihan membaca teks-teks sastra itu perbuatan ingin waras ketimbang berlagak paling beriman dan paling benar dalam polemik-polemik mengacu ke agama di Indonesia masa sekarang. Begitu.