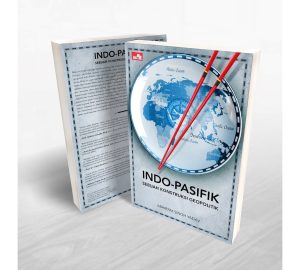Puisi tak melulu tentang senja, hujan, atau lara hati. Atau lara hati di senja yang hujan. Puisi juga menyoal peristiwa berbuku. Buku-buku mencari sisa ruang di sela hujan, senja, dan lara yang makin menyumpeki semesta puisi “kekinian”.
Kita merujuk puisi berbuku dari penglihatan anak dan ibu. Bermaksud menengok peristiwa berbuku dari ruang paling penting di atas muka bumi: keluarga.
Dalam buku puisi Ibu Mendulang Anak Berlari (2016) garapan Cyntha Hariadi, kita menjumpa potret interaksi antara ibu dan anak. Dalam kisah-kisah teladan, ibu seringkali digambarkan bak malaikat. Pembaca dibuat lupa kalau ibu juga manusia yang tak cuma berlumur kesabaran. Dengan anak, mereka juga bisa murka:
Apa pun yang terjadi di antara kita setiap hari/ membuang muka, menghindari tatapan mata, adu mulut/ silat lidah, tarik urat, main tangan, banting pintu, piring pecah/ tembok gegar, lantai retak, tersisipi kepingan-kepingan hati/ yang hancur dari sebuah ledakan yang menguras raga// setiap malam,/ tubuh kita berhimpitan kembali/ jiwa kita menyatu di dalam sebuah buku.
Ibu dalam puisi Cyntha tersebut terlihat jujur. Sebagai aku-lirik, terdengar suara lelah darinya atas kejadian pada siang hari tadi. Ibu jengkel perintahnya tak dituruti anak. Benda-benda dan suara-suara pecah memenuhi rumah. Ibu dan anak bagai dua televisi yang disetel berbarengan. Hanya saja, mereka punya perasaan sabar yang rentan remuk dan dua tangan untuk beradu tunjuk
Yang menarik dari puisi di atas, Cyntha tak menampilkan citra ibu-ibu (muda) zaman sekarang. Dalam puisi itu tidak ada gawai, peranti yang agaknya sudah menjadi barang wajib dimiliki hari ini. Barangkali sang aku-lirik tahu, gawai memang ampuh membuat rumah jauh dari percekcokan. Diam tapi bersekat. Maka, meski tahu besok pasti akan ada ribut-ribut lagi, ia memilih buku sebagai tempat bediam yang tak saling mengasingkan:
Mata yang masih menolak berpandangan/ akhirnya lelah dan mengatup/ kedua sepasang lengan saling merengkuh/ lupa apa yang diributkan hari tadi.
Kita bisa membayangkan “Ibu mendulang” cerita yang menjadi tenaga “anak berlari” dalam imaji. Ketika lelah mengembara dalam kisah, mata anak mengatup. Lengannya merengkuh tubuh yang semula dirinya. Ibu terus melanjutkan dulangan cerita. Matanya mungkin sudah berat, tapi ia terus, sembari melirik anaknya yang sudah pulas. Ketika cerita usai, barulah ia menutup buku. Mendekap tubuh di sampingnya. Tubuh yang akan terus ia rasa dirinya.
Buku adalah tanah lapang. Ibu menghamparkan bentang itu pada anak. Tapi yang lapang itu bukan malah menjauhkan. Pada buku, tanah lapang justru menjadi tempat mereka berlari, bercengkerama, dan mengaso bersama. Peristiwa berbuku menjadi peristiwa intim alih-alih mengasingkan.
Begitu pula peristiwa berbuku yang ditulis Abinaya Ghina Jamela, penyair perempuan kelahiran 2009. Buku adalah wilayah yang tak pernah tuntas. Ibulah menjadikan Naya terus bergairah mengembara pada ruang yang ia tahu tak akan pernah berujung itu. Tulis Naya dalam sebuah puisinya: Kenapa aku/ suka membaca? Biar pintar seperti bunda. Ibu menjadi detak hidup berbuku.
Sejenak kita mengingat peneliti Asia Tenggara terkemuka, Benedict Anderson (1936-2015). Dalam memoarnya, Hidup di Luar Tempurung (2016), Ben berkisah bahwa orang tuanya membikin perpustakaan rumah tiada tanding. “Mereka juga mendorong kami terbiasa membaca tentang kehidupan, pengalaman, dan pemikiran orang-orang yang berbeda bahasa, berada di kelas dan wilayah yang berbeda, serta berasal dari periode kesejarahan yang berbeda,” kenang Ben.
Seperti kelak aku-lirik dalam puisi Cyntha dan Naya, keranjingan berbuku Ben juga diinisiasi orang tuanya. Buku-buku yang mengungkung masa kecil Ben berisi cerita-cerita. Itu menjadikan masa kanaknya benar-benar penuh cerita. Dan manusia, Anda tahu, terbentuk dari cerita. Mungkin dulu Ben kecil tidak pernah menyangka, tapi kini kita mengerti saja, melihat asupan buku masa kecil Ben, mengapa ia menjadi manusia yang sungguh-sungguh “hidup di luar tempurung”.
Peristiwa berbuku mengajarkan kita ogah tenang mendekam dalam tempurung. Membaca bukan peristiwa beku nan menenangkan. Duduk atau tiduran kala membaca bukan berarti tidak kemana-mana dan tak mendapat apa-apa. Membaca itu penjelajahan penuh gejolak. Kita cerap tiga baris puisi yang memantulkan peristiwa biografis membaca Naya: aku membaca buku./ Buku tentang jantung, detaknya/ seperti kuda berlari.
Jantung bagi Naya tak sekadar organ tubuh. Naya tak membaca jantung sebagai organ pemompa darah belaka. Jantung juga berarti suara deru kuda di hamparan sabana. Dimulai dari organ dalam tubuh, imaji Naya melayang menuju tanah lapang tempat kuda berlarian. Ada cahaya emas matahari sore, angin sepoi, desir rumput, dan suara deru kaki kuda. Buku membawa imajinasi melintasi ruang-ruang.
Membaca buku kerapkali menjadi peristiwa penuh ketakterdugaan. Sayangnya, masa kanak, atau masa ketika imajinasi lincah berloncatan, buku tak sering dijadikan perayaan. Bisa jadi karena dari suatu rumah, buku dianggap laiknya barang mewah. Atau, boleh jadi, dari rumah yang lain, buku teranggap sebagai barang kuno membosankan. Lagi pula, dengan anggapan macam itu, buku masih bisa dijumpai di perpustakan.
Asumsi demikian menanggalkan imajinasi buku di rumah. Padahal, seperti dikatakan Murti Bunanta (2008), perpustakaan memang berjejal buku, tapi tak banyak yang bisa mencipta peristiwa berbuku. Sebab itu, masa kanak terjauhkan dari peristiwa menakjubkan berbuku.
Barangkali itulah mengapa dalam puisi Surat Malam untuk Paska (1999) Joko Pinurbo menulis: masa kanak adalah bab pertama/ sebuah roman yang sering luput dan tak terkisahkan. Dalam puisi itu aku-lirik membandingkan dirinya dengan kau, yang “ingin belajar membaca sebutir kata/ yang memecahkan diri menjadi tetes ari hujan/ yang tak terhinga banyaknya.”
Cerita dalam buku sebenarnya bisa menjadi penanda dalam perjalanan waktu manusia yang turut mengisahkan “bab pertama”. Bagaimana cerita-cerita dalam buku mulanya kita terima dan kemudian kita beri makna. Ingatan itu, pada usia yang semakin mendewasa, semakin kaya. Dan menjadi tempat berpulang kala lelah pada dunia yang semakin tua.
Artikel ini juga tersedia dalam bahasa:
 English
English