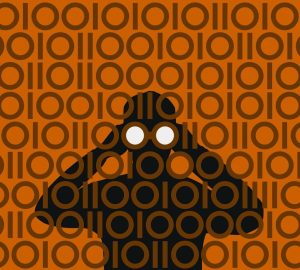Khalayak negeri ini tampaknya harus memacu sikap arif. Sikap ‘kebegawanan’ ini perlu didekap erat senyampang jamaknya hamburan berita dan narasi yang memantik petaka. Setiap kali kita memelototi medsos entah itu twitter, facebook dan lainnya jantung terasa berdegup. Tak hanya ungkapan yang lintang pukang kebenarannya, tapi juga makian atau hujatan yang saling menyambar bak predator yang sedang berburu mangsa.
Tetiba saat wafatnya KH Maimoen Zubeir, tokoh bangsa yang kepulangannya ditangisi banyak orang, muncul ujaran kebencian di medsos oleh bedebah yang mengaku wartawan sebuah tv ternama di ibukota. Pernah pula muncul tuduhan bahwa terorisme itu hasil rekayasa dari pihak-pihak tertentu. Bahkan tuduhan ini keluar dari anggota parlemen terhormat. Dengan bahasa yang terbungkus eufimistis, istilah ‘pengalihan isu’ memancar seolah memesona pembacanya. Yang berbau politis terasa lebih dahsyat mencuat, memaki dan menjatuhkan dengan menebar hoax bahkan fake news menjadi ‘panggilan jihad’ demi membela jagoannya.
Contoh hoax yang giris, sebagaimana sebuah ‘atsar’ yang diriwayatkan oleh Lee McIntyre dalam buku kecilnya bertajuk Post-Truth (2018). Arkian, di belahan bumi barat ada sekelompok sekte pengikut Dorothy Martin, yang mendaku bisa berkomunikasi dengan mahkluk alien. Lalu ia mengumumkan bahwa dunia akan kiamat pada tanggal 21 Desember 1954. Sontak, pengikutnya percaya, mereka mulai menjual seluruh harta benda mereka, dan berkumpul di sebuah gunung menunggu kiamat dan penyelamatan dari kaum alien. Namun pada malam itu, alien tidak datang, kiamat juga tidak terjadi.
Bayangkan betapa bingung, kecewa, malu dan marahnya orang-orang ini. Ajaibnya, Dorothy Martin bisa menenangkan mereka dengan sebuah pesan baru: iman dan doa kalian begitu kuat dan hebat sehingga para alien membatalkan rencana kedatangan mereka. Maka, doa-doa penuh iman para pengikut inilah yang justru menyelamatkan dunia dari kiamat.
Bagi seseorang atau kelompok yang sudah terbebat oleh pikiran radikal sehingga menetaskan paranoid dan serba syakwasangka seraya menggenggam teori konspirasi sebagai rujukannya, hal-hal yang masih belum jelas kebenarannya akan mudah terlahap. Justru bagi mereka yang dipandang hoax adalah berita atau narasi yang ‘ilmiah’, berdasar riset dan rujukan yang otoritatif.
Maka, kun faya kun, terjadilah kisah seseorang yang rela menjual harta benda dan bahkan rumahnya untuk bekal hijrah ke Suriah. Berita dan narasi mewartakan bahwa akhir zaman akan tiba dan harus hijrah ke Bumi Syam. Seorang ustaz berapi-api mengkhotbahkan segala hal yang seolah ‘ilmiah’ dari soal nujumannya tentang ‘Akhir Zaman’ hingga soal terorisme sebagai konspirasi dan ini hanya berdasar pada ‘keyakinan’ tanpa investigasi ilmiah dan sikap kritis.
Fenomena seperti ini mengungkap kembali betapa Indonesia selalu mengalami ‘lompatan’ yang tak beraturan. Dulu saat televisi hadir di masyarakat, berbondong-bondong masyarakat menonton televisi. Dan kini, dunia internet hadir yang membuat masyarakat menjadi eforia sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi yang bertebaran di internet. Mereka ‘dipaksa’ untuk menggunakan media digital, tetapi sesungguhnya mereka belum ‘siap’ dengan era digital. Akibatnya, mereka hanya menggunakan internet untuk keperluan yang superfisial, bukan pendalaman keilmuan. Ya, mereka belum memiliki tradisi membaca dengan baik.
Fakta yang Ditekuk
Inilah era ‘post truth’. Istilah ini merujuk pada masyarakat yang lebih mempercayai pandangan sendiri dan emoh terhadap fakta sebenarnya. Yang penting berita atau narasi yang muncul memberikan ‘kesenangan’ atau ‘kenyamanan’ bagi pembacanya tanpa harus berpayah-payah menginvestigasi sejauh mungkin demi mencapai ‘kebenaran’. Maka, tiada lagi kebenaran, karena yang ada adalah ‘opini’ dan ‘persepsi’.
Dan kini, ketika teknologi informasi mengular, kita sekarang masuk di era yang aneh. Yang penting membikin pikiran dulu, realitasnya nanti disusulkan dan disesuaikan. Tak ayal, ‘Post-truth’ menjadi sohor, kendati istilah itu sebenarnya sudah populer semenjak 1992. Di negeri kita hingga saat ini terjadi ‘disrupsi’ dengan kerapnya kita disuguhi berbagai wacana yang aneh-aneh. Dan lebih anehnya lagi, wacana-wacana kosong tanpa data alias murni retorika ini mendapatkan sambutan luar biasa dari para fanatik. Kebenaran tidak lagi dipersoalkan. Orang lebih merasa nyaman ketika “fakta” ditekuk dan disesuaikan dengan tafsir, opini dan keyakinan pribadi.
Post-truth berakar dalam jiwa manusia sendiri yang mudah jatuh dalam cognitive bias. Manusia ternyata tidak serasional yang dianggap selama ini. Di depan kebenaran-kebenaran yang tidak mengenakkan, manusia cenderung jatuh dalam cognitive bias. Ego kita memiliki mekanisme pertahanan diri, sehingga saat apa yang kita yakini terbukti salah, kita tidak serta merta mengakui kesalahan kita. Ini pula yang disebut filsuf Herbert Marcuse dari madzhab Frankfrut sebagai ‘One Dimensional Man’, manusia yang kehilangan sarwa dimensinya karena menciutkan diri dalam ‘jeruji’ keyakinan yang picik, tanpa kritisisme.
Salah satu cognitive bias adalah cognitive dissonance, yakni ketidakcocokan pengetahuan, namun bisa diharmoniskan. Dalam ungkapan filsuf Jerman Nietzsche, manusia memang butuh “pegangan”. Apa pun akan ia jadikan pegangan, bila kebutuhannya akan pegangan besar. Semakin besar kebutuhannya, semakin fanatik kebenaran dipegang. Dan normal bahwa orang menyebut pegangannya sebagai yang paling benar. Pun kalau itu adalah kesalahan, hoax atau fake news, sejauh itu membuat ia nyaman, maka akan ia sebut sebagai kebenaran.
Post-truth makin ‘erupsi’ seiring makin turunnya peran media koran dan televisi tradisional. Setiap orang sekarang bisa menjadi penulis, editor dan penerbit untuk apa yang ia pikir benar. Munculnya teknologi dan perkembangan media sosial juga menjadi trigger makin anarkisnya pemberitaan sehingga hoax dan fake news menjadi sesuatu yang dianggap lumrah saja, bahkan ‘kudapan’ harian yang diburu cukup lewat gadget.
Lalu, apa kabar dengan dunia akademis? Di depan fenomena post truth, dunia akademis seperti ‘dinistakan’ oleh ‘para pengamat dadakan’. Hasil riset yang memakan waktu, tenaga, pikiran dan dana yang besar menjadi ‘tak bunyi’ di haribaan nitizen yang memberantakkan cukup dengan ‘gombalan’ yang membuta tanpa ‘akal sehat’. Gelar akademis yang mentereng terpaksa ‘loyo’ tak berkutik bahkan tidak jarang akademikus justru ikut memproduksi berita hoax dan narasi kebencian (hate speech). Dunia kampus yang diharapkan bisa menjadi penjaga gawang kewarasan rasio lagi-lagi tak berdaya.
Alamak! Sungguh fakta yang ironis. Bila masyarakat sekarang ini bingung dengan soal kebenaran, mereka justru tidak mungkin meminta nasehat kepada para akademikus, karena di dunia akademis sendiri sudah mengidap skeptisisme pada rasio dan kebenaran.
Apakah ini akibat polah tingkah dari postmodernisme yang hadir untuk melawan ‘narasi besar’ modernisme? Nama-nama ‘kombatan posmo’ seperti Jean-François Lyotard, Derrida, Michel Foucault, Heidegger dan Friedrich Nietzsche telah meletakkan fondasi filosofisnya yang lalu menyerbak menjadi ‘gaya hidup’ berbagai bidang. Ide “dekonstruksi” dari Derrida yang menyatakan bahwa makna sebuah teks, pun kalau kita merujuk pada pengarang teksnya sendiri, tidak pernah bisa ditentukan.
Apa pun bisa dianggap sebagai “teks” yang bisa dibolak-balik maknanya tanpa pernah sampai pada makna ultima. Akibatnya, tidak ada lagi makna-benar atau makna salah. Yang dipertanyakan dalam metode dekonsktruksi memang kebenaran itu sendiri! Setiap interpretasi atas teks dianggap sah dan valid, tidak ada yang benar dan salah. Semua hanyalah narasi-narasi yang valid dalan konteks konstruksinya sendiri, dan tidak ada urusannya dengan kebenaran. Keyakinan posmodernis pada pecahnya kebenaran ini bisa diasalkan pada epistemologi perspektivis Nietzsche yang ditafsir secara posmo.
Dalam kacamata posmodernisme tidak ada kebenaran objektif, tiap klaim akan kebenaran objektif sebenarnya menyembunyikan kepentingan ideologis politik tertentu dari orang yang mengatakannya. Kebenaran dinyatakan lewat bahasa, padahal bahasa adalah cermin dari relasi dominasi dan kuasa. Dengan demikian, tiap klaim kebenaran tak lain hanyalah strategi dominasi atau taktik ‘bullying’ dari pemegang kekuasaan kepada orang-orang yang lemah. Mengingat kebenaran objektif tidak ada, maka bila ada yang mengklaim kebenaran, ia mewakili kepentingan dominan yang hendak menindas mereka yang lemah.
Kita tentu tidak pernah bermaksud mengatakan bahwa “fakta objektif tidak pernah ada”. Yang benar, filsafat posmo mengajarkan bahwa tidak ada akses pada kebenaran yang bersifat langsung dan niscaya, karena kita semua dibatasi oleh bahasa. Dan saat kita berbahasa, mau tak mau, bahasa bersifat partikular, tidak pernah objektif.
Dalam tilikan Lee McIntyre (2018), iklim post-truth memiliki akar filosofis pada ide-ide yang mengusung relativisme kebenaran, perspektivisme kebenaran, skeptisisme kebenaran, dan terapan atasnya sebagaimana tampak dalam “sosiologi konstruktivis”. Para pemikir postmodernisme– yang akarnya bisa dirujuk pada Nietzsche dan Heidegger–akan mempertanyakan soal teori baku kebenaran sebagai “korespondensi antar pikiran dan kenyataan”.
Bersamaan dengan itu, konsep tentang manusia dan pikiran atau rasionya juga dipertanyakan. Apa-apa yang di era modern dianggap jelas dan stabil menjadi goyah. Apa “realitas” itu sendiri juga menjadi dipertanyaan. Dengan pertanyaan-pertanyaan kaum skeptis seperti itu, posisi realis seakan-akan menjadi posisi yang membutuhkan topangan kebenaran transendental, semacam “ada dalam dirinya sendiri” yang menjadi landasan bagi keberadaan sesuatu.
Segala sesuatu di tangan dekonstruksi bisa dipertanyakan. Fakta bisa jadi hanyalah opini. Apa yang semula dianggap sebagai teori, ternyata di baliknya bekerja ideologi tertentu. Lewat cara berpikir yang dekonstruktif, tak ada sesuatu pun yang jelas dengan sendiri. Tak ada sesuatu yang tidak dikonstruksi.
Pada dirinya sendiri, kritik-kritik atas kebenaran adalah hal yang biasa dan wajar. Sejarah filsafat dipenuhi oleh pertempuran mengenai validitas tidaknya sebuah kebenaran. Namun, duhai posmo! Apa yang terjadi dengan model kritikan posmodernis memang bergerak terlalu jauh. Kebenaran dianggap tidak ada, objektivitas dianggap klaim semu.
Boleh saja banyak yang marah terhadap para posmodernis yang dengan ngawur meruntuhkan segala sesuatunya. Berabad-abad, kita setia dan hormat pada rasio, kebenaran dan ilmu pengetahuan. Berabad-abad kita berjuang melawan ideologi gelap yang sewenang-wenang dan segala bentuk tahayul. Namun saat ini, pada banyak kita justru meruntuhkan itu semua atas nama“kebebasan tafsir”.
Cilaka tiga belas, ide-ide kiri yang radikal ini justru diambil oper oleh kaum kanan radikal. Mereka mempertanyakan kebenaran objektif, kebenaran sains, kebenaran klaim-klaim yang diterima universal selama ini. Wacana posmodernis diperalat guna menyebarluaskan kebohongan-kebohongan kaum kanan radikal. Dan uniknya, mereka yang terlihat kuat keagamaannya justru paling suka mengumbar kebencian dan kebohongan. Maka yang menampak, banyak ke rumah ibadah, banyak pula menebar kebencian.
Ketika ide-ide posmo disergap oleh kaum ekstrem kanan, maka dunia menjadi garang dan menyundut kepanikan. Kita menjadi takut, kekalapan atas nama agama akan melahirkan mafsadah bahkan ifsak al-dimak, perseteruan berbalas darah. Radikalisme yang lalu melahirkan terorisme bisa dilihat sebagai produk dari ‘gagal paham’ ini. Padahal sejatinya dengan semangat dan metode dekonstruksi dimaksudkan kepada publik, agar supaya orang mampu berfikir kritis di depan fakta-fakta yang belum terobjektifkan dengan jelas.
Jaga Kewarasan
Nah, dalam situasi centang perenang dunia sosial kita, niscaya untuk melahirkan pribadi-pribadi yang teguh, berani, tulus dan pengabdi. Kita tak butuh ‘label’. ‘pangkat’, ‘gelar’ , ‘jenggot’, ‘jidad hitam’ atau apapun atribut lainnya. Kita hanya butuh-meminjam ungkapan sufistik Jalaluddin Rumi- yaitu ‘fihi ma fihi’, apa yang menukik jauh dalam diri yang jernih menuju kasunyatan hakiki. Atau mengutip ungkapan filosofis Nietzsche dalam Also Sprach Zarathustra,
….orang harus berani berbicara bagaikan guruh dan kilat kepada indera-indera yang lemah dan tertidur. Tetapi suara keindahan berbicara lembut. Ia meresap hanya ke dalam jiwa-jiwa yang paling bangun.
Ya, kepandiran dan kebohongan harus ditaklukkan dan kebenaran harus dijunjungtegakkan. Dengan begitu, tampil selalu di setiap masa mereka yang terus melawan rupa-rupa kebencian, intoleransi dan radikalisme sembari mengumandangkan indahnya kebersamaan, pengorbanan dan welas asih.