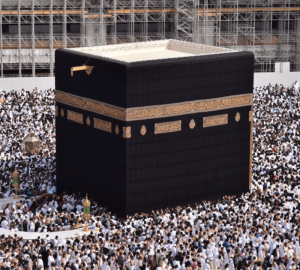Suatu anugerah besar dari Tuhan, manusia mampu mengungkap makna yang terbesit dalam lubuk hatinya dengan kata-kata yang kemudian kita sebut dengan bahasa.
Sejatinya bahasa merupakan wadah yang menampung makna. Sementara wadah terkadang tidak mampu menampung isi yang berupa makna.
Makna pun demikian, tidak jarang sulit diungkap karena tak menemukan kata yang tepat, karena memang kata-kata itu terbatas, tidak dengan makna yang sangat kaya dan luas.
Luasnya makna, dan terbatasnya kata, tidak lantas menghalangi orang mengungkap makna lewat kata-kata. Karena di antara kelebihan kata (kalimat) adalah dapat menampung beberapa makna dalam waktu dan tempat yang sama.
Realitas inilah yang berlaku dalam kitab suci al-Quran. Walau usianya telah menembus berabad-abad tahun, tetapi teks-teks yang dibawanya tak kan pernah putus dari limpahan makna yang menyertai perkembangan ilmu pengetahuan sepanjang masa.
Imam Suyuthi dalam al–Itqan-nya menyebut bahwa mukjizat yang dimiliki al-Quran tidak sama dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi terdahulu yang hanya bersifat indrawi, seperti sapi Nabi Shaleh dan tongkat ajaib Nabi Musa.
Mukjizat keduanya hanya disaksikan dengan mata kepala dan berlaku dalam waktu tertentu yaitu sepanjang hidup nabi mereka.
Sementara mukjizat al-Quran berkenaan dengan mata hati dan akal pikiran yang akan tetap eksis sepanjang zaman.(al-Itqan Fi Ulumu al-Quran 393)
Dengan begitu, al-Quran benar-benar menyimpan makna yang sangat dalam dan melimpah yang akan terus menginsfirasi manusia dengan kandung makna-maknanya.
Lalu bagaimanakah al-Quran menyimpan makna dalam lafal-lafalnya yang terbatas itu? beberapa paragraf yang disajikan dari kajian Ushul Fiqh di bawah ini akan mencoba menjawab pertanyaan itu.
Kata-kata yang tersusun menjadi sebuah kalimat tidak jarang mengandung beberapa makna yang diperoleh dari berbagai aspeknya.
Setiap aspek menyimpan makna. Semakin banyak aspek yang dijangkau semakin banyak pula makna yang diperoleh.
Secara umum aspek-aspek atau jalur yang dapat digunakan memahami suatu kalimat tergolongkan dalam empat macam. Jalur ibarat an-nash, isyarat an-nash, dalalat an-nash, dan iqtidha’ an-nash.
Masing-masing makna yang terperoleh dari keempat jalur ini diakui sebagai makna yang dimaksudkan oleh pemilik kalimat.
Sehingga jika dikaitkan dengan al-Quran dan as-Sunnah, kesemua makna yang diperoleh melalui empat jalur ini, harus diamalkan dan dapat menjadi dalil suatu hukum karena diakui sebagai makna ayat atau hadis (madlulat an-nas).(Ushul Fiqh Wahab Khalaf 126)
Apa itu ibarat an-nash? ibarat an-nash ialah istilah untuk proses perolehan makna dari redaksi suatu kalimat tanpa melihat faktor-faktor luar. Sedangkan makna yang dipahami dengan proses ini disebut makna ibarat atau makna teks.
Selanjutnya isyarat an-nash. Sama dengan kategori sebelumnya, isyarat an-nash juga menunjuk suatu proses. Sedang makna yang dipahami darinya disebut dengan makna isyarat.
Contoh untuk dua kategori itu, Q.S. al-Baqarah 2 ayat 187
اُحِلَّ لَکُمۡ لَیۡلَۃَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ اِلٰی نِسَآئِکُمۡ
“Dihalalkan bagi kalian bersenggama dengan pasangan kalian di malam hari bulan puasa”
Mengacu pada proses pertama yaitu ibarat an-nash, maka makna yang diperoleh adalah kehalalan bersenggama dengan istri dimalam hari bulan Ramadan.
Sedangkan dari proses kedua yaitu isyarat an-nash diperoleh makna (hukum) kebolehan berpuasa dalam keadaan hadas besar.
Logikanya begini, al-Quran menyatakan, pasutri boleh bersenggama di malam hari bulan Ramadan. Sementara, seperti yang kita ketahui bahwa malam dimulai sejak terbenam matahari hingga terbitnya fajar. Asalkan belum terbit fajar maka tetap dikatakan malam.
Sehingga seandainya sepasang pasutri bersenggama di penghujung malam hari Ramadan dan selesai sebelum terbit fajar, maka pasangan pasutri tetap boleh berpuasa walaupun belum sempat mandi besar. Berdasarkan makna isyarat ayat di atas. (al-Wajiz Fi Usul Fiqh 165-166).
Setelah ibarat dan isyarat an-nash, urutan ketiga adalah dalalah an-nash. Berbeda dengan dua sebelumnya, dalalah an-nash adalah proses perolehan makna dari spirit dan rasionalitas suatu teks.
Jika seorang ayah misal melarang anaknya dengan berkata “anakku jangan sakiti orang lain” maka anak yang mengerti dengan teori dalalah an-nash ini akan berkesimpulan “menyakiti saja dilarang, apalagi membunuh”.
Nah, kesimpulan membunuh juga dilarang adalah contoh makna yang diperoleh dari spirit teks lewat dalalah an-nash.
Contoh yang populer adalah Q.S. al-Isra’ ayat 23:
فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ
“jangan katakan “Ah” kepada ibu bapakmu”
Mengatakan “Ah” saja tidak boleh apalagi memukul. Secara tersurat larangan memukul memang tidak ditemukan, tetapi ia tersirat yang diperoleh dari proses dalalat an-nash.
Terakhir adalah proses yang disebut dengan iqtidha’ an-nash. Iqtidha’ an-nash adalah perolehan makna dari kehendak kata yang secara tersurat tak terucap, tetapi mesti adanya.
Contoh sederhananya, seorang ibu berkata kepada anaknya, “Nak, tolong, air minum itu” maksudnya “tolong ambilkan air minum itu”.
Ucapan si ibu tidak menyiratkan makna perintah mengambil air. Tetapi ucapan ibu tidak bisa dipahami tanpa mempertimbangkan makna perintah mengambil.
Nah, makna perintah mengambilkan air minum dari ucapan si ibu ini, adalah contoh proses iqtidha’ an-nash. Sedang makna yang diperoleh dikenal dengan makna iqtidha’.
Contoh populer dalam al-Quran adalah Q.S. an-Nisa’ 4 ayat 23:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ
“diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian”
Maksudnya adalah haram menikahi bukan fisik ibu itu yang haram, karena hukum, berkaitan dengan tindakan bukan dengan benda atau fisik.
Wal hasil, semakin luas jangkauan teks yang dilihat semakin banyak makna yang diperoleh. Wallahu a’lam.