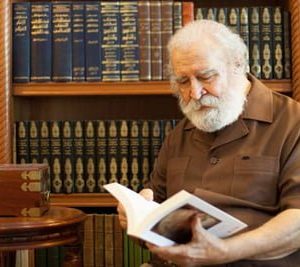Selalu terjadi pertarungan sentimental antara ahli sains dan ahli filsafat dalam menemukan kebenaran objektif yang benar-benar mencerminkan realitas. Tetapi, perlu diingat tidak semua yang bergelut dalam sains dengan metode positif pasti menyalahkan metode pemikiran filsafat.
Demikian pula ahli filsafat tidak bisa dipungkiri masih ada yang secara emosinal antipati dan pesimis pada ilmu-ilmu kealaman (sains). Tidak dapat digeneralisasikan pertarungan epistemologi ini. Karena masing-masing mengklaim kebenaran absolut bagi dirinya lalu membantah relatifitas selainnya.
Dalam konteks ini, perlu untuk dipisahkan antara sains dan ‘saintisme’ yang sekarang sedang hangat menjadi perbincangan di sosial media. keduanya sama-sama menggunakan metode positif dan empiris lalu diakhiri dengan penyimpulan rasional.
Hanya saja perbedaannya, ‘saintisme’ sudah berubah menjadi sejenis pandangan praktis, lebih tepatnya ideologisasi dalam menemukan kebenaran. Karena itu, saintisme hanya mengakui metode sains-lah yang paling tepat dalam menjelaskan realitas. Bahkan, ia juga untuk menjelaskan masalah fundamental seperti asal-usul alam semesta (kosmologi), kesadaran manusia, makna kehidupan, hingga akhir kehidupan.
Sains berusaha keras menguraikan semua itu. Lalu, jika ada yang tidak terjelaskan karena alat dan metodenya tidak mampu (capable) menggalinya. Para saintis kemudian satu sama lain berselesih. Berikut ini perselisihan kedunya.
Perspektif Saintis yang pertama, menganggap bahwa scope yang tidak sanggup digali oleh metode sains adalah non-sense, atau bahkan tidak mempunyai eksistensi sama sekali.
Contohnya ketika membuktikan, adakah ujung dari ruang dan waktu? Pengambilan informasi secara observatif tidak akan mampu mencapai sudut alam semesta itu, menggunakan alat apapun dalam menemukan keberadaan itu, ataupun menafikannya.
Walaupun demikian memang masih ada saintis berspekulasi melalui teori perluasan materi: alam semesta yang terus melebar dan merenggang. Kemudian menyimpulkan tiadanya ujung alam semesta. Tetapi, itu tetap saja tidak terbukti secara empiris alias masih spekulasi semata melalui proses deduksi (koherensi) dari teori—yang itu pun—masih kontroversial di kalangan saintis.
Kritik saintis terhadap pemikir filsafat (baca: filosof) adalah karena mereka mengakui menemukan kebenaran tanpa usaha sedikit pun. Hanya dengan berdiam, merenung, menyusun koherensi antara satu proposisi dan proposisi lain lalu menyimpulkan, “Inilah Tuhan”, “Inilah Akhirat”.
Menurut sains, kebenaran seharusnya diusahakan dengan pengamatan secara langsung terhadap alam semesta, bukan malah dengan duduk merenung lalu menyandarkan dagu! Pemikir filsafat kebanyakan berspekulasi (memungkin-mungkinkan) dan hanya berputar-putar dalam otaknya saja. Itulah mengapa sains sangat menjauhi metode epistemologi seperti itu.
Tetapi filsafat menimpali kembali saintisme bahwa, “Kalian tidak akan mencapai kebenaran tanpa proposisi filsafat, kritik terhadap filsafat adalah kritik terhadap landasan sains itu sendiri!” Metode sains memang tidak bisa dan tidak harus memercayai (afirmasi) prinsip kausal, prinsip identitas dan kontradiksi sebelum melakukan penelitian saintifiknya.
Semua kepercayaan sains tentang prinsip itu menjadi landasan dalam mengamati. Keinginan mencari sebab karena meyakini realitas yang diesperimenkan adalah akibat. Keinginan untuk mencapai kebenaran didasari oleh keyakinan bahwa setiap yang benar adalah benar tidak mungkin salah.
Itu semua merupakan penerapan filsafat dalam metode eksperimen. Lalu, bagaimana cara sains memercayai konsep-konsep itu tanpa membuktikannya terlebih dahulu secara saintifik? Bisakah landasan itu dibuktikan dengan saintifik? Tentu mustahil. Di sinilah sains harus berlutut pada filsafat.
Selanjutnya, perspektif kedua saintis setelah mengakui bahwa mereka tidak sanggup meneliti hal-hal yang metafisis. Mereka mengakui kalau wilayah itu bukan ranah mereka. Mereka membiarkan wilayah abu-abu itu dijamah oleh metode yang lain, pengetahuan langsung sudah berlepas diri darinya.
Saintis seperti ini tampaknya lebih adil dalam menempatkan kebenaran dan tidak memaksakan dirinya. tidak seperti sebelumnya, ketidakmampuan disamakan dengan ketiadaaan. Hal ini jelas-jelas berbeda.
Misalnya, dengan kata-kata yang sering kita dengar, karena Tuhan tidak mampu dilihat (atau diteliti) maka Tuhan tidak ada. Padahal kalau diperhatikan, ketiadakmampuan saintis dulu dalam menemukan pesawat yang terbang di udara bukan meniadakan kemungkinan pesawat terbang sama sekali.
Spekulasi dalam sains juga banyak terjadi. Meskipun mereka mengkritik filsafat yang spekulatif mereka menggunakan spekulasi juga dalam membuat teori-teori fundamental tentang alam semesta: Kosmologi dan Eskatologi.
Saintis terlalu terburu-buru menyimpulkan ketiadaan Tuhan sebelum membuktikan (melihat Tuhan langsung—dengan metodenya) bahwa Tuhan itu betul-betul tiada. Tentu berbeda antara ‘meniadakan’ dan ‘mungkin tiada’.
Alasan pembebanan bukti (burden of proof) selalu dijadikan argumentasi. Padahal tiada bedanya menegasikan dengan mengafirmasi sama-sama harus dibuktikan, karena negasi pun sejenis afirmasi tentang ‘ketiadaan’ dan setiap afirmasi harus di buktikan.
Sederhananya, jika saintis yang tinggal di hutan pedalaman dan tidak mengetahui keberadaan Candi Borobudur, apakah dengan ketidaktahuan saintis itu berarti meniadakan Borobudur? Tentu tidak, Borobudur tetap berada di tempatnya dan tidak dipengaruhi oleh ketidaktahuan saintis yang mengafirmasi ketiadaan Borobudur.
Sepatutnya, sains dan filsafat jika betul-betul ‘sadar diri’ di mana scope epistemologi masing-masing? Di mana seharusnya menegasi dan mengafirmasi? Keduanya pasti harmonis, permasalahan ini memang karena ideologisasi epistemologi yang sudah membutakan dan melampaui batas yang tidak seharusnya dijamah dan menjamah yang tidak sepatutnya dipredikasi.