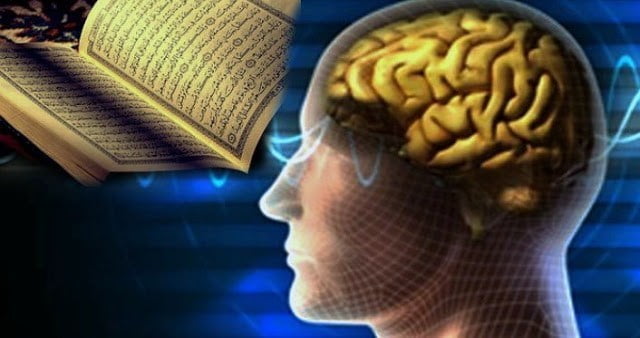Dalam pandangan Islam, setiap manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan suci (fitrah). Suci atau fitrah manusia di sini memiliki pengertian luas, mulai dari bersih dari noda/dosa sampai memiliki kecenderungan orientasi ketuhanan.
Kesucian itu kemudian ternoda oleh proses interaksi manusia tersebut dengan lingkungan dan pergaulan. Kemudian, muncullah ajaran tobat (secara bahasa: kembali) menuju kesucian yang sebelumnya ia miliki.
Kembali kepada kesucian ini dianggap sangat penting karena setiap manusia akan kembali kepada Dzar Yang Mahasuci. Maka, kepulangan kepada-Nya harus dalam keadaan suci. Kesucian inilah yang akan menentukan posisi seseorang kelak dengan Dzat Yang Mahasuci tersebut.
Atas dasar itu, ajaran mempertahankan kesucian atau kembali kepada kesucian merupakan pesan utama yang disampaikan oleh Al-Qur’an. Di antara ayat Al-Qur’an yang bertutur tentang fitrah ini adalah firman Allah SWT.:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. al-Rum [30]: 30).
Di dalam bahasa Al-Qur’an, ada enam macam fungsi preposisi “fa” (maka), di antaranya fungsi “fashihah”, penanda bahwa uraian yang difahului “fa” seperti ini terkait dengan uraian ayat sebelumnya. Ini sekaligus materi pelajaran bahwa pemahaman terhadap satu ayat tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman terhadap ayat sebelum dan sesudahnya.
Ayat-ayat sebelumnya (28-29) bertutur tentang ketauhidan, pemisalan tentang kebangkitan, dan pembangkangan orang-orang musyrik terhadap ketauhidan dan fenomena eskatologis tersebut.
Atas pembangkangan orang-orang musyrik tersebut, tidak ada alasan untuk putus asa dalam menegakkan ajaran ketauhidan, melainkan tetap fokus terhadap agama ketauhidan. Inilah hubungan ayat 30 dengan ayat-ayat sebelumnya.
Menghadapkan wajah kepada agama pada ayat ini diungkapkan dalam bentuk fi`il amr (perintah). Bentuk ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa penghadapan tersebut merupakan suatu keharusan (tidak ada pilihan), mesti dilakukan segera (al-fawr), dan tidak boleh ditunda-tunda (tarakhi). Atas dasar pemahaman ini, maka beragama dengan benar merupakan sebuah kewajiban individual.
Dalam bahasa Indonesia, ungkapan “menghadapkan wajah dengan lurus kepada agama” disebut dengan gaya bahasa metafora (isti’arah, dalam bahasa Arab). “Wajah” dipinjam untuk membahasakan memeluk agama dengan penuh konsentrasi, karena memang anggota tubuh ini bagian yang terpenting ketika seseorang berkonsentrasi terhadap sesuatu. Ini adalah salah satu keindahan gaya bahasa Al-Qur’an.
Ungkapan bahasa Arab yang persis untuk terjemahan “hadapkanlah wajahmu” adalah “aqbil wajhaka”, tetapi ayat ini menggunakan ungkapan “aqim wajhaka”. Tentu ada maksud penekanan makna di sini.
Diksi “aqim” berasal dari kata “qama-qiyam-mustaqim” (artinya berdiri). Kata ini sering diterjemahkan pula dengan “teguh” dan “kokoh”. Maka, makna yang diinginkan oleh ayat ini adalah berpegangan kepada agama dengan teguh dan kokoh, bukan hanya sekedar menganutnya. Makna ini diperkuat dengan keberadaan kata “hanifan” yang berarti mengkonsentrasikan kepada agama Islam secara istiqamah.
Ungkapan “dengan lurus” pada terjemahan di atas adalah terjemahan dari kata “hanifan”. Makna “hanif” adalah “mala `an” (berpaling dari). Jadi, lurus di sini harus dipahami dalam artian lurus dan konsentrasi serta berpaling dari berbagai upaya-upaya pendangkalan agama.
Dalam beragama, seseorang pasti menghadapi kendala-kendala yang tidak sedikit, di antaranya faktor-faktor eksternal yang menghalanginya untuk beragama secara benar. Nah, maka beragamalah secara lurus.
“Al-Din” yang dimaksud adalah agama Islam/agama tahuhid. Artikel “al” pada kata “al-din” dinamakan “alif-lam ma`rifat” (merujuk kepada sesuatu yang sudah dimaklumi/diketahui). Maka, tidak boleh dipahami bahwa agama yang dimaksud di sini adalah agama apa saja.
Kecenderungan kepada agama Islam atau beragama Islam secara benar dan teguh disebutkan sebagai fithrah. Fitrah ini bisa saja berkurang bahkan hilang karena berbagai faktor, maka ada perintah untuk mempertahankannya.
Pada ungkapan “fithratallah” ada ungkapan lain yang ditiadakan. Redaksi lengkapnya adalah “alzimu fithratallah” (pertahankan fitrah dari Allah tersebut).
Uraian di atas sekaligus meneguhkan bahwa beragama itu perlu perjuangan. Atau, beragama secara benar itu harus diperjuangkan. Mempertahankan fithrah tentu juga perlu perjuangan. Ajaran-ajaran yang disampaikan dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah pada dasarnya adalah panduan-panduan untuk mempertahankan fithrah tersebut.
Fitrah, dalam artian asal kejadian manusia berupa kecenderungan kepada ketauhidan atau beragama secara benar, tidak mungkin dirubah. Tak seorang pun mampu menghilangkan potensi ketauhidan seseorang. Tak seorang pun mampu menghilangkan potensi kecenderungan seseorang kepada kebenaran. Karena fithrah ini potensi yang tidak bisa dihilangkan pada diri seseorang, maka mengembalikannya merupakan sesuatu yang harus terus diupayakan. Maka, di sinilah dakwah memiliki eksistensi dirinya.
Kata “al-qayyim” seakar dengan kata “qama-mustaqim” (teguh, kokoh). Agama yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya adalah agama yang kokoh dan tegak, tidak condong ke kanan dan tidak pula ke kiri.
Mari kita teguhkan dan kuatkan keberagamaan kita. Agama Islam yang kita anut ini adalah agama yang lurus dan kokoh. Agar kita tidak dikategorikan kelompok orang yang tidak mengetahui kelurusan dan kekokohan agama ini, maka terus dan teruslah gali setiap sisi dari agama ini.
Demikian makna fitrah dalam pandangan agama Islam yang berdasarkan kajian tafsir Al-Qur’an pada surat Al-Rum ayat 30. Subhanallah. Begitu dalam dan indah makna yang diperlihatkan ayat di atas. Wallahu a`lam bish-shawab.
Tulisan ini disarikan dari Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran.