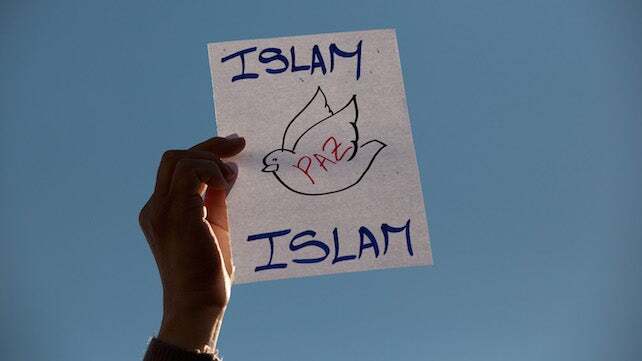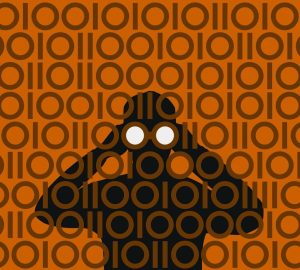Ini tentang bagaimana globalisasi memiliki banyak layer atau lapisan-lapisan yang di dalamnya memberi dampak yang besar bagi agama. Globalisasi dengan segudang penawaran tanpa batas, khususnya di bidang politik dan ekonomi, ternyata tidak saja memberi dampak yang baik bagi kehidupan.
Beberapa masalah serius ternyata juga muncul beriringan dengan merebaknya globalisasi. Salah satu isu terpanas tentang isu-isu global yang juga menjadi masalah dunia adalah tentang fundamentalisme dan terorisme.
Artikel ini secara khusus ingin merekam bagaimana Islam bersentuhan dengan globalisasi dan seluruh nilai-nilainya. Salah satu tesis utama yang menjadi pegangan penulis adalah bahwa globalisasi pada hakikatnya memiliki wajah ganda.
Di satu sisi globalisasi menawarkan tatanan kehidupan yang ideal, tetapi di sisi lain ia juga bisa menjadi jahat dan mampu menjadi pemangsa yang mematikan bagi tatanan kehidupan itu sendiri.
Bila melihat sentuhan antara agama dan globalisasi, paling tidak ada dua aspek utama yang perlu dilihat. Pertama, tentang pengaruh globalisasi terhadap agama, dan kedua, tentang respons agama terhadap globalisasi.
Pada aspek pertama, globalisasi memang benar-benar memberi pengaruh terhadap agama. Misalnya dalam pesatnya arus penyebaran media-telekomunikasi. Contoh ini sering kali wajah agama dibentuk oleh media.
Ini tentang bagaimana fenomena-fenomena agama itu dibentuk oleh citra media, sehingga baik tidaknya suatu agama bisa dilihat bagaimana media menarasikan fenomena agama tersebut. Melalui media, sejumlah fatwa-fatwa global juga dapat memungkinkan untuk diserap oleh segenap warga dunia.
Misalnya saja, ketika Grand Syech Al-Azhar membuat fatwa tentang larangan salat Jumat yang bertujuan untuk membendung penyebaran virus Covid-19. Fatwa ini secara langsung maupun tidak, dapat mempengaruhi keberagamaan masyarakat Indonesia. Sehingga media juga dapat menjadi sarana untuk menyalurkan berita-berita islami ke seantero dunia tanpa ada sekat-sekat.
Pengaruh globalisasi pada agama yang kedua bisa dilihat melalui munculnya banyak kepercayaan-kepercayaan baru. Ini tentang sesuatu yang disebut dengan diversitas agama alternatif, bahwa globalisasi dengan seluruh nilai-nilainya sering kali membuat seseorang kehilangan spiritualitas.
Kekosongan spiritualitas itu terjadi karena globalisasi memang tidak pandang bulu dalam menyebarkan nilai-nilai modenitas. Akibatnya, nilai-nilai agama menjadi tergerus dan bisa jadi hilang.
Ada semacam kerinduan untuk kembali ke nilai-nilai luruh, sebagian orang kembali ke agamanya, sebagian lagi membentuk keyakinan-keyakinan baru yang tampak asing bagi agama tradisional. Misalnya dengan kelahiran keyakinan baru bernama New Age yang cukup masif di Amerika.
Karena spektrum agama terlalu luas dan perlu penjabaran yang luas pula, maka respons ini hanya akan menyinggung dalam konteks Islam saja. Salah satu alasannya, karena Islam adalah salah satu agama yang banyak diperbincangkan di ranah global.
Hal itu secara khusus terkait isu-isu yang berkaitan dengan fundamentalisme dan terorisme. Banyak peneliti beranggapan bahwa fundamentalisme dan terorisme adalah gerakan kebangkitan agama secara global yang merupakan bentuk respons terhadap globalisasi.
Dalam buku Theorization Religion in Globalization (2008), Cristian Karner dan Alan Aldridge membagi respons agama terhadap globalisasi menjadi tiga macam; fundamentalisme, radikal resisten, dan komodifikasi agama.
Pertama, fundamentalisme. Fenomena ini bisa dilihat melalui menguatnya identitas atau sektarianisme dalam beragama. Fundamentalisme sendiri tak lain dari bentuk fanatisme dan kepercayaan yang berlebih-lebihan terhadap agama. Meskipun, watak aliran ini yang sesungguhnya tidaklah hanya berkutat pada penguatan identitas agama, tetapi lebih pada orientasi politik.
Bisa dipastikan, fundamentalisme merupakan sebentuk fanatisme yang membutuhkan kekuasaan. Mereka tidak saja mengembalikan agama ke jalur yang benar-benar suci, tetapi juga sekaligus mengambil kekuatan politik sebagai aspirasi untuk memperjuangkan agamanya.
Sederhananya, ketika mereka telah mampu membendung globalisasi dengan seperangkat imannya, mereka lalu membutuhkan ruang sosial yang lebih besar. Tujuannya agar keyakinan tersebut memiliki kekuatan yang bisa diperhadapkan dengan globalisasi.
Kendati demikian, fundamentalisme sering kali lebih bersifat politis daripada agamis. Di banyak negara berkebudayaan Islam, seperti di kawasan Timur Tengah, fundamentalisme mengambil banyak bentuk. Hanya saja, semua gerakannya memiliki kemiripan satu sama lain, yakni sebuah ‘agamaisasi’ politik dan terkesan memanfaatkan agama untuk tujuan-tujuan politik.
Dalam konteks ini, sebut saja misalnya Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan Jamaah Islamiyah, beberapa organisasi ini memang mengusung aspirasi Islam dan berkeinginan untuk membangun tatanan dunia yang lebih islami. Namun, pada saat yang sama mereka terjebak pada kepentingan politik dan kekuasaan.
Kedua, radikal resisten. Bentuk dari radikal resisten bisa berupa ekstremisme, tetapi kadang-kadang ia juga menjadi teroris. Tentu saja, kedua hal ini harus dibedakan agar kita tidak dikacaukan dengan pengertian agama yang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain.
Misalnya ekstremisme, ia tidak bisa disebut teroris karena gerakannya tidak bercirikan pertumpahan darah. Sering kali, ekstremisme dipahami sebagai gerakan islamis (fundamentalisme), tetapi dengan sedikit melakukan kekerasan secara sporadis.
Mereka tidak melulu menggunakan kekerasan dalam perjuangannya. Bila diperlukan, kekerasan itu menjadi halal dilakukan.
Wujud radikal resisten yang kedua disebut teroris. Memang harus diakui bahwa gerakan teroris umumnya dilakukan atas motif jahat yang tidak memakai embel-embel agama. Akan tetapi, harus diakui pula bahwa terorisme yang mendapat legitimasi dari agama juga ada banyak.
Ciri utama gerakan teroris berbaju agama biasanya merupakan organisasi yang tertata dengan baik. Selain itu, misi-misi politisnya sedemikian terencana dan sering kali faktor utama tumbuh suburnya terorisme adalah karena faktor ekonomi.
Dalam sebuah jurnal berjudul Predatory Globalization and Democraty in Islamic World (2002), Mustapha Kamal Pasha mengajukan sebuah tesis bahwa salah satu faktor utama tumbuh suburnya terorisme karena hegemoni Barat telah begitu mengakar kuat di negara-negara Muslim.
Ia menyebut, salah satu ideologi globalisasi yang secara langsung berdampak pada umat Islam adalah neo-liberalisme. Melalui ideologi tersebut, dunia benar-benar telah mengecil dan tanpa sekat, pasar bebas meraja lela di mana.
Akhirnya negara tidak memiliki kontrol terhadap aktivitas perekonomian. Bila negara tidak memiliki kontrol, maka jurang antara si kaya dan si miskin akan semakin terjal dan memprihatikan.
Ketiga, komodifikasi agama. Tema ini memang agak berlainan dengan apa yang telah disinggung di atas. Meski begitu, ia juga merupakan bagian penting dari respons agama terhadap globalisasi.
Komodifikasi agama artinya bagaimana agama dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ia menjadi pantas dan relevan dengan globalisasi. Selain itu, komodifikasi agama juga bisa berarti bagaimana komunitas agama menjaga nilai-nilai agamanya agar ia tetap utuh di era globalisasi yang tak menentu.
Contoh terbaik dari munculnya fenomena komodifikasi agama adalah munculnya tren-tren baru. Misalnya, kemunculan film-film berbau religi, sertifikasi halal untuk produk-produk makanan, pakaian dengan imbuhan merek syar’i. Tidak hanya itu, menjamur pula perumahan-perumahan yang bercirikan ‘syariah’, bahkan merebak pula bank-bank syariah berskala nasional dan internasional.
Pertanyaannya, apa yang menjadi inti dari respons Islam terhadap globalisasi? Sederhananya, respons Islam terhadap globalisasi adalah sebuah keniscayaan.
Ini terjadi karena masyarakat muslim meyakini bahwa Islam adalah agama yang telah tuntas dan mampu menjawab segala problem yang lahir di setiap zaman. Untuk itu, respons ini tentu tidak bisa dilihat semata-mata sebagai sesuatu yang negatif, karena tidak selamanya nilai-nilai yang datang dari Barat itu baik dan bersifat universal.