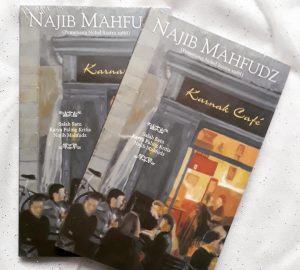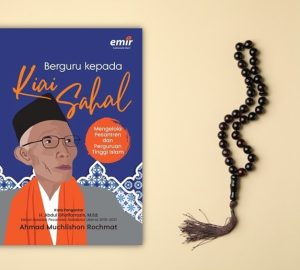Judul : Karnak Kafe
Penulis : Najib Mahfudz
Penerjemah : Happy Susanto
Halaman : 166 hlm
Tahun terbit : Cetakan Pertama 2008
Penerbit : Alvabet
ISBN : 978-979-3064-55-0
Kafe Karnak dalam novel ini dikisahkan berlokasi di ujung jalan raya, jalan al-Mahdi, Kota Kairo, ibukota Mesir. Najib Mahfudz, sastrawan besar Mesir pemenang Nobel Sastra 1988 ini menjadikan sebuah kafe kecil ini sebagai tempat perbincangan situasi politik Mesir tahun 1967, saat menjelang dan sesudah perang melawan Israel, di Sinai.
Tahun 1967 adalah tahun yang penting bagi bangsa Mesir. Tahun-tahun itu menjadi tahun yang menentukan bagi masa depan perjuangan politik bangsa Mesir.
Saat itu bangsa Mesir sedang dalam puncak optimisme politik hendak perang melawan Israel. Spirit Sosialisme Arab yang digawangi Gamal Abdul Nasser saat itu sedang menggebu-gebu, seolah bangsa Mesir menemukan ruh nasionalisme dan revolusinya.
Sebelum itu, pada tahun 1952, Mesir mengobarkan revolusi politik dengan dipimpin oleh panglima militer revolusioner Gamal Abdul Nasser yang muak dengan situasi dekadensi kekuasaan monarki Raja Faruk. Raja Faruk ditumbangkan dengan paksa, dan garda revolusi nasionalis-sosialis menjadi penguasa dan didukung oleh mayoritas rakyat Mesir.
Bangsa Mesir di tahun-tahun setelah revolusi 1952 tersebut seolah menemukan kembali gairah kebangsaannya. Setelah sekian lama menjadi koloni Perancis dan kemudian setelah Perang Dunia Kedua jatuh ke tangan kekuasaan monarki Raja Faruk yang loyal kepada Amerika Serikat, menjadikan masyarakat Mesir semakin muak dengan situasi negerinya.
Dalam situasi masyarakat yang tak bergairah tersebutlah panglima militer Mesir yang revolusioner, Gamal Abdul Nasser bersama sekian kompi pasukannya melakukkan pemberontakan dan perebutan kekuasaan dari Raja Faruk si loyalis Amerika Serikat. Tak hanya perebutan kekuasaan semata, revolusi tersebut memiliki gagasan, yakni Sosialisme Arab.
Presiden Nasser itu layaknya Soekarno di Indoensia, mereka sama-sama nasionalis dan sosialis. Sepertinya yang membedakan mereka hanyalah latar belakangnya saja, Nasser berkarir di militer, sedang Soekarno aktivis politik sipil. Tapi dalam keduanya, ada banyak kemiripan, terutama dalam gagsannya tentang nasionalisme yang anti imperialisme dan memiliki arah kebijakan ekonomi yang sosialis, berdikari, mandiri.
Dalam situasi politik yang penuh gelora dan penuh optimisme, di tahun 1967 Mesir hendak bertempur melawan Israel di Sinai. Kenapa perang dengan Israel? Saat itu bangsa Arab, termasuk Mesir sangat muak dengan penindasan yang dilakukan Israel kepada bangsa Palestina. Israel adalah simbol imperialisme paska Perang Dunia Kedua, karena memang menjadi boneka Amerika Serikat.
Situasi Mesir saat itu menjadi pelik dan runyam, ketika optimisme mereka kandas dalam peperangan. Mesir kalah dalam perang dengan Israel. Gelora politik yang padu dalam bendera revolusi Mesir tersebut mengalami porak poranda. Rakyat mengalami kekecewaan, depresi, dan kehilangan arah.
Dalam situasi yang penuh kekecewaan dan kehilangan arah itulah, politik diberbincangkan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang di Kafe Karnak, di ujung jalan al-Mahdi, Kairo. Pemilik kedai itu adalah bernama Qurunfula, mantan bintang tari Mesir yang diusia mendekati senjanya masih berparas cantik, bertubuh menawan, dan cerdas. Qurunfula berjalin kasih dengan aktivis muda bernama Hilmi Hamada yang berideologi komunis.
Novel ini tak melulu hanya membicarakan politik, tapi dipadukan dengan kisah cinta yang menggebu-gebu, kisah cinta Qurunfula, si mantan bintang tari sekaligus pemilik kafe dengan seorang aktivis muda komunis berusia separuh usia Qurunfula, bernama Hilmi Hamada. Kisah cinta mereka berujung tragis, Hilmi Hamada akhirnya mati saat diinterogasi di penjara karena dianggap kontra reolusi dan mengancam kekuasaan yang sedang sempoyongan setelah kalah perang.
Kisah cinta yang lain adalah kisah cinta pasangan aktivis bernama Ismail al-Syaikh dengan kekasihnya Zainab Diyab. Keduanya adalah aktivis mahasiswa berhaluan sosialis moderat. Mereka sempat juga dipenjara karena dituduh kontra revolusi. Padahal, pada dasarnya mereka adalah pendukung penuh revolusi yang dipelopori penguasa, rezim Gamal Abdul Nasser.
Penangkapan terhadap banyak aktivis yang sebetulnya mendukung penuh revolusi dalam novel ini menampakkan bahwa situasi politik paska kekalahan perang dengan Israel tersebut dalam kondisi yang sedang tidak stabil dan saling mencurigai. Penggambaran Najib Mahfudz atas situasi penuh kecurigaan tersebut dipertegas dengan sosok Khalid Shafwan.
Shafwan adalah seorang intelektual progresif yang dulu sering nongkrong di Kafe Karnak. Akan tetapi, situasi dan kondisi politik memaksanya untuk menjadi agen kekuasaan untuk menangkap orang-orang yang dianggap kontra revolusi, seperti Hilmi, Ismail, dan Zainab.
Novel ini kecil dan berhalaman tipis, akan tetapi dapat menggambarkan situasi Mesir di tengah kekalahan perangnya melawan Israel secara epik. Antara cinta yang rumit dan politik yang sedang kehilangan optimisme dapat dipadukan secara menarik oleh Najib Mahfudz.
Membaca novel ini kita dapat meresapi penggambaran atas situasi-situasi Mesir yang penuh dengan kecurigaan tersebut. Juga dipermanis oleh kisah cinta dalam sela-sela perjuangan politik.