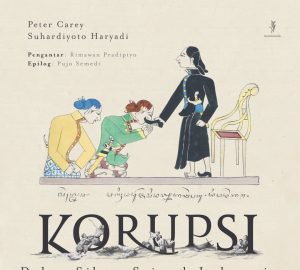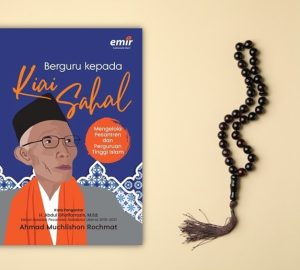Judul: Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Deandel (1808-1811) sampai Era Reformasi
Penulis: Peter Carey, Suhardiyoto Haryadi, Sri Margana
Penerbit: Komunitas Bambu
Cetak: 2017
Tebal: lxii+278 halaman
ISBN: 978-602-9402-88-9
Kita simak kutipan di Jawa Pos, 18 September 2019: “Namun, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan, ada 289 orang di antara total 560 anggota DPR yang tanda tangan. Bagi dia, tangan tangan tersebut adalah persetujuan meski anggota dewan tak hadir secara fisik. Jumlah itu, ujar Fahri, sudah mencapai kuorum sehingga rapat paripurna bisa berlanjut.” Tanda tangan itu sudah mewakili rakyat. Tanda tangan di kertas mengartikan anggota DPR bekerja serius dan tulus dalam mengesahkan revisi Undang-Undang KPK?
Peristiwa 17 September 2019, menghasilkan berita-berita dan artikel-artikel mengandung kemarahan dan sindiran. Pembaca turut dalam gejolak pelbagai berita dan artikel. DPR mencipta sejarah tak menghasilkan air mata atau pujian. Publik mustahil menangis. Peristiwa “heroik” antara DPR dan pemerintah justru memicu marah dan tawa kesakitan gara-gara misi melemahkan, menumpulkan, dan “menghancurkan” KPK. Para pembaca koran tak hadir di peristiwa itu bisa simak berita di Kompas, 18 September 2019: “Akhirnya, hari penentuan itu tiba. Hanya dihadiri secara fisik oleh 108 orang dari 560 anggota DPR dalam ruang rapat paripurna, undang-undang yang mengubah masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini disahkan juga. Meski penolakan terhadap revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengalir, DPR dan pemerintah terus melenggang melanjutkan proses dan pengesahannya.” Pihak-pihak bermusuhan dengan KPK mungkin sedang mesem dan menggelar pesta. KPK telah dipecundangi dalam kerja memberantas korupsi.
Masa depan pemberantasan korupsi terasa suram. Kita mundur untuk melihat ke masa lalu. Lakon korupsi di Indonesia memang awet sepanjang masa, belum jeda atau tamat. Sejak dulu, korupsi tetap kata memiliki arti belum terlalu berubah meski ada usaha-usaha menambahi arti akibat tata politik dan hukum mutakhir. Di Indonesia, korupsi itu istilah dari negeri jauh tapi tak asing lagi saat korupsi mulai dipergelarkan di tanah jajahan. Korupsi malah terlalu milik Indonesia, melebihi kata cuma di kamus.
Pada 1950, terbit Kamus Ilmu Politik susunan S Badhy. Kamus mungil, 200 halaman. Kamus berisi istilah-istilah dari pelbagai bahasa asing diterjemahkan dan mendapat pengertian dalam bahasa Indonesia. Di halaman 57, corruptie (korupsi) berarti “memakan jang bukan haknja.” Pengertian pendek dan jelas. Di kamus, pembaca pun memperoleh penjelasan lanjutan berlatar Indonesia masa lalu: “Karena administrasi negara belum beres sekarang banjak terdapat korupsi di djawatan-djawatan hingga merugikan rakjat dan negara.” Penjelasan milik masa 1950-an, berbeda jauh dari Indonesia abad XXI saat korupsi ada di DPR, Mahkamah Konstitusi, kabinet, BUMN, dan birokrasi di daerah-daerah.
Pada tahun-tahun mendebarkan (2018 dan 2019) korupsi malah merajalela. KPK “rajin” mengumumkan para politisi atau para peraih kekuasaan di pilkada adalah pelaku atau terlibat dalam korupsi. Hajatan demokrasi ternoda, kita berduka. Dulu, Sindhunata membahasakan penodaan oleh para koruptor itu membuktikan kerja politik di Indonesia mletho. Orang terlena di kekuasaan tapi lupa etika dan janji. Puisi berjudul “Ramalane Pasar Kembang” bercerita aib-aib kekuasaan: Yen pasar kembang ilang kumandhange,/ ngendi-ngendi paran dadi lokalisasi,/ uwong-uwong ilang isine,/ wuda mblejet nglakoni korupsi. Di mata publik, para koruptor telah pantang malu dan mengaku tak pernah bersalah, setelah mengeruk untung berlimpahan dari korupsi.
Korupsi tak mulai pada masa 1950-an atau berakhir pada 2018. Buku berjudul Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Deandels (1808-1811) sampai Era Reformasi, menuntun kita ke belakang: sejarah persemaian korupsi di Indonesia. Sejak dua abad silam, Deandels mewariskan tata cara memusuhi korupsi tapi belum mujarab. Ia dikenang sebagai pejabat revolusioner dalam pembenahan administrasi dan kerja politik, berkaitan keruntuhan VOC akibat korupsi. Peter Carey menulis: “Namun walaupun Deandels sendiri tidak ‘bersih’ dalam arti menolak tindakan yang korup, warisan sistem kepemerintahannya masih tetap dahsyat dan bergaung sampai sekarang.” Orang-orang telanjur mengenang jalan terpanjang menimbulkan korban tapi agak melupa kebijakan-kebijakan di politik untuk memusuhi korupsi.
Ingatan jauh ke belakang digenapi Sri Margana dengan sodoran masa 1970-an. Indonesia sudah berlumuran korupsi. Pada masa awal Orde Baru, Soeharto menunjuk Mohammad Hatta sebagai penasihat presiden dalam usaha memberantas korupsi. Hatta justru menemukan korupsi hampir kelaziman. Indonesia berusia seperempat abad tapi korupsi sudah mengakar dan menumbuhkan masalah-masalah rimbun sulit dipangkas atau dirubuhkan. Korupsi sudah meninggalkan urusan etis-moral di kalangan elite politik.
Sri Margana pun ada di simpulan bahwa akar historis-sosiologis untuk lakon korupsi sudah ditemukan sejak ratusan tahun silam, mungkin lebih ke belakang dari masa kebangkrutan VOC pada abad XVIII. Masa lalu tak jua bersih saat bersambungan ke Indonesia masa revolusi dengan titik terpenting 1945. Politik sulit stabil mempengaruhi pembesaran korupsi. Di kalangan sinis, Indonesia itu mentas dari penjajahan untuk “dimamah” para koruptor setiap hari, tak mengenal cuti atau libur panjang.
Ingatan pada puluhan tahun lalu, Suhardiyoto Haryadi menata lagi kebijakan-kebijakan memberantas korupsi: keberhasilan dan penghambatan. Pembentukan KPK agak memberi janji pembersihan noda-noda di Indonesia. Kasus demi kasus diungkap memunculkan tokoh-tokoh besar dan moncer. Orang-orang ingin daftar koruptor pendek saja. Keinginan itu belum terkabul. Daftar malah bertambah panjang sampai pada hajatan demokrasi 2019. Korupsi belum reda di pelbagai institusi. Korupsi cenderung berkaitan ambisi-ambisi elite dan partai politik dalam ongkos berdemokrasi. Selebrasi demokrasi gagal menebar makna kemuliaan. Korupsi berdalih demokrasi itu penistaan dan penghancuran masa depan Indonesia.
Buku berpenampilan apik terbitan Kobam bukan mengundang pembaca untuk takjub pada Indonesia: dulu dan sekarang. Pembaca “dijatuhkan” ke kubangan terkotor hasil ciptaan para koruptor, dari masa ke masa. Buku menguak ingatan-ingatan agak memberi pesimis mengenai Indonesia masa sekarang atau esok hari. Pada saat buku di hadapan sidang pembaca, berita-berita pengungkapan kasus korupsi mendahului memicu marah dan senewen berkepanjangan. Kita pun membaca buku berharap menumpas ragu, kalimat demi kalimat dan alinea demi alinea tak melupa. Begitu.