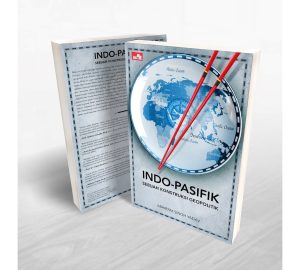Pemerintah bertugas mengenalkan dan mengumumkan para pahlawan dengan menerbitkan buku-buku. Pelaksanaan upacara, pidato, dan ziarah ke makam pahlawan, dan untuk peringatan Hari Pahlawan perlu digenapi penerbitan buku-buku bertema pahlawan sesuai misi penguasa.
Pada masa lalu, buku-buku keluaran pemerintah menjadi acuan pembelajaran dan penghormatan pada pahlawan. Jumlah pahlawan terus bertambah berarti penulisan dan penerbitan buku tak pernah sempurna.
Buku demi buku mesti dikerjakan agar jutaan orang menambah pengetahuan tentang pahlawan. Setiap tahun, pahlawan mengisi halaman-halaman baru dalam terbitan buku sejarah atau biografi.
Pada 1953, Kementerian Penerangan Republik Indonesia menerbitkan buku berukuran besar dengan judul Pahlawan Kemerdekaan. Di sampul buku, pembaca melihat gambar para pahlawan. Judul dan gambar-gambar di sampul buku gamblang menebar pesan agar pembaca meneladani para pahlawan berlatar perjuangan meraih kemerdekaan. Para pahlawan itu tak cuma gambar tapi biografi heroisme, pengorbanan, derita, dan kemuliaan.
Di halaman 1, pembaca diajak merenung dengan kalimat agak puitis: “Republik Indonesia jang kita miliki sekarang adalah berurat-akar dari masa jang silam, silih-ganti telah lahir pemimpin-pemimpin diseluruh tanah air jang membela dan mempertahankan hak-hak rakjat dalam zamannja masing-masing.”
Sebutan pahlawan mendapat sinonim keren. Pembaca digoda berimajinasi tentang para pahlawan dan Indonesia: “Mereka menabur benih dan buahnja kita petik pada hari ini, dengan perumpamaan lain, mereka adalah arsitek dan pembina pundamen dari Gedung Republik Indonesia jang kita miliki sekarang.”
Pahlawan itu “arsitek”, tak selalu terimajinasi sebagai tokoh memegang keris, pedang, bedil, tombak, atau bambu runcing. Sebutan “arsitek” mungkin diinginkan berarti serius dan mentereng. Indonesia itu “gedung”, perumpamaan beraroma modernitas!
Pemerintah mengenalkan 17 pahlawan, dijelaskan secara ringkas dan tersaji impresif melalui gambar-gambar. Kita mengandaikan pada masa lalu orang-orang belum mengakrabi foto atau gambar para pahlawan. Penerbitan buku bergambar bisa membuat orang mengingat wajah dan penampilan para pahlawan.
Ingatan itu kadang baku akibat pembaca tak mendapat jumlah gambar melimpah. Kita masih ingat bahwa Pangeran Diponegoro itu berjubah dan bersorban; Ahmad Dahlan memakai kacamata; Kartini pasti berkebaya; WR Soepratman mengenakan jas, peci, dan kacamata; Tjipto Mangoenkoesoemo tentu berblangkon; Tjokroaminoto berkumis lancip; Wahidin Soediro Hoesodo khas dengan baju lurik dan blangkon.
Buku terbitan pemerintah itu berketebalan 36 halaman. Buku berslogan: “Pahlawan pergi meninggalkan djasa.” Buku apik meski cuma hitam-putih. Barangkali buku itu permulaan dari propaganda pemerintah mengenalkan para pahlawan melalui perbukuan.
Bagi para murid, buku bergambar dan penjelasan ringkas menggampangkan rasa ingin mengerti Indonesia melalui biografi para tokoh, sejak abad XIX sampai masa kemerdekaan. Buku itu jadi warisan penting dari masa kekuasaan Soekarno.
Rezim Orde Lama tamat, berganti ke rezim Orde Baru dengan penguasa bernama Soeharto. Penerbitan buku-buku bertema pahlawan tetap diadakan meski agak berbeda corak dari edisi buku masa lalu. Buku berjudul Pahlawan Kemerdekaan Nasional diterbitkan Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1967. Tebal 92 halaman.
Pemerintah mengisahkan 8 pahlawan: Abdul Muis, Kartini, Tengku Tjik Di Tiro, Soerjopranoto, Ki Hadjar Dewantara, Douwes Dekker, Wahidin Soedirohoesodo, dan Sam Ratulangi. Departemen Penerangan memberi pengakuan: “Kita mejakini bahwa riwajat hidup dan perdjuangan daripada mereka merupakan sifat-sifat chusus mereka dalam hal pengorbanan untuk kepentingan bangsa atau generasi jang akan datang, untuk kita menghargainja dengan mengambil sari tauladannja…”
Buku berfungsi menghormati jasa para pahlawan. Menjadi bacaan publik agar mengingat dan meneladani pahlawan.
Buku cenderung memihak ke kalimat-kalimat ketimbang gambar. Pembaca bisa mengetahui biografi pahlawan, sejak lahir sampai meninggal. Peristiwa-peristiwa penting diceritakan secara dramatis meski pembaca tak mendapat halaman daftar pustaka atau sumber data pengisahan.
Buku itu terasa puitis dan reflektif dengan pengutipan nasihat Tjipto Mangoenkoesoemo: “Serahkanlah dirimu pada pekerdjaan jang mendjadi kebahagiaan anak-tjutju kita, agar supaja turunan kita tidak akan mengatakan bahwa kita telah hidup tidak berguna.” Kita jadi insaf bahwa kepahlawanan bermisi kebahagiaan. Para pahlawan ingin Indonesia berbahagia.
Rezim Orde Baru rajin menerbitkan buku-buku bertema pahlawan. Buku terpenting diterbitkan oleh Departemen Sosial, menggantikan peran Departemen Penerangan. Pada 1971, terbit buku berjudul Pahlawan Pembela Kemerdekaan susunan Badan Pembina Pahlawan Pusat. Pimpinan redaksi penggarapan buku adalah Nugroho Notosusanto.
Tampilan buku tak menarik. Sampul buku tak bergambar. Tebal 108 halaman. Biografi 16 pahlawan diperkenalkan pada pembaca agar semakin mengerti patriotisme dan sejarah capaian kemerdekaan. Nugroho Notosusanto berpesan: “Hakekat kepahlawanan adalah suri-tauladan jang dihadapkan kepada generasi-generasi jang mendatang untuk mereka djadikan pegangan dan sumber inspirasi.”
Kalimat bijak tapi klise. Kalimat mengejutkan justru diberikan oleh HMS Mintardja selaku Menteri Sosial Republik Indonesia: “Penjusunan buku ini… pekerdjaan jang sungguh berat dan mulia karena jang disedjarahkan adalah mereka-mereka jang membuat sejarah.”
Dua rezim kekuasaan memiliki taktik sama dalam mengenalkan para pahlawan. Penerbitan buku-buku menjadi andalan. Perbedaan terletak pada pilihan pahlawan untuk diceritakan, pijakan ideologis buku, penentuan tim redaksi, dan struktur buku.
Kita tentu mewarisi buku melimpah garapan rezim Orde Baru ketimbang Orde Lama. Pada masa Soeharto berkuasa, buku-buku telah ditetapkan sebagai senjata paling ampuh dalam membentuk atau membakukan sejarah sesuai selera penguasa. Begitu.