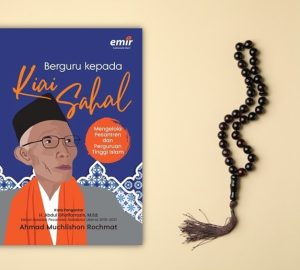Judul: Ulama Perempuan Madura (Otoritas dan Relasi Gender)
Penulis: Hasanatul Jannah
Penerbit: IRCiSoD
Tahun: Cetakan Pertama, Oktober 2020
Tebal: 344 halaman
ISBN: 978-623-7378-83-9
Selama ini, tidak banyak peneliti yang melakukan kajian secara mendalam tentang bagaimana peran yang dilakukan seorang nyai (perempuan ulama). Barangkali karena nyai dipandang tiada beda dengan perempuan-perempuan lain yang hanya berperan dalam wilayah domestik saja. Karenanya tak ada yang menarik bagi peneliti untuk dikaji. Perlu diketahui, yang dimaksud dalam hal ini bukan nyai dalam pengertian masa kolonial yang banyak menjadi gundik, melainkan istri atau anak perempuan dari seorang kiai.
Sebaliknya, kita tidak kesulitan untuk menemukan kajian sebagai refrensi akan sosok seorang kiai. Bagaimana kiprahnya mengasuh pesantren, aktif di organisasi sosial keagamaan, melakukan dakwah di tengah-tengah masyarakat, terlibat dalam dunia politik dan lain sebagainya. Sebut saja misalnya kajian yang telah dilakukan Hiroko Horikoshi, Clifford Geertz, Pradjarta Dirdjosanjoto sampai Zamakhsyari Dhofier.
Minimnya kajian akan peran sosok nyai makin mengokohkan pandangan patriarki. Bahwa perempuan harus ditempatkan di bawah kuasa dan kendali laki-laki dalam setiap lini kehidupan. Karena perempuan adalah makhluk yang lemah, tidak kreatif, dan minus akal. Selain itu juga berpengaruh terhadap citra pesantren dan agama Islam pada umumnya, sebagai institusi dan agama yang menomorduakan perempuan.
Zamakhsyari Dhofier, misalnya, menyebut elemen-elemen dasar pesantren adalah pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kiai. Dalam kajiannya, Dhofier tidak memasukkan nyai sebagai elemen penting dalam pembentukan dan pengembangan tradisi pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa nyai dipandang sebagai sosok yang tidak memiliki kemampuan (baik pengetahuan, sosial, dan spiritual) dalam dunia pesantren.
Nah, di tengah minimnya kajian terhadap peran nyai itulah buku yang ditulis Hasanatul Jannah ini begitu berarti. Dalam amatannya, nyai dalam dunia pesantren tidak hanya sekedar menjadi pendamping kiai yang hanya berkutat dalam urusan domestik. Akan tetapi, nyai juga berperan aktif di dalam mengembangkan pesantren, berdakwah, dan menjadi tumpuan masyarakat untuk memecahkan pelbagai persoalan sosial keagamaan.
Buku ini berfokus pada sepak terjang dari empat sosok nyai di Madura. Di antaranya adalah Nyai Aqidah Usmuni, Nyai Khairiyyah, Nyai Sifak Thabroni, dan Nyai Muthmainnah. Keempat sosok nyai yang merupakan representasi dari empat kabupaten di Madura ini, seperti dinyatakan di atas, memiliki peran yang signifikan. Baik di dalam pesantren maupun di tengah-tengah masyarakat.
Nyai Aqidah Usmuni, misalnya, di Kabupaten Sumenep merupakan satu-satunya nyai yang tidak hanya membantu pengembangan pesantren, melainkan mendirikan, memimpin dan mengelola pesantren sejak tahun 1985. Sampai saat ini, telah berdiri pendidikan formal mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi. Santri yang diasuh mencapai angka 500-an, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Hal yang unik lagi adalah penamaan pesantren yang dinisbatkan kepada sang pendiri, yakni Aqidah Usmuni. Sesuatu yang tidak lazim, karena pada umumnya nama pesantren cenderung dilekatkan pada nama kiai sebagai suami, ayah maupun kakek.
Motivasi Nyai Aqidah mendirikan pesantren, sebagaimana diurai dalam buku ini, lahir dari keprihatinan akan minimnya akses pendidikan karena beban biaya yang tak mudah dijangkau. Kondisi demikian ditopang dengan pandangan yang cenderung melanggengkan terpinggirkannya anak perempuan terhadap pendidikan. Anak perempuan dianggap tidak perlu memeroleh pendidikan yang tinggi karena wilayahnya hanya di seputar dapur, sumur, dan kasur.
Nyai Aqidah tidak hanya mengurus pesantren tapi juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial keagamaan. Dengan mengasuh beberapa majelis pengajian di pelosok-pelosok desa. Bahkan, tidak jarang Nyai Aqidah menjadi juru damai dalam rumah tangga yang hampir retak karena dipicu adanya KDRT.
Nyai di Madura, dalam amatan Hasanatul Jannah, tidak hanya aktif dalam lingkungan pesantren dan kegiatan sosial keagamaan. Mereka juga memberikan pemahaman akan relasi gender, hak-hak perempuan, pentingnya pendidikan bagi perempuan, dampak pernikahan dini, dan hal-hal lain terkait. Tentu memberikan pemahaman akan itu semua kepada masyarakat bawa tidak mudah. Maka, dibutuhkan strategi dan kecakapan komunikatif.
Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan Nyai Khairiyyah. Untuk meminimalisir pernikahan dini, Nyai Khairiyyah menetapkan peraturan bahwa santri-santrinya tidak boleh menikah (minimal) sebelum lulus Madrasah Aliyah. Sebelum peraturan tersebut dibuat, di tengah kegembiraan anak-anak mencari ilmu, banyak orang tua yang menjemput paksa anak-anaknya untuk dinikahkan.
Dari mana sumber otoritas nyai di Madura hingga mereka begitu ‘leluasa’ berperan dalam ranah publik, seperti keempat nyai tersebut di atas? Dalam temuan Hasanatul Jannah setidaknya ada tigal hal yaitu, penguasaan yang mendalam akan ilmu-ilmu agama, kekuatan pangaroh, dan faktor genealogis. Di antara tiga sumber tersebut, sebab yang terakhir sepertinya lebih dominan.
Bagi masyarakat Madura, faktor genealogis lebih diutamakan dibanding dengan penguasaan mendalam akan ilmu agama. Seberapa pun tinggi pencapaian seseorang terhadap ilmu-ilmu agama tetapi bukan keturunan kiai/nyai, sulit baginya memeroleh otoritas di tengah-tengah masyarakat. Jika seseorang yang berasal dari keluarga kiai/nyai, baik laki-laki maupun perempuan, berperilaku di luar kebiasaan pada umumnya akan mendapat pemakluman. Dan empat dari nyai yang perannya diurai dalam buku ini berasal dari keluarga kiai/nyai.
Bagi saya, nyai di Madura, sebagaimana juga kiai, tidak menemukan hambatan yang cukup berarti untuk berperan dalam ranah publik maupun memberikan pemahaman akan emansipasi perempuan. Karena pertama, perempuan pada umumnya dalam pandangan orang Madura lebih banyak ditempatkan dalam posisi yang “setara”. Contoh, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya sendiri maupun keluarganya, perempuan Madura bebas beraktifitas di luar rumah (dalam amatan Hasanatul Jannah, hal ini hanya terjadi pada perempuan yang dikategorikan sebagai perempuan kenek/dumeh). Kedua, seperti di sebut di atas bahwa nyai menempati kedudukan tinggi dalam strata sosial masyarakat Madura. Segala ucapan dan tindakan seorang nyai akan menjadi rujukan, termasuk dalam hal pentingnya emansipasi perempuan. Karena itu, faktor individu seorang nyai adalah penentu akan relasi gender yang sehat di Madura.
Walaupun hal itu butuh proses. Karena Madura bukan wilayah yang seratus persen bebas dari pandangan-pandangan patriarki. Akan tetapi, peluang untuk terwujudnya relasi gender yang sehat di Madura terbuka lebar. Apalagi dimotori oleh orang-orang yang ‘berdara biru’.
Respon kalangan kiai saja, sebagaimana diurai dalam buku ini, terhadap nyai yang berperan dalam ranah publik terbelah menjadi dua kategori, yakni kiai konservatif dan kiai moderat. Yang dimaksud dengan kiai konservatif adalah kiai yang memberikan batasan-batasan terhadap peran dan kiprah nyai, baik dalam tatanan sosial, keagamaan, ekonomi, bahkan politik. Walaupun kiai dalam kategori ini tetap berharap kontribusi nyai dalam membantu penataan pondok pesantren, sosial kemasyarakatan, namun dalam batas tertentu tanpa mengungguli kapasitas kiai.
Sedangkan kiai moderat lebih responsif terhadap peran yang dialkukan nyai dalam ranah publik. Karena mereka rerata memiliki kesadaran tafsir kontemporer dan memiliki wawasan keilmuan dalam berbagai disiplin. Artinya, kiai dalam kategori ini tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga disiplin keilmuan lain.
Yang ganjil dari buku ini adalah pemberian judul Ulama Perempuan Madura. Sebab, jika kita mengacu pada hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 2017, istilah “perempuan ulama” berbeda dengan “ulama perempuan”. Istilah pertama menunjuk kepada semua orang yang berjenis kelamin perempuan dan memiliki kapasitas keulamaan, baik yang sudah memiliki perspektif keadilan gender maupun belum. Sementara, “ulama perempuan” menunjuk kapada semua ulama, baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki dan mengamalkan perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan atau gender.
Maka, jika memakai istilah ulama perempuan, yang diurai seharusnya bukan hanya nyai yang dapat dikategorikan sebagai ulama. Tetapi siapa pun ulama di Madura, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki pemahaman dan bekerja secara intelektual maupun praktikal dalam mengintegrasikan keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman.
‘Ala kulli hal, buku ini tidak hanya menyumbang akan kekosongan kajian terhadap peran nyai dalam lingkungan pesantren. Tetapi juga membuka mata kita bahwa sosok nyai begitu berarti. Karena mereka adalah ulama (pewaris nabi) yang juga memiliki tanggung jawab melaksanakan misi kenabian untuk menghapus segala kezhaliman sesama makhluk atas dasar apapun.