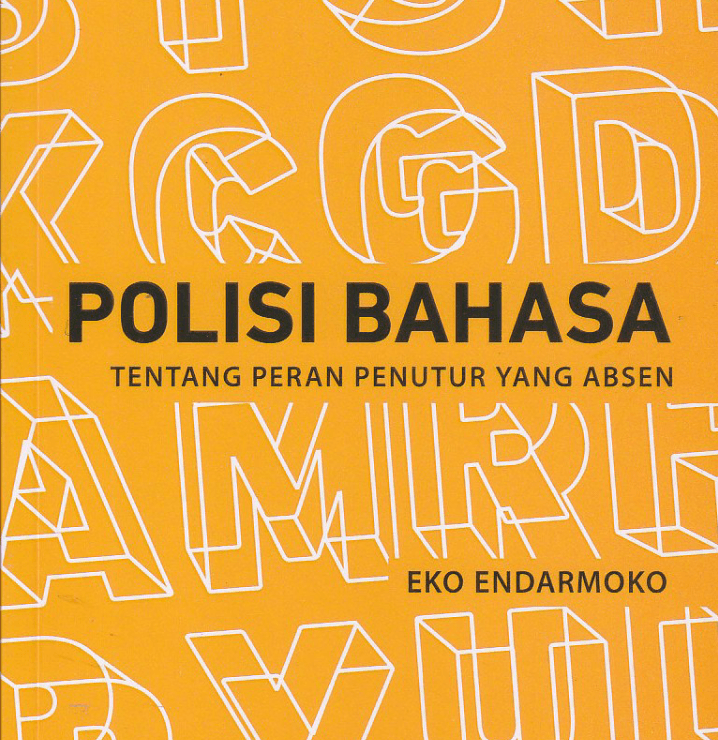Judul: Polisi Bahasa: Tentang Peran Penutur yang Absen
Penulis: Eko Endarmoko
Penerbit: Kompas
Cetak: Pertama, 2019
Tebal: xx+236 halaman
ISBN: 978-602-412-696-4
Suatu kesalahan yang sulit direvisi di bulan Ramadan tapi tidak menimbulkan efek dosa secara teologis, adalah ucapan: “Selamat Menjalankan Ibadah Puasa.” Dari penutur awam sampai komersial tidak merasa perlu ada yang diperbaiki agar tidak menimbulkan aib kebangsaan. Kesalahan ini menjadi salah satu dari 60 tulisan editor dan pakar bahasa, Eko Endarmoko, yang dihimpun dalam kumpulan esai bahasa berjudul Polisi Bahasa: Tentang Peran Penutur yang Absen (Kompas, 2019). Eko mengimajinasikan ibadah puasa, yang “dijalankan” bukannya “dijalani”, sanggup bergerak ibarat benda-benda padat. Obyek setelah kata kerja berakhiran /-kan/ mestinya bergerak. Eko mencontohkan; melemparkan batu, menaikkan koper, atau menjalankan motornya.
“Menjalankan ibadah puasa” yang seharusnya “menjalani ibadah puasa” hanyalah salah satu tulisan yang bernaung di subjudul “Soal Klise”. Di sini, Eko juga membabarkan persoalan “merupakan”, peribahasa, Indonesia yang banyak dalam kalimat “Dirgahayu HUT Kemerdekaan RI ke-73, dan lain-lain. Masih ada tiga subjudul (“Bahasamu Kastamu”, “Keder”, “Kasus Ajaib”) yang membawa pembaca memikirkan ulang bahasa Indonesia dan peran manusia Indonesia sebagai penutur pasti bahasa Indonesia. Sedikit mengingatkan pada jargon Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud yang terus mengajukan optimisme saat bahasa Indonesia dianggap terancam, “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing.”
Perkara bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ternyata masih juga meresahkan Eko. Pengalaman kecil singgah di Stasiun Manggarai mengawali tulisan “Lagak”. Eko melihat seorang ibu muda berucap tegas, “No! No! No!” kepada anak yang terlalu aktif berlari. Di gerai roti, seorang penjaga kasir lebih memilih mengucapkan black coffee (kopi hitam) dan beef (daging sapi). Ada kompleks rendah diri dalam lagak memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, ingin pamer dan dipandang terpelajar. Padahal jelas, ruang penemuan Eko atas kejadian berlagak ini bukan lingkungan secara status sosial-kebahasaan mentereng.
Para penutur diwakili ibu muda (biasa) dan penjaga kasir merepresentasikan kelas sosial yang cenderung rendah dibandingkan misalnya pengusaha, artis, dosen, mahasiswa, atau koki restoran. Kalau Eko sempat menonton suatu tayangan kompetisi memasak di salah satu televisi swasta, dia pasti lebih prihatin. Para juri dan peserta lomba mengaduk-aduk bahasa seperti benar-benar tidak sanggup menyimpan ragam kosakata bahasa Indonesia di kepala bahkan untuk kata-kata paling sederhana di dunia santapan sekalipun; onion, fish, tomato, black pepper, chicken, butter, over cook, sauce, plating. Dalam satu kalimat terucap, bisa dipastikan separonya berbahasa Inggris. Publik mungkin tidak akan sempat menghakimi tindakan para juri sebagai peremehan bahasa Indonesia atau berlagak. Mereka chef terkenal lho, wajar saja berlagak! Campur-campur bahasa telah mengalami pengaburan status sosial para penutur.
Lisan atau Tulisan
Tulisan-tulisan Eko menciptakan tarik ulur antara penutur lisan dan pengguna tulisan, siapakah tertuntut untuk lebih mematuhi kaidah tata bahasa. (Penutur) bahasa tulis biasanya lebih memiliki beban moral menguasai ketepatan berbahasa karena tulisan berkesan lebih ilmiah, baku, atau memiliki jangka waktu lebih panjang untuk dilihat. Bahkan meski telah berusia sekian tahun, tata bahasa tulis masih bisa diperdebatkan. Orang yang menulis dan tulisan lebih dituntut menguasai tata bahasa baku. Bandingkan dengan bahasa lisan yang seketika terkatakan, cenderung sulit dipermasalahkan. Penutur lisan cenderung tidak perlu merasa harus bercakap-cakap secara sistematis, terkontrol, dan tentu baku asal pesan tersampaikan.
Baku tak baku dalam kelisanan salah satunya dibahas Eko lewat esai “Bulé Berkundai dan Saté Petai” yang mempermasalahkan pola kata berakhiran /é/ (e taling) yang masuk dalam ragam baku dan diftong /ai/ yang dianggap baku seperti, balé-balai, cabé-cabai, capé-capai. Masalahnya, ada ketidakkonsistenan dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang sama-sama memasukkan bule-bulai dan konde-kundai pada halamannya yang gembrot. Eko mengajukan pertanyaan, “Apakah dasar pertimbangan bahwa bentuk dari ragam lisan dan percakapan berpeluang sangat tipis, atau malah sama sekali tidak bisa, menyandang status baku? Dari mana pula orang tahu bahwa bentuk yang baku adalah yang berakhiran diftong /ai/? Padahal tadi kita sudah melihat, bulé dan kondé dicatatkan ke dalam kamus besar itu bersama-sama bulai dan kundai.” Dengan mengabaikan kamus sekalipun, orang biasanya lebih spontan mengucapkan cabé, peté, saté, capé(k). Polisi bahasa bakal kewalahan menghadapi spontanitas bahasa berjamaah tak baku ini, bukan?!
Meski Eko terlanjur memilih judul buku yang agak seram, Polisi Bahasa, tetap saja nasib bahasa kita bukan bergantung pada pihak yang terdengar berotoritas menegakkan hukum bahasa seperti “polisi” dalam pengertian secara harfiah. “Polisi bahasa yang baik, saya kira tahu persis beda dirinya dari polisi di bawah korps Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sama sekali tak punya kewenangan memaksa, atas nama hukum (bahasa) sekalipun,” begitu tulisan Eko di esai “Polisi Bahasa”. Polisi bahasa tidak usah terlalu cerewet. Penutur biar bertindak mengusahakan bahasa Indonesia sebagai peristiwa eksistensial berbangsa. Oh!
Dibandingkan di buku sebelumnya, Remah-remah Bahasa: Perbincangan dari Luar Pagar (Bentang, 2017), esai-esai bahasa di Polisi Bahasa: Tentang Peran Penutur yang Absen memang lebih pendek, temanya sederhana, dan ringan. 50 tulisan di buku semula tampil rutin rubrik “Tabik” di laman Beritagar.id sejak Oktober 2017 sampai September 2018 dan 10 sisanya tersebar di Kompas, Tempo, dan Majas. Tulisan sepertinya menyesuaikan alam pembaca digital yang lebih beragam-berkecepatan sekaligus memenuhi kapasitas mata menatap layar gawai. Mari belajar bahasa (Indonesia) dengan mudah dan gaul! Tapi tetaplah awas polisi, hati-hati berbahasa ya!