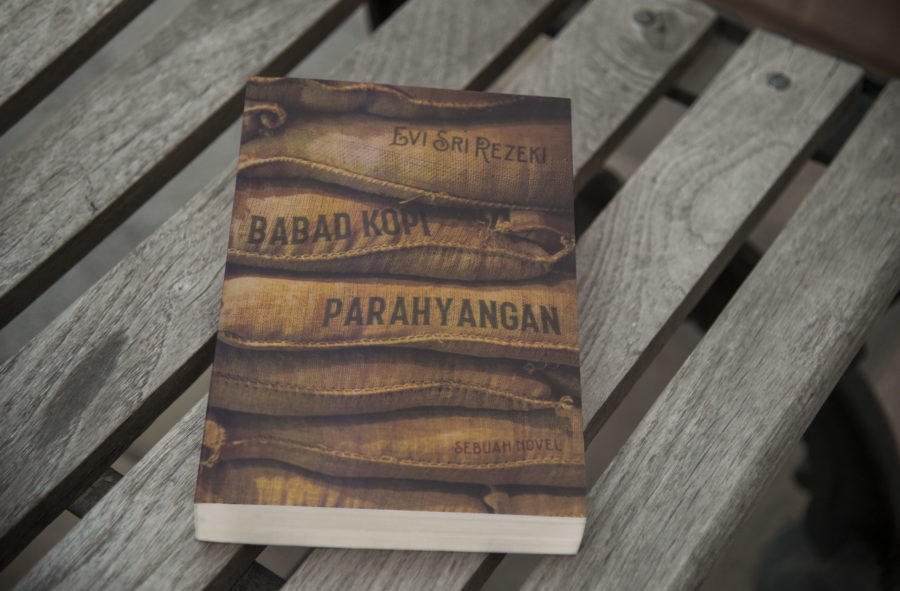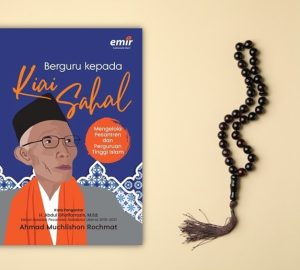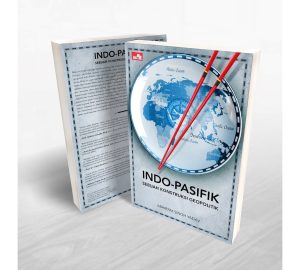Judul : Babad Kopi Parahyangan
Penulis : Evi Sri Rezeki
Penerbit : Marjin Kiri
Cetak : 2020
Tebal : 348 halaman
ISBN : 978 979 1260 96 1
Di sekitar kopi, ada makian, bualan, patah hati, dan revolusi. Kopi bermasa lalu di Indonesia, sejak 1950-an sampai 1970-an. Kopi mengental di gubahan-gubahan teks sastra, mungkin teringat atau luput dari percakapan, setelah buku-buku puisi mengenai kopi terus terbit. Kita mungkin jenuh. Mundurlah ke masa lalu. “Kau bagiku bukan tukang kopi, Mira,” ucap Awal pada perempuan pujaan. Semua bermula di kedai kopi. Utuy T Sontani dalam buku drama berjudul Awal dan Mira (1959) memberi keterangan: “Jang dimaksudkan kedai kopi kepunjaan Mira itu sebenarnja serambi muka dari rumah Mira jang dibangun djadi kedai kopi. Dan rumah Mira itu rumah bambu, ketjil tapi masih baru, letaknja menghadap ke djalan, didirikan diatas bekas reruntuhan rumah batu jang hantjur oleh peperangan, terpentjil djauh dari keramaian.”
Mira adalah tukang kopi. Kejadian pada 1951 saat Indonesia masih gonjang-ganjing oleh politik dan pemulihan dari petaka-petaka revolusi. Di situ, ada kopi. Perkataan Mira: “Dari itu alangkah bahagianja aku djadi tukang kopi, sebab dari belakang dagangan ini aku dapat melihat orang-orang jang tidak beres seperti kalian!” Si pembuat cerita memberi maklumat zaman tak beres. Kita membaca di masa berbeda, menonton masa lalu itu kopi dan daftar kutukan masa 1950-an. Revolusi memberi duka. Buku itu tertinggal di masa lalu meski orang-orang membuat peringatan 100 tahun Utuy T Sontani. Kini, kita bertemu prosa baru berjudul Babad Kopi Parahyangan gubahan Evi Sri Rezeki. Cerita berlatar abad XIX, menguak sejarah kolonial dan kopi.
Di sebuah kedai, orang-orang minum dan mendapat pengisahan kopi. Si Pelaut, tokoh memiliki informasi perdagangan kopi di dunia berbagai kata-kata mengandung cemooh dan sesalan. Ia mengabarkan bahwa kopi-kopi diminum orang-orang di Belanda atau Eropa berasal dari Parahyangan. Di novel, kita membaca penjelasan: “Sebetulnya semua orang tahu kalau Kompeni mereguk habis kopi dari seluruh penjuru Nusantara tapi mereka berlagak bodoh.” Kita lekas digeret ke masa lalu. Di hadapan kita, tokoh-tokoh dan perkebunan kopi. Pembaca tak sedang diajak minum kopi dalam kemanjaan atau kenikmatan di waktu senggang. Novel itu memuat tragedi-tragedi pahit melebihi rasa kopi.
Parahyangan itu “sarang mutiara hitam” alias kopi akibat muslihat dalam perjanjian dagang. Tanah subur menjadi sumber pendapatan besar bagi pemilik modal dan pejabat, menimpakan sengsara ke petani dan buruh. Kopi-kopi memberi “kepahitan” tapi menghasilkan untung berlimpahan di Eropa. Segala berita dan cerita mengawali peran tokoh bernama Karim memiliki janji terlibat dalam “roman” pahit kopi di Parahyangan. Ia merantau dari Sumatra. Segala hal direnungkan demi kesanggupan menanggung risiko dan raihan pengertian kopi. Ia bergerak sampai ke perkebunan kopi. Tokoh ditampilkan memiliki kemampuan baca-tulis, terbaca berani dan “terpelajar”. Ia memulai perjalanan dengan keinsafan seperti tercantum dalam novel: “Ia akan menulis risalah kopi dengan Melayu sebab akan ia persembahkan kepada anak-cucu yang kelak entah berpijak berkiblat di mana.” Ambisius!
Parahyangan, tempat terceritakan melalui kebijakan para penguasa. Kebijakan penananaman dan perdagangan kopi ditentukan perintah-perintah penguasa. Para bupati dan petani diwajibkan patuh bila tak mau mendapat hukuman-hukuman berat. Evi Sri Rezeki memberi “pengantar” ke pembaca agar tak tersesat di cerita atau mendekam di buku-buku sejarah. Van den Bosch, nama penting dalam sejarah. Tokoh memiliki pemikiran “manis beracun” untuk membuat Nusantara sengsara berkepanjangan. Pembaca berhenti sejenak di keterangan sejarah dinamakan Cultuur-stetsel. Novel mengisahkan kopi mendapat sokongan keterangan-keterangan sejarah, memikat pembaca ke masa lalu bisa dipertanggungjawabkan mengacu data-data sejarah.
Jawa itu sumber (paling) menguntungkan Belanda. Kita menerima konklusi itu melalui kebijakan-kebijakan ekspor pelbagai komoditas dihasilkan di Jawa. Parahyangan tentu masuk dalam perhitungan laba. Jawa menguntungkan terbaca dalam buku berjudul Sistem Tanam Paksa di Jawa (2003) garapan Robert van Niel. Di hadapan novel, kita melulu berpikir bahwa Parahyangan “terlalu” menguntungkan bagi pengusaha dan pejabat mata duitan. Parahyangan pun tempat berpetaka saat orang-orang diperintah, dipatuhkan, dan dihukum dalam capaian-capaian produksi kopi. Sejarah itu berlinangan air mata dan berdarah. Novel tak meluputkan jalinan asmara dan lakon keluarga, berharap pembaca tak berjalan “lungkrah” menuju sejarah.
Kita ke sejarah melalui lakon keluarga Adang (Asep). Tokoh bercerita asal usul “kepahitan” hidup: “Pada masa itu, Kompeni telah merangsek ke tanah Parahyangan setelah menundukkan Kerajaan Mataram yang kemudian menghadiahi Kompeni sebagian besar pedalaman Tatar Sunda. Ketika kopi hasil tanah Jawa dinilai berkualitas tinggi, Kompeni menyuburkan tanaman itu sampai kaki pedalaman. Siapa menetap ketiban beban mengurusi kopi.” Sejarah membawa kesengsaraan seperti datang mendadak, memberi pilihan dilematis pada kaum bumiputra. Kalimat penting dicantumkan pengarang agar pembaca mengerti sejarah: “Buah kopi adalah lambang penaklukan dan angkar di tanah Sunda.”
Tokoh-tokoh bumiputra dalam novel gubahan Evi Sri Rezeki di babak “menghinakan” dan “mematikan”. Halaman demi halaman, kita membaca nasib petani atau warga desa mendapat “kutukan” dari pemujaan laba kopi. Kita mampir ke buku garapan Haryoto Kunto berjudul Wajah Bandoeng Tempo Doeloe (1984). Cultuur-stetsel (1831-1870) menghasilkan untung 823 juta gulden. Kopi menjadi sumber keuntungan besar. Sejarah kopi di Parahyangan selalu teringat dalam lagu rakyat. Kunto memberi kutipan: Dengkleung dengdek, buah kopi raranggeuyan. Ingkeun anu dewek ulah pati diheureuyan (Dengkelung dengdek, buah kopi bertangkai-tangkai. Biarkan, itu milik saya, jangan sering diganggu).
Tokoh menggetarkan dalam novel adalah pasangan Karim dan Euis. Mereka membela martabat dan menginginkan kopi itu “membahagiakan”, bukan memberi sengsara-sengsara pada bumiputra. Perlawanan dan siasat mendapatkan hidup pantas berhadapan dengan pejabat dan orang-orang mata duitan. Euis pun “terpelajar”, memiliki kemampuan baca-tulis. Dua tokoh “terpelajar” itu bermufakat mengubah nasib dan alur sejarah di Parahyangan. Semua gara-gara kopi. Karim semakin terpicu setelah membaca Max Havelaar gubahan Multatuli. Buku terdapat di pejabat pribumi bertugas mengelola perkebunan. Membaca itu sebagai “hukuman” mengobarkan perlawanan.
Dua tokoh menentukan “kemenangan” meski ada pengorbanan dari para petani. Hari-hari buruk dilalui demi pemenuhan janji bahwa kopi itu mesti membahagiakan. Sengsara harus usai. Pada 1876, Karim membuat catatan harian dalam episode berbeda setelah merampungi “kutukan” di perkebunan kopi. Deskripsi pengarang membuat pembaca mengalami kelegaan sejarah: “Karim menghirup aroma kopi yang manis lembut dari gelas bambu. Cairan berwarna cokelat kehitaman itu membasahi lidah, langit-langit mulut, mengalir ke tenggorokan. Racikan kopi buatan Euis terasa begitu nikmat. Ia nyalakan rokoknya, terdengar bunyi keletak-keletik tembakau terbakar ketika ia mengisap dalam.” Kopi itu kenikmatan bagi orang-orang di Parahyangan, setelah raihan untung berlimpahan bagi Belanda.
Buku Babad Kopi Parahyangan layak dibaca.