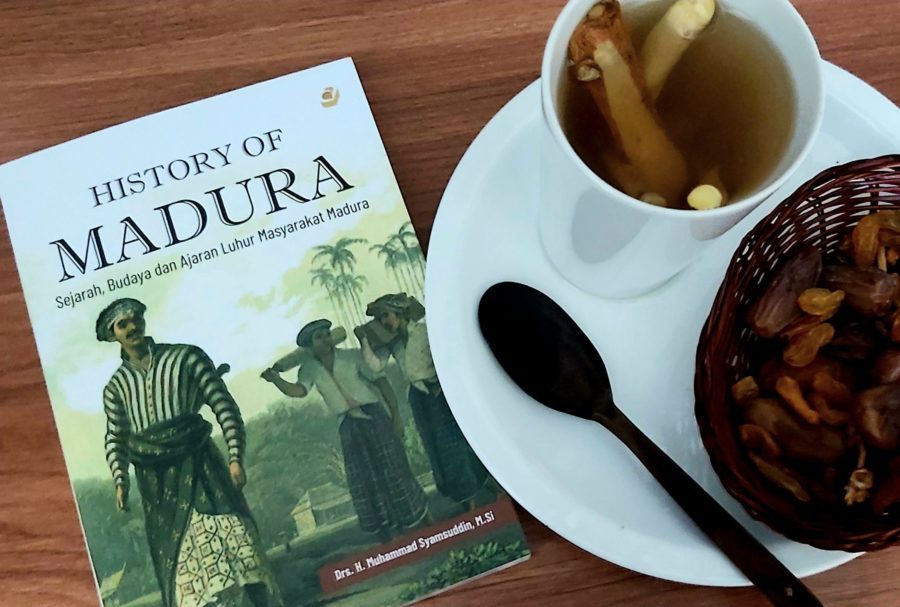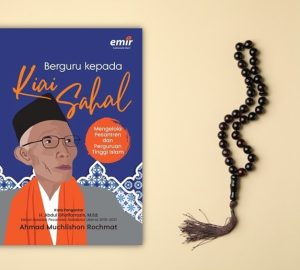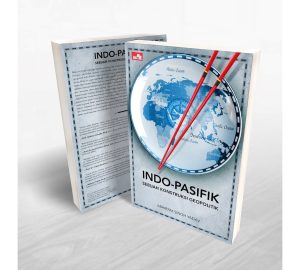Judul Buku: History of Madura: Sejarah, Budaya, dan Ajaran Leluhur Masyarakat Madura
Penulis: Muhammad Syamsuddin
Penerbit: Araska Publisher
Cetakan: 1, 2019
Tebal: 288 halaman
ISBN: 978-623-7145-35-6
Pada masa kecil, nenek sering cerita tentang dinamika kehidupan kampung. Dengan karakter apadanya, spontan, terbuka, seperti karakter-kepribadian orang Madura yang tergambar dalam buku ini, ia cerita semuanya. Mulai dari sejarah, budaya hingga ajaran-ajaran leluhur orang Sumenep, Madura.
Saat nenek, Buina, baru menikah, gejolak kontestasi politik kultural meningkat. Otoritas sosial dan politik di Sumenep pada masa itu, terjadi tindakan represif dan membuat peraturan yang tidak pro pada wong cilik.
Dalam pandulum kekuasaan hegemoni itu, yang dilakukan oleh Belanda dan disokong oleh Mantri (kaum elite), otomatis mempengaruhi pemikiran dan tindakan orang-orang Madura. Karena begitu represif, masyarakat kian takut dan patuh. Ayam-ayam kesayangan kakek (waktu zaman dulu sangat mahal) diminta oleh para Mantri, bahkan beserta telurnya. Jika menolak, maka ditakut-takuti akan dibawa ke tahanan Belanda.
Dari saking tak tahannya dengan keadaan demikian, orang-orang mulai berani melawan. Berbagai macam dilakukan, melalui negosiasi, musyawarah atau kalau tetap tidak bisa dengan sikap santun maka dilakukan dengan sikap jantan, termasuk carok.
Carok bagi banyak orang dianggap budaya kekerasan. Sebab, budaya ini diwujudkan dalam pertarungan fisik dengan menggunakan celurit, sebuah senjata tajam khas Madura. Kalau kita mengatahui sejarahnya, tentu saja kita tidak akan menuduh dengan cerca.
Secara historis, carok sudah terjadi pada abad 18 M, masa penjajahan Belanda. Sebagaimana dikatakan Muhammad Syamsuddi dalam History of Madura: Sejarah, Budaya, dan Ajaran Leluhur Masyarakat Madura (2019), budaya carok terkandung sikap jantan dan kesatria. Sebab, dalam perang carok, ada aturannya. Disitu, harus ditentukan lapangan, jam, dan tempatnya. Carok tidak boleh asal bacok atau melukai orang. Jikapun bisa harus bermatrai.
Pada masa dulu, perang carok tidak menggunakan celurit. Di zaman Cakraningrat, Jokotole (belom ada istilah carok), perkelahian secara kesatria itu menggunakan pedang atau keris, seperti budaya Jawa. Baru setelah masuk era Sakera abad-19 (tokoh legendaris Madura), istilah carok muncul dan gegeman pedang-keris digantikan dengan celurit.
Mulanya, carok ini lahir karena politik licik Belanda. Sakera (keturunan Madura, yang lahir di kelurahan Raci Kota Bangil, Pasuruan, Jatim) sebagai orang yang sakti yang selalu melawan kediktaktoran Belanda. Sakera (yang berarti orang pejuang melawan penjajahan) sebagai orang ningrat dan tokoh Islam yang saleh, juga menjadi mandor tebu milik pabrik gula kancil Mas Bangil.
Sebagai orang yang taat agama dan memiliki rasa tanggungjawab besar terhadap pekerja, maka apa yang menimpa bawahannya patut dilidungi. Suatu ketika, Belanda ingin meluwaskan lahan tebunya. Kemudian Belanda memanfaatkan Carik Rembang (antek Belanda) untuk mencari lawan dengan cara apapun, termasuk dengan jalan kekerasan.
Melihat perilaku sewenang-wenang dari antek Belanda terhadap masyarakat, maka Sakera turun tangan, menghalangi perbuatan tersebut. Karena itu, Sakera menjadi buron Belanda. Kemudian Belanda mengancam Sakera. Jika Sakera tidak menyerahkan diri, maka ibunya akan di bunuh. Sakera membela ibunya, akhirnya Sakera menyerah dan dipernjara.
Hari demi hari berjalan. Kabar buruk terdengar Sakera. Bahwa istri tercintanya, Marlena, diselingkuhi kerabat karibnya, Brodin. Mendengar cerita itu, Sakera melarikan diri. Ketika lolos, dengan celurit andalannya, Sakera melakukan carok, menebas Brodin, si lelaki busuk yang gila perempuan. Lalu kemudian, antek Belanda, Carek Rembang dan juga menebas leher polisi Bengil (hlm. 118-123). Dari situlah lahir budaya carok sampai saat ini, yakni menjaga harkat dan martabat. Bahkan muncul semboyan “ lebih baik putih tulang daripada putih mata”.
Bagi orang Madura, istri atau perempuan adalah martabat dan harga diri seorang lelaki (suami), dan oleh karena itu, ia harus dilindungi. Dengan cara apapun, meski bertaruh nyawa. Maka tak salah jika seorang perempuan dijadikan landasan hukum bagi kehidupan sosial zaman dulu, sebab pengetahuan perempuan menyatu dalam kehidupannya. Keadilan melekat pada tubuh perempuan. Bukan Cuma di Madura, tetapi kalau kita telusuri lebih jauh, konon juga terjadi di Atena (kita bisa lihat sejarah Medusa-Kuda Pegasus). Bahwa sesungguhnya hukum dibuat untuk melenyapkan pandangan-tindakan patriarkis demi mencipta keadilan.
Saya rasa, carok itu simbol. Jika orang melakukan perilaku tercela, korupsi, kolusi, nepotisme, ekstremisme, anarkisme, penyelewengan kebijakan, dan pelecehan seksual dan seterusnya, dia dianggap bukan hanya mati secara ragawi tetapi juga secara moral.
Dalam buku, Syamsuddin seperti mengapresiasi fakta, bahwa seiring terakumulasinya pengetahuan dari perjalanan hidup manusia Madura, segalanya juga ikut terakumulasi. Dari situ pula, muncul tantangan orang Madura untuk memahami sesuatu juga harus memiliki tujuan, yakni tercapainya keadilan bagi kehidupan sosial.
Ajaran-ajaran lelehur, seperti bhuppa’, babbhu’, ghuru, rato, (menghormati-menaati bapak, ibu, guru/kiai, dan pemimpin yang adil) dan kar ngarkar colpe’ (berusaha keras sampai dapat) serta a bantal sahadat, a sapok iman, a pajung Allah (semangat keagamaan yang rasional) perlu diaktualisasikan dalam laku kehidupan. Supaya, rampa’ naong beringin korong, mendapatkan keberkahan, kedamaian, dan kesejateraan.
Tetapi, kalau sekedar berfokus pada efisiensi untuk mendapatkan atau mengerjakan sesuatu, seperti kata Hebermas dalam The Theori of Commucative Action (1984), bisa memunculkan berbagai masalah sosial. Dengan demikian, kita patut mempertanyakan ‘bagaimana’ tujuan bisa dicapai, dan mengapa tujuan itu harus dikejar, serta apakah tujuan itu mesti ‘harus’ dikejar?
Mengejar sesuatu tidak mesti harus tercapai dengan cepat, tetapi bagaimana ia mencari dengan cara-cara yang baik dan tidak tercela. Kalau memakai perspektif Madura, memandang-mengejar sesuatu harus dengan kacamata saudara, yakni semuanya harus dianggap taretan dibi’. Dengan menganggap semua manusia adalah tertan dibi’, maka akan muncul kesadaran persaudaraan, kemanusiaan, kerendahatian dan keadilan. Dari situ ‘bagaimana’ harus terhubung dengan ‘mengapa’ dan ‘seharusnya’ dalam satu sistem nilai: taretan dibi’.
Sebagai suatu karakter orang Madura, meski beda starata sosial, baik dari kelas sentana (bangsawan), mantri (kelas elite) dan abdi (kaum bawahan), atau bahkan berbeda suku, agama, negara, tetap harus berkomitmen menjaga persaudaraan. Sebab, dalam settong dara atau dalam satu komitmen persaudaraan, akan meneguhkan kekuatan moral dan meningkatkan integritas kenusantaraan serta kemanusiaan.
Kemauan bersaudara, adalah salah satu amal saleh yang amat mulia, seperti dianjurkan dalam firmanNya (al-Hujarat, 48:10), bahwa semua manusia itu bersaudara. Maka sudah benar, orang Madura menganggap semua manusia adalah saudara sendiri, taretan dibi’. Jika terjadi konflik antar mereka, maka perlu diupayakan uslah atau perdamaian.
Karena itu, semua ajaran-ajaran leluhur Madura adalah lokus penting untuk melihat bagaimana tata cara hidup orang Madura. Juga, sebagai tetirah menjalani hidup seadanya (zuhud). Jika dikembangkan sikap itu, maka orang tidak mudah ngoyo, tidak rakus harta, tidak rakus kekuasaan, tidak rakus status sosial, dan tidak rakus seksual. Kehidupan dan rezekinya terasa nikmat yang diberikan oleh Tuhan.
Membaca buku ini, seperti membaca Madura. Tapi, Madura tak sepenuhnya ada dan terbaca dalam buku ini. Oleh karena itu, butuh pendalaman lagi untuk melihat Madura. Supaya bisa memahami akar identitas dan tidak mengulangi apa yang sudah ada dan tidak menggantung di tinjauan tafsir filosofi yang kering. Meski demikian, buku ini dapat menyumbang literatur dan bisa memahami bahwa tradisi pada dasarnya adalah perwujudan dari aktivitas sistemik, dari bentuk pengalaman, pengatahuan ataupun nilai-nilai. Dan bisa menyingkap banyak kesalahpahaman tentang Madura[]