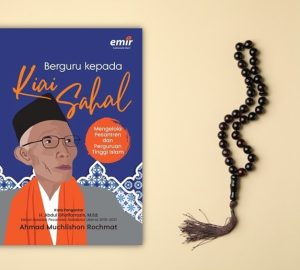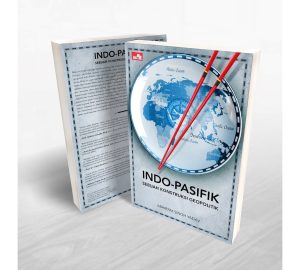Judul : Tuhan dan Hal-Hal yang Tak Selesai
Penulis : Goenawan Mohamad
Penerbit : Diva Press
Cetak : Januari 2019
Tebal : 200 halaman
ISBN : 978 602 391 660 3
Pada 1964, ia tak menulis puisi politik penuh marah dan gerah. Situasi Indonesia sedang gaduh, menempatkan orang di sesak slogan, pidato, atau perintah. Di puisi, ia masih mungkin menepi dari tuntutan-tuntutan politik minta ramai. Ia berpuisi pepohonan, waktu, dan Tuhan. Puisi berjudul “Hari Terachir Seorang Penjair, Suatu Siang” mungkin bukan puisi terapik dari Goenawan Mohamad. Puisi itu sudah jarang terbaca.
Puisi dimuat di buku berjudul Pariksit (1971), buku tak pernah cetak ulang gara-gara Goenawan Mohamad mengaku jemu dan malu. Kita simak puisi menjelang tahun-tahun tercatat sebagai petaka, 1965-1966. Pada detik-detik panas dan semrawut, Goenawan Mohamad menulis: Di siang suram bertiup angin. Kuhitung pohon satu-satu/ Tak ada bumi jang djadi lain: daunpun luruh, lebih bisu/ Ada matahari lewat mengendap, djam memberat dan hari/ menunggu/ Segala akan lengkap, segala akan lengkap, Tuhanku.
Suasana di puisi mengena bagi orang turut mengalami tahun mengandung dusta dan kecewa. Ia memilih bicara pada Tuhan, enggan memberi kata ke penguasa atau orang-orang melulu terpikat politik. Pada bait lanjutan: Kemudian Engkaupun tiba, mendjemput sadjak jang tak tersua/ Kemudian haripun rembang dan tanpa tjuatja/ Siang akan djadi dingin, Tuhan, dan angin telah sedia/ Biarkan aku hibuk dan tjinta berangkat dalam rahasia.
Puisi digubah dan terbit, sebelum rambut Goenawan Mohamad beruban dan wajah mulai pamer kerut. Kini, ia menua di tahun keras dan ganas. Ia tak mengulangi menggubah puisi seperti masa 1960-an. Ia tetap memilih puisi meski tak setekun masa lalu.
Pada 2019, puisi itu terbaca (lagi) dengan lirih dan menghindari kecerewetan berpolitik. Semua terus bicara berdalih demokrasi, tak sungkan mengucap atau berseru Tuhan dengan nada meninggi. Goenawan Mohamad masih ingin menghitung pohon, hari, dan rahasia. Ingin itu seperti tindakan menjauhi politik meski ia malah tampak semakin menanggapi politik.
Pada 2019, Goenawan Mohamad memberi petuah-petuah bukan puisi-puisi ketuhanan. Ia sadar berada di “siang akan djadi dingin” oleh kegugupan berpikir dan kesembronoan mengumbar bahasa. Ia ingin “menghangatkan” hari-hari sampai ke hari berdemokrasi. Petuah-petuah itu terkumpul di buku berjudul Tuhan dan Hal-Hal yang Tak Selesai.
Buku pernah terbit pada 2007, mengalami ralat untuk terbaca dengan suasana berbeda di tahun penuh slogan dan kebohongan. Ia absen sejenak dari puisi tapi memberi suguhan puitis bagi pembaca tekun merenungi tatal demi tatal berjumlah 99 dalam 200 halaman.
Di tatal 13, Goenawan Mohamad memberi percik renungan: “Tidak jelas bagaimana Dia dulu datang kepada kita dan bagaimana nama-Nya melekat. Mungkin itu tanda bahwa yang-transenden telah menembus batas yang-imanen; bahwa yang-ilahi telah merasuki sejarah, sering melalui tikungan dan berputar. Kita tidak bisa hanya punya satu cerita. Setiap momen adalah interpretasi yang tidak dapat diulang. Tuhan tidak berbicara dalam klise.”
Pemberhentian kita di renungan itu agak mengoreksi politik dan zaman bertaburan klise. Kita mengingat kehadiran Tuhan, mengingat titah bercerita tanpa klise-klise dalam raihan pamrih-pamrih picisan, dari duit sampai kekuasaan. Pada cerita-cerita, manusia menugasi diri di semaian iman dan pembuktian janji kemanusiaan.
Orang-orang mungkin enggan memungut renungan demi renungan saat Indonesia sedang dirundung komentar-komentar tak keruan, bukan cerita-cerita ke terang. Pada detik-detik berputar, orang-orang mengumbar segala klise kebebalan dan mengajak konfrontasi tak beradab. Mereka mengadakan bualan-bualan dan fitnah-fitnah tak memberi panggilan ke sejarah dan penentuan masa depan. Mereka mengelabui orang-orang masih mengingat-menemui Tuhan dengan wajah semringah dan bahasa elok seperti daun-daun terberkati.

Kisruh berkaitan demokrasi menimpakan agama ke keruh pemahaman dan amalan. Agama dipaksa menjadi pembenaran dari siasat berpolitik dan meninggikan gengsi bercap keislaman. Agama terlalu jauh dari hening dan bening. Goenawan Mohamad pun mengingatkan: “Agama dimulai dari hening dan saat yang dahsyat dan berakhir dengan konstruksi.” Ia tak sedang memberi ceramah atau kuliah di hadapan orang-orang merindui tata cara beriman di kedalaman makna. Agama semakin “dipersempit” gara-gara kemauan politik.
Di tatal memaknai manusia dan agama, Goenawan Mohamad ingin mengembalikan keberterimaan kita pada agama tanpa tumpukan kolot dan fanatik-mengeras. Kita mungkin diingatkan lagi larik lama buatan Goenawan Mohamad: “Tuhan, kenapa kita bisa bahagia?” Larik dari tahun 1971 itu gampang berubah di masa sekarang menjadi kebalikan: “Tuhan, kenapa kita bisa sulit bahagia dengan ketetapan agama di mata tertutup?”
Kita sampai pula di renungan demokrasi, diundurkan jauh ke abad-abad silam saat demokrasi bergerak di Prancis bersebaran ke Eropa, Amerika, dan Asia. Demokrasi bermula dari adegan-adegan mencekam di Prancis, dikenang dengan revolusi. Goenawan Mohamad memberi tafsir di babak permulaan demokrasi sedang bersemi: “Maka lahir pikiran-pikiran politik yang tajam, media massa yang tak terkekang, pasar yang sibuk, ekspresi yang bebas di pelbagai lapangan hidup.
Risalah ilmiah, laporan jurnalistik, karya sastra yang menyampaikan kesunyian dan protes, ilmu yang menemuciptakan hal baru dan menangkis pengetahuan lama–semua itu bermula dari kesadaran, mungkin juga keresahan, bahwa sang penghulu yang juga sang penentu akan selalu dipenggal.” Situasi di Prancis masa silam tak pernah berulang di Indonesia. Kini, demokrasi di Indonesia disesaki kebebalan dan kemarahan tak pernah argumentatif. Demokrasi tak bermula dari gemetar tapi benci dan penghinaan.
Demokrasi di penghitungan, bukan di renungan. Kita memilih jadi pembaca ketimbang capek memanen gosip dan fitnah politik. Kita membaca sampai ke tatal 84 memuat petikan tanggapan atas risalah mencengangkan buatan Francis Fukuyama. Goenawan Mohamad menulis: “Ini abad ke-21. Kita hidup dalam sebuah zaman yang makin menyadari ketidaksempurnaan nasib.” Petikan itu mengalami pengecilan makna saat orang gampang jatuh di kalah: “nasib”. Kita tak ingin mengeluh “nasib” di sempit makna Tuhan dan agama saat nalar picik berpolitik melanda setiap hari. Begitu.