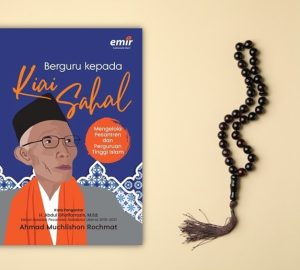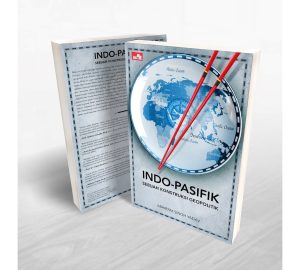Madura sering diproyeksikan dengan carok, sate, dan karapan sapi. Itu Madura di luar. Membincang Madura sebagaimana daerah lain, tentu tidak akan ada habisnya. Iya mengalir. Mencari muara-muara baru. Meskipun, pada dasarnya Madura di ruang lain masih beku, kaku dan barangkali juga tradisional.
Lanskap Madura yang jauh dari hiruk-pikuk tradisi modern bisa kita jumpai pada karya Royyan Julian. Buku Madura Niskal (2022), menghadirkan wajah Madura yang berbeda. Madura yang bukan lagi sekadar hidup dan tumbuh di pinggiran. Sebagaimana diperlihatkan oleh teman-teman sastrawan, budayawan dan penyair. Yang justru mengidentifikasi kultur Madura cukup tunggal. Royyan menyebut mereka sebagai pegiat kebudayaan yang memikul beban tradisi.
Gejala beban tradisi ini muncul di era modern. Di mana setiap elemen tradisi yang dihadirkan ke permukaan mengadopsi simbol-simbol masa lalu. Sepertinya mereka absen terhadap wacana yang berkembang belakangan. Persoalan-persoalan sosio-politik perkotaan, misalnya, nyaris tidak disentuh. Membaca Madura, iya mengulang pembacaan atas teks-teks dan tradisi pedesaan dan pinggiran.
Royyan dalam esai berjudul Tidak Mencari Madura yang Hilang dengan hati-hati menyoroti pergulatan tentang kemaduraan. Karya-karya seni dan sastra punya kecenderungan memotret tradisi masa lalu, dan enggan untuk mengadopsi tradisi luar. Seperti contoh, sapi dalam imajinasi masyarakat Madura bukan hanya hewan yang hampa makna. Iya, beralih menjadi hewan yang menyandang simbol kebudayaan superior, mempunyai kedigdayaan. Di sinilah Royyan menyebut sebagai gambaran dari pentingnya merawat identitas etnis dan menjaga kebudayaan tradisional (hlm. 124).
Sekali lagi, Madura hidup dalam tradisi organik. Mengisi ruang-ruang kosong dari kebudayaan lain. Bukan semata-mata menikmati romantisme dengan kebudayaan dan tradisi masa lalu, apalagi abai pada perkembangan hari ini. Kita bisa menjumpai karya-karya sastra yang masih berkelindan dengan persoalan keluhuran tradisi seperti kesakralan tanah, carok, maskulinitas, dan seterusnya. Yang semua itu, tentu terjebak pada beban tradisi.
Royyan sebagai orang yang tumbuh dan berkembang di Madura, tentu ingin menulis dan berbicara tentang Madura bukan sekadar Madura yang kebanyakan ditulis oleh lain. Melainkan Madura dengan kekayaan budaya dan tradisinya mampu berbicara sesuai dengan konteks zamannya.
Keberadaan buku ini, tentu menjadi semacam penyeimbang dari wacana yang jamak ditemukan dalam karya orang-orang Madura sebelumnya. Di mana Royyan menemukan diskursus dalam kosmologi tanah Madura. Tanah bukan hanya unsur ekosistem, dan penyambung hidup belaka. Lebih jauh, tanah bagi masyarakat Madura mampu menghubungkan antara yang hidup dengan yang berada di alam baka.
Belakangan, kita melihat karya-karya sastra, seni pertunjukan dan seni rupa yang mempunyai kecenderungan pada romantisme tradisi. Tapi, sayangnya, hal itu tidak disadari. Berada di kutub mempertahankan tradisi yang dianggap sakral. Sehingga menyeret beban tradisi ini jauh ke masa lalu. Memandang atribut dan simbol masa lalu sebagai yang mutlak. Akhirnya, kebas dari perubahan. Membelenggu kebudayaan yang organik. Lihat misalnya teater-teater kontemporer yang asyik dengan properti tradisional Madura: celurit, lesung, atribut sapi dan sebagainya (hlm. 129).
Royyan tak tanggung-tanggung mempertanyakan pola pikir yang demikian. Keluar dari kebiasaan mencitrakan Madura yang tradisional, bukan semata-mata melupakan kulit dan terjangkit penyakit kebarat-baratan. Melainkan sebagai upaya mengawinkan antara yang tradisional dengan perubahan di era saat ini. Barangkali seperti prinsip NU ‘al-muhafadhatu ‘ala qadimis shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah’, memelihara tardisi lama yang baik dan terbuka terhadap perubahan yang lebih baik.
Bagi saya, Madura tidak harus melulu tentang tradisi lokal, karena Madura cukup kompleks. Jika boleh jujur, ada banyak persoalan yang sedang dan akan dihadapi masyarakat Madura. Wacana alih fungsi lahan, maraknya tambak udang dan yang akhir-akhir ini lagi naik daun Madura dicanangkan jadi provinsi. Persoalan-persoalan ini masih sedikit dibicarakan, meskipun ada toh masih kalah dengan Madura yang seperti dalam puisi-puisi D. Zawawi Imron. Madura yang di dalamnya terdapat taman firdaus. Padahal, nyatanya tidak sedemikian.
Lebih jauh, Royyan dengan hati-hati mencoba menggiring pembaca untuk melihat Madura lebih jujur. Ketika memang butuh pembangunan pariwisata, misal, kenapa mesti harus memaksakan diri meniru Bali? Padahal alam di Madura tidak menawarkan lanskap keindahan. Tetapi di sisi lain, Madura memiliki kebudayaan yang khas. Apalagi hal ini dikembangkan pada sektor pariwisata berbasis kebudayaan akan menghindarkan kita dari eksploitasi alam demi hasrat industri (hlm. 132). Lagi-lagi peluang ini tidak dimanfaatkan dengan baik.
Untuk menjaring wisatawan datang ke Madura. Kita hanya butuh serius menggarap arsitektur perumahan dan permukiman khas taneyan lanjang menjadi perkampungan tradisional, makan-makan keramat dan tradisi lokal tidak hanya berada dalam dunia abstrak, tetapi berwujud wisata religi dan kampung seni. Kerja-kerja semacam ini tentu butuh waktu. Membicarakan Madura di masa depan merupakan tugas berat. Tapi, melihat Madura yang terus bergerak dan berdialog dengan kebudayaan lain, tentu menjadi kabar baik.
Judul : Madura Niskala
Penulis : Royyan Julian
Penerbit : BASABASI
Cetak : Januari 2022
Tebal : 168 halaman
ISBN : 978-623-305-260-3