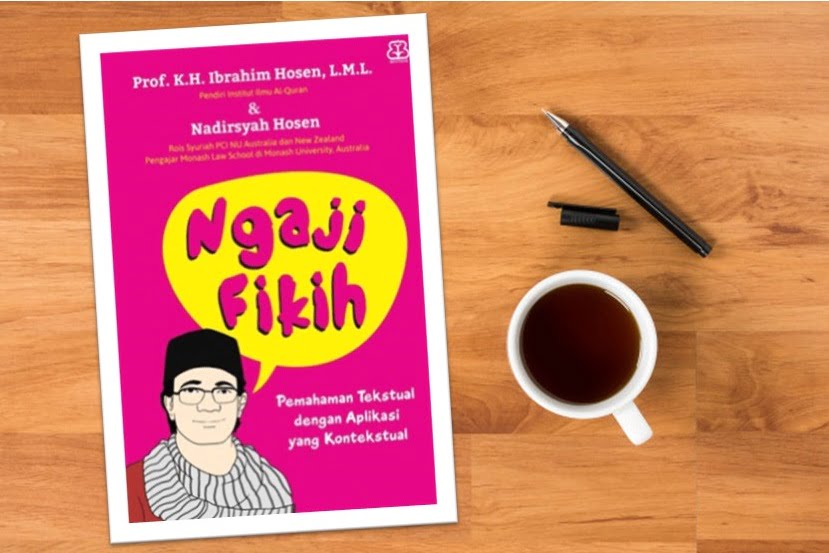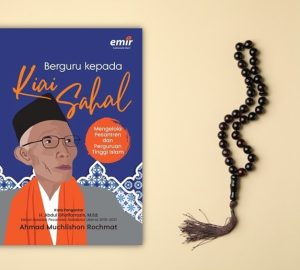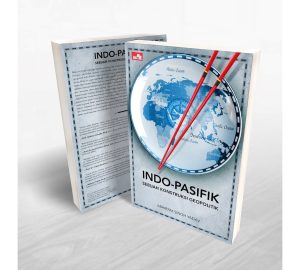Selama ini, kita mengenal Fikih dengan arti sebuah tatanan hukum yang diistinbatkan dari sumber-sumber Islam. Fikih sendiri merupakan manifestasi Islam dalam mengatur tatanan kehidupan manusia. Sebab itupula, Fikih sering disebut sebagai hukum Islam.
Menurut Yusuf Qardhawi hukum Fikih berbeda dengan hukum syariat. Hukum syariat memiliki pengertian sebagai ketentuan-ketentuan Islam yang jelas dan rinci yang terkait erat dengan wahyu Ilahi. Atau lebih ringkasnya aturan yang bersumber dari nash qathi’ (dalil yang jelas). Sementara hukum Fikih adalah aturan hukum yang bersumber dari nash zhanni (dalil yang samar).
Contoh sederhananya begini, dalam Islam judi itu dilarang, nasnya qath’i dan ini merupakan syariat. Namun, apa yan disebut dengan judi itu? Apakah lotre termasuk dalam kategori judi? Inilah wilayah Fikih untuk menjelaskannnya.
Contoh lainnya adalah Islam melarang riba, dilihat dari dalil, ini termasuk nash qath’i dan tidak ada ulama yang memperbolehkan riba. Tetapi, apakah bunga bank termasuk riba? Para ulama berbeda-beda pendapat mengenai hal tersebut, dan ini masuk dalam wilayah Fikih.
Oleh sebab itu, Fikih merupakan hasil produk dari proses ijtihad ulama dalam menghadirkan Islam dengan sebentuk tatanan hukum. Tentunya hal ini tidak lepas dari adanya dialektika antara teks dan realita dalam istinbatnya. Dari sini dapat dipahami bahwa hadirnya Fikih merupakan respon agama terhadap realitas kehidupan manusia.
Namun problem yang dihadapi Fikih selama ini adalah hukum Fikih selalu berorientasi ke atas, artinya orientasi hukum Fikih selama ini hanya ditunjukkan kepada Tuhan. Misalnya ketika kita mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, seolah-olah yang kita lakukan adalah untuk kemaslahatan Tuhan. Padahal Allah swt. sendiri tidak butuh atau tidak untung atau rugi terhadap apa yang kita lakukan.
Problem mendasar inilah yang dibawa oleh Nadirsyah Hosen dalam bukunya berjudul Ngaji Fikih: Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi yang Kontekstual. Menurut Nadirsyah, Implikasi yang kita kerjakan bukan untuk Tuhan, melainkan untuk kemaslahatan kita sendiri. Dengan demikian lanjut Gus Nadir, bila suatu ketentuan hukum tidak sesuai dengan kemaslahatan kita, maka ketentuan hukum tersebut harus dinomer duakan.
Pendek kata, setiap ketentuan yang telah digariskan Tuhan dipahami bukan sebagai beban kepada manusia melainkan sebagai kebutuhan manusia. Ketentuan dalam nas haruslah dipahami sebagai bentuk standar yang harus selalu dirujuk dalam rangka proses menuju Ilahi, bukan sebagai standar yang harus apa adanya yang diterapkan tanpa peduli dengan kondisi kita (hlm. 59).
Dengan Fikih yang berwajah humanis ini, intelektual NU sekaligus pengajar Monash Law School di Monash University Australia ini, menghindarkan kita dari klaim-klaim yang tidak perlu dalam cara keberagamaan kita. Klaim-klaim seperti alim, sesat, ingkar, paling benar, dan lainnya dapat diminimalisasi.
Gus Nadir mencontohkan, seseorang yang tinggal di sekitar masjid dan selalu mengikuti shalat berjamaah lima waktu dengan tepat waktu. Lalu kita pandang ia sebagai orang alim.
Berbeda dengan contoh itu, bagi fikih humanis, seorang manajer yang bekerja di lingkungan non Islami dan jauh dari tempat ibadah, serta benar-benar dikejar waktu dalam kerjanya selalu menyempatkan dirinya untuk shalat lima waktu, namun ia hanya dapat melaksanakan paling tidak dua waktu, dipandang lebih alim daripada contoh sebelumya.
Menurut Gus Nadir, hal tersebut disebabkan orang yang tinggal di sekitar masjid tidak perlu pengorbanan untuk selalu hadir shalat lima waktu. Hal itu berbeda dengan manajer itu yang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin menjalankan lima waktu, tapi hanya sempat dua atau tiga waktu, sesekali pernah juga lima kali. Manajer ini membutuhkan pengorbanan yang begitu besar untuk mengerjakan perintah Tuhan tersebut.
Lebih lanjut Gus Nadir mengungkapkan bahwa ketentuan dalam nash dilihat sebagai proses bukan hukumnya itu sendiri. Fikih berwajah humanis ini juga tidak melihat kasus-kasus yang terjadi dan generalisasinya. Seperti tidak diberlakukannya hukum potong tangan bagi pencuri dengan alasan tertentu dan menggantinya dengan hukuman tahanan.
Begitu pula contoh seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya. Perempuan ini tidak mempunyai pekerjaan dan keterampiran, sehingga dengan amat terpaksa menjual dirinya (melacur) demi menghidupi anaknya.
Fikih berwajah humanis tidak serta menyalahkan perempuan tersebut. Boleh jadi, dosa dan sanksi ditimpakan kepada suaminya yang meninggalkan dirinya. Apalagi suami tersebut tidak tahu di mana keberadaannya. Boleh jadi dosa tersebut ditimpakan kepada kita, sebagai dosa komunal, yang bertanggung jawab atas ketimpangan sosial yang terjadi.
Inilah fikih humanis. Fikih yang memihak pada sisi kemanusian kita. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah haruslah dipahami dalam kerangka kemanusiaan kita. Gus Nadir menilai, dengan cara ini kita dapat membumikan Fikih. Perubahan orientasi hukum Fikih semacam ini akan melahirkan hukum yang situasional, subjektif, dan individual, serta kondisional dengan semangat menuju kehendak Ilahi.
Terlepas setuju atau tidaknya dari contoh-contoh kontroversial yang dikemukakan oleh Gus Nadirsyah Hosen, pada intinya buku Ngaji Fikih ini mencoba untuk menjadikan manusia sebagai titik sentral fikih, bukan Allah. Waallahu ‘Alam
Judul Buku: Ngaji Fikih: Pemahaman Tekstual dengan Aplikasi yang Kontekstual
Penulis: Nadirsyah Hosen
Penerbit: Bentang
Tahun: Mei 2020
Tebal: xiv + 446 halaman
ISBN: 978-602-291-703-8