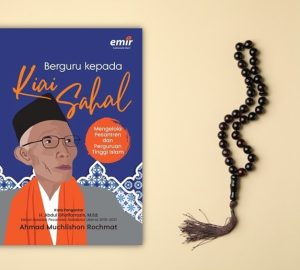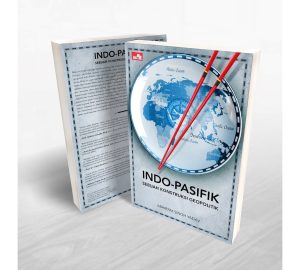Judul Buku: Ingin Saleh Boleh Merasa Saleh Jangan
Penulis: Abd. Halim, dkk.
Penerbit: Sulur Pustaka
Cetakan: 1, Mei 2020
Tebal: 234 halaman
ISBN: 978-603-5803-87-1
Di tubuh umat Islam sedang menyiratkan dua pergulatan ideologi besar. Pertama, kelompok indigenous Islam Indonesia yang memandang pentingnya “Indonesianisasi Islam”. Kedua, kelompok non-indigenous Islam Indonesia yang memandang perlunya “Islamisasi Indonesia” melalui jaringan transnasionalnya secara global. Kesimpulan itu ditarik Toto Suharto dalam teks pidato pengukuhan guru besarnya, Remoderasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Tantangan Ideologis (2020).
Fenomena itu menjadi identifikasi yang khas dan dapat melahirkan teoritas bahkan tantangan. Lebih jauh, ia juga memengaruhi laku dan perubahan pamahaman umat Islam dalam beragama. Perubahan itu lalu dicoba disorot dan dijawab oleh beberapa penulis dalam buku Ingin Saleh Boleh, Merasa Saleh Jangan (2020).
Abd. Halim, misalnya, melihat cara pandang dan laku umat Islam, khususnya anak muda cenderung reformalis. Mereka ingin saleh, tapi karena tidak mendalami agama, mereka kadang memaksakan syariat dan membangun garis damarkasi, lalu merasa saleh. “Pada era sekarang, banyak pemuda/i muslim memiliki semangat hijrah dalam rangka menjadi pribadi saleh dalam pengamalan ajaran Islam. Hanya saja, terkadang sikap semangat berhijrah hanya ditampilkan dengan perubahan busana dan penampilan. Gerakan hijrah yang masif, ditambah banyak artis mendeglarasikan diri di media sosial bahwa mereka telah berhijrah,” tulis Halim.
Ia bahkan menyebut orang mengharuskan saleh boleh, tapi merasa saleh jangan. Sikap buruk dan hina dan butuh kepada Tuhan adalah sifat menghamba. Sedangkan sikap mulia dan agung itu adalah sifat Tuhan. Sehingga tidak ada ketaatan yang menimbulkan merasa mulia dan agung. Kita tahu, tawadhu’nya orang bermaksiat dan perasaan hina, merasa takut kepada Allah, lebih baik daripada takabburnya orang alim atau orang yang ahli ibadah.
Jalan beragama seharusnya meniru Nabi Muhammad. Mendahulukan kebijaksanaan pada orang lain daripada diri sendiri. Bersikap adil kepada semua umat, termasuk kepada orang yang tidak meminta melakukan keadilan. Belajar dan menyampaikan ajaran agama dengan cara yang sesuai kondisi dan situasi yang didakwahinya. Nabi mencintai kedamaian dan melarang kekerasan dalam beragama. Serta menghargai keragaman. Berdakwahnya Nabi selalu dilandasi kasih sayang dan kecintaan kepada semua kaum manusia.
Hingga suatu ketika, dalam berdakwah Nabi mendapat gangguan dari kaum musyrik, dan karena itu sahabat meminta agar Nabi berdoa kepada Allah supaya mereka di azab. Tapi Nabi menjawab dengan bijak, “Saya tidak diutus oleh Allah untuk melaknat manusia tetapi untuk mengasihi manusia”. Jika berdakwah menggunakan kata-kata kasar, menebar kebencian, maka terlalu jauh kita berjarak pada ajaran Nabi.
Keberjaraan pada tuntunan Nabi, sungguh menjadi ruang lebar yang sesegara disergap oleh kelompok fundamentalis fanatik. Peluang itu pada akhirnya membuka pintu hadirnya “paham baru” yang terpaksa dimasuki ajaran-ajaran populis. Jangankan pendalaman agama yang menjadikannya rahmah, bahkan terbuka dan santun-toleran terhadap yang beda paham pun akan sulit terjadi. Pada akhirnya, resistensi dalam tubuh Islam justeru akan (kembali) menguat.
AE Priyono dalam prakata teks akademisnya buku Kuntowijoyo Paradigma Islam: Intrepretasi Untuk Aksi (2017), lebih dulu mencatat gejala itu. Bahwa dalam tubuh umat Islam mengalami tiga kecendrungan: pertama, mengalami koservatisasi, menjadi pasif secara sosial, dan mengambil jalan eskapis. Kedua, bergerak menjadi bagian dari radikalisasi global, menjadi bagian dari wacana Islam transnasioal dan cenderung a-nasional; ketiga, terjebak pada status-qou. Tapi eksistensi muslim hari ini lebih jauh dari itu, ia mengadaptasi pada iklim teknologi digital. Digital mendapatinya menjadi dunia baru dan karena itu, ia digunakan untuk merakit realitas artifisial keagamaan mereka.
Dalam pandangan Abraham Zakky Zulhazmi, pengajar komunikasi dan penyiaran Islam (KPI) IAIN Surakarta, dalam buku ini, sebagian umat Islam yang cenderung “hidup” di digital, ia cenderung bersikap ekslusif dan pragmatis. Dan sebab itu aktualisasi universalitas Islam menjadi terhalang. Ajaran Islam kian menyempit. Bahkan kini, bukan saja menegaskan keberjarakan atara kitab suci dan ilmu penafsiran, akal dan maqashidinya, tetapi ruang belajar seperti masjid, pondok, kampus, kiai, dosen jadi instrumen belaka. Hanya penanda identitas.
Dalam pertautan itu, Zakky menulis dengan mata KPI-nya, “Hari ini, sebagaimana kita lihat, banyak orang bergeser karena internet. Dulu orang belajar agama tidak mantap rasanya jika tidak kepesantren. Kiai menjadi sumur ilmu yang tak kering-kering. Kini, sebagian orang merasa cukup dengan hanya belajar di internet. Padahal google adalah rimba raya yang jika tak hati-hati kita akan tersesat. Kita patut khawatir, kiai-kiai dan orang-orang alim dalam urusan agama makin ditinggalkan karena orang-orang makin merasa semuanya sudah tersedia di internet”. Zakky merasa khawatir. Ia memandang hal itu sudah menguat dan akan menanjak.
Penjabaran Zakky menjelaskan kenyataan riil kepada kita, bahwa digital bisa melepaskan orang dari tatanan primordial karena sirkulasinya bukan hanya lepas dari pemiliknya melainkan menjebak mereka. Moral keagamaan terabaikan bahkan dalam kenyataannya, kasalehan ritual-sosial-virtual tidak dikenali. Digital tidak disadari bahwa ia telah ikut menghasilkan kebrutalan agama.
Namun, budaya “agamaisasi digitalitas” akan terus terjadi. Semakin banyak orang belajar agama di internet, lantas membentuk keyakinan sendiri. Mereka seperti mendapatkan pispot sebagai wadah baru: tidak peduli benar atau tidaknya ajaran itu, tidak akan mengubah keyakinannya walau dihadapkan oleh fakta yang bertentangan dengan agamanya.
Penerimaan yang bersifat emosional menjadi keyakinan yang sulit digoyahkan dengan epistemik argumen kebenaran apa pun, ketika kefanatikan menjadi sumber eksistensial. Nilai hierarki kebenaran dilihat dari banyaknya pengikut. Gempita bukan karena terbukanya nilai agama dan maksud Al-Quran, melainkan karena provokatif. Kejahilan menjadi saleh, asalkan bisa berternak ayat. Pada titik itulah, Nur Rahman, dalam buku ini ingin meredam fenomena itu.
Ia menuliskan: “Memang secara doktrin, membaca Al-Quran saja mendapatkan pahala, namun tidak cukup. Sebagai kitab yang berfungsi (hudan), kita juga harus membaca maksud dan kandungannya. Bagi masyarakat Indonesia, memahami ajaran agama dan Al-Quran bukan perkara mudah. Bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa sehari-hari kita. Selain itu, banyak kaidah lain yang dipersyarakatkan dan harus dipenuhi. Maka kita perlu membuka penjelasan para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Karena di internet dan terjemahan Al-Quran saja seringkali belum memuat makna terdalam dari Al-Quran. Oleh karenanya, ilmu tafsir dengan kaidah-kaidahnya menjadi penting dalam beragama”.
Seluruh penjelasan di atas itu, menegaskan kepada kita bahwa sebagian manusia dan umat Islam kini sedang kehilangan fundamental structure ajarannya, tapi mengambil jalan eskapis. Oleh karena itu, kita perlu radikalisasi moralisasi digital dan sosial, serta peneguhan epistemik agama, agar tercipta keutuhan ajaran yang logis. Yang pada akhirnya berpeluang menjadikan manusia saleh ritual, sosial, dan virtual.[]